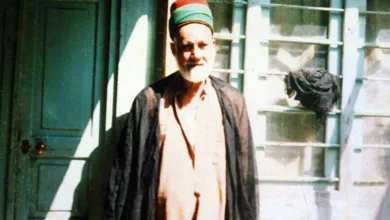CAHAYA YANG JATUH KE DALAM LAPAR: Sebuah Prosa Liris tentang Tasbih, Keheningan, dan Tubuh yang Berpuasa

Penulis: Ustadz Dimitri Mahayana, Sekretaris Dewan Syura IJABI
“Dua jiwa, ah, bersemayam di dadaku — satu ingin berpisah dari yang lain…” — Goethe, Faust
“Dan tiba-tiba aku mengerti: cinta bukan soal memiliki. Ia soal menjadi tempat pulang bagi sesuatu yang lebih besar dari dirimu.” — Haruki Murakami
“Tubuh mengingat apa yang pikiran telah lupa.” — Han Kang, The Vegetarian
“Ia tumbuh sendiri di pulau itu, tanpa guru, tanpa nama — dan pelan-pelan ia menemukan bahwa segala sesuatu adalah satu.” — Ibn Tufayl, Hayy ibn Yaqzan
I. SEBELUM KATA-KATA
Ada siang yang tidak bisa dijelaskan dengan cuaca. Bukan karena terlalu panas, bukan karena angin terlalu diam, melainkan karena ada sesuatu di dalam siang itu yang berdenyut — seperti senar yang dipetik di ruangan kosong, dan suaranya terus bergetar lama setelah jari diangkat.
Di siang seperti itu, mulut berpuasa. Perut mengenal kekosongan. Dan anehnya, justru dalam kekosongan itulah sesuatu mulai bicara. Bukan suara. Bukan bisikan. Lebih seperti tekanan — seperti tangan kasatmata yang menekan dada dari dalam, perlahan, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu di sana. Bahwa di balik semua kesibukan, di balik semua kata yang telah diucapkan dan semua makanan yang telah ditelan, ada inti yang selama ini menunggu untuk didengar.
سُبْحَانَ الضَّارِّ النَّافِعِ
Mahasuci Zat yang Memberi Mudharat dan Manfaat.
Subḥāna aḍ-Ḍārri an-Nāfiʿi. Mahasuci Dia — yang dari-Nya mengalir segala sesuatu, tanpa kecuali. Selembar daun yang jatuh tanpa pamit. Air yang menetes perlahan dari celah batu di puncak gunung yang tidak pernah dikunjungi siapa pun. Suka dan duka yang datang bergantian seperti musim yang tidak perlu meminta izin. Ada mudharat dan ada manfaat — dan keduanya, dalam seluruh paradoksnya yang membingungkan, memancar dari Satu Tangan yang sama, Satu Wujud yang tidak pernah terpecah, tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri.
Pada pengucapan pertama, zikir ini hanyalah bunyi. Pada pengucapan ke-30, ia mulai menjadi pertanyaan. Pada pengucapan ke-60, ia menjadi sesuatu yang lebih mirip napas daripada kata. Dan pada pengucapan ke-100 — aku tidak lagi tahu siapa yang mengucapkan, dan kepada siapa.
Goethe konon menulis tentang dua jiwa yang bersemayam dalam satu dada — satu ingin tinggal di bumi, satu ingin terbang ke atas. Aku mengenali keduanya siang ini. Satu bagian dariku ingin makan, ingin minum, ingin mengisi kekosongan yang terasa begitu nyata di perut. Bagian lainnya — bagian yang aneh, yang tidak pernah benar-benar bisa aku namakan — justru bersyukur atas kekosongan ini. Seolah kekosongan itu bukan kekurangan, melainkan ruang yang sengaja dikosongkan. Ruang untuk sesuatu yang lebih besar dari roti dan air.
Dan kemudian aku mengerti — atau lebih tepatnya, sesuatu dalam diriku mengerti, tanpa bisa kujelaskan dengan logika mana pun — bahwa yang tampak sebagai dua hal yang berlawanan itu sebenarnya adalah satu. Bahwa lapar dan kenyang, duka dan bahagia, yang melukai dan yang menyembuhkan, semuanya adalah tangan dari pemilik yang sama. Bahwa Ia yang memberi mudharat dan Ia yang memberi manfaat adalah Wujud yang tidak pernah terpecah. Seperti musim dingin dan musim semi yang berasal dari satu bumi yang sama.
Han Kang kabarnya pernah menulis tentang tubuh yang memberontak — seorang perempuan yang tiba-tiba berhenti makan daging, bukan karena doktrin, bukan karena filsafat, melainkan karena tubuhnya berkata sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa. Tubuh itu tahu sesuatu yang pikiran belum sampai.
Perutku yang lapar siang ini seperti itu. Ia bukan sedang protes. Ia sedang bercerita. Ia berkata: inilah rasa yang dikenal oleh mereka yang tidak makan bukan karena pilihan, melainkan karena tidak ada pilihan. Di Gaza. Di kamp-kamp pengungsi. Di lorong-lorong kota yang tidak masuk berita. Perutku yang lapar adalah jembatan kecil antara aku dan mereka — jembatan yang rapuh, ya, namun cukup untuk kulewati dengan perlahan, dengan kepala tertunduk, dengan rasa malu yang produktif.
Dan bukan hanya mereka yang hidup sekarang. Tubuh yang lapar ini juga memanggil ingatan ke depan — ke Hari ketika semua manusia akan berdiri tanpa bekal, ketika lapar dan haus menjadi ujian yang sesungguhnya, ketika segala yang pernah kita timbun tidak bisa lagi menjadi pelindung. Puasa adalah latihan untuk hari itu. Bukan latihan fisik. Latihan jiwa.
II. TENTANG MENERIMA YANG TIDAK BISA KITA PILIH
سُبْحَانَ الْقَاضِي بِالْحَقِّ
Mahasuci Zat yang Menetapkan dengan Kebenaran.
Subḥāna al-Qāḍī bi al-Ḥaqqi. Mahasuci Dia yang menetapkan segala kejadian dengan Kebenaran — bukan kebenaran yang selalu bisa kita baca dengan mata telanjang, tetapi kebenaran yang terukir di lapisan yang lebih dalam dari yang bisa dijangkau oleh kepanikan atau kesedihan kita. Semua yang terjadi — yang kita sambut dengan syukur maupun yang kita terima dengan air mata — adalah pancaran dari kebaikan-Nya, adalah pantulan dari keindahan-Nya. Sering kali kita tidak memahaminya. Sering kali kita tidak perlu memahaminya dahulu untuk bisa melanjutkan berjalan.
Murakami juga konon pernah menulis tentang seorang lelaki yang kehilangan istrinya tiba-tiba — tanpa pesan perpisahan, tanpa alasan yang bisa dipahami. Selama berbulan-bulan lelaki itu hidup di antara dua hal: keinginan untuk mengerti, dan penerimaan bahwa mungkin beberapa hal memang tidak bisa dimengerti. Dan pada akhirnya, yang menyelamatkannya bukan jawaban. Yang menyelamatkannya adalah kemampuan untuk terus berjalan meski tanpa jawaban.
Ada ketetapan yang tidak meminta persetujuan kita. Ada kehilangan yang datang tanpa surat pemberitahuan. Ada rasa sakit yang tiba-tiba sudah di dalam dada sebelum kita sempat mempersiapkan diri. Dan tasbih ini — Subḥāna al-Qāḍī bi al-Ḥaqqi — bukan perintah untuk diam. Bukan instruksi untuk menelan kepedihan tanpa nama. Ia adalah sebuah ajakan untuk melihat lebih dalam: bahwa di balik setiap ketetapan yang tampak kejam, ada Struktur Agung yang lebih besar dari pemahaman kita. Seperti bagian dari partitur yang terdengar disonan jika didengar sendirian, tetapi menjadi bagian tak tergantikan dari simfoni ketika didengar secara keseluruhan.
Marcus Aurelius, kaisar yang juga filsuf, kabarnya menulis di buku catatannya yang tidak pernah dimaksudkan untuk diterbitkan: “Engkau memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian. Sadari ini, dan kau akan menemukan kekuatan.” Bukan kekuatan untuk mengubah kenyataan, melainkan kekuatan untuk memilih respons terhadap kenyataan.
Ridha, dalam bahasa yang kita warisi dari para arif, bukan berarti pasrah seperti batu yang tenggelam. Ridha adalah aktif — ia adalah kesediaan untuk menjadi saluran, bukan sekadar wadah. Ia adalah syukur dalam segala hal, baik suka maupun musibah. Menerima bahwa musibah bukan hukuman, melainkan undangan untuk bertanya: “Apa yang bisa aku lakukan dari sini?”
Jika ada ketidakadilan di depan mata — dan ada, selalu ada — Ridha tidak berkata “sudah takdir” lalu berpaling. Ridha berkata: “Aku menerima bahwa ini terjadi, dan aku bergerak untuk menjadikannya lebih baik.” Menjadi perpanjangan dari Yang Menetapkan dengan Kebenaran, Kebaikan, dan Keindahan. Menjadi tangan-Nya yang terlihat di dunia yang sering tidak adil.
III. TETESAN DI HADAPAN SAMUDRA
سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى
Mahasuci Zat yang Mahatinggi lagi Tertinggi.
Subḥāna al-ʿAliyyi al-Aʿlā. Mahasuci Dia yang Mahatinggi — begitu tinggi hingga segala konsep yang pernah kita ciptakan untuk menjangkau-Nya hanya menyentuh bayangan dari bayangan-Nya. Dan walau hati para hamba terbakar oleh rindu yang tidak bisa mereka padamkan, walau seluruh kerinduan itu menggelegak seperti air yang mendidih dalam bejana yang terlalu kecil — Ia tetap Mahatak Terjangkau, Mahatinggi dalam segenap keluhuran-Nya yang tak berawal dan tak berakhir.
Ibn Tufayl menulis tentang Hayy — seorang bayi yang terdampar di pulau terpencil, dibesarkan oleh seekor rusa, tanpa bahasa, tanpa guru, tanpa kitab. Melalui perjalanan batinnya yang sunyi itu, Hayy sampai pada satu kesimpulan: bahwa di balik segala yang terbatas, ada Yang Tak Terbatas. Bahwa segala yang ada ini adalah pancaran dari satu Wujud yang Tunggal. Hayy sampai pada Tuhan bukan melalui kata-kata, melainkan melalui keheningan yang semakin dalam.
Lapar siang ini mengajarkan hal yang serupa. Tubuh yang terbiasa merasa cukup, tiba-tiba menyadari betapa bergantungnya ia. Pada seteguk air. Pada sepotong roti. Pada napas berikutnya yang belum tentu datang. Ketergantungan ini bukan kelemahan yang memalukan — ia adalah informasi. Informasi bahwa kita bukan asal-usul dari keberadaan kita sendiri. Bahwa kita menerima, bukan menciptakan.
Fanā’ — kata yang sering diterjemahkan sebagai “penghilangan diri” — bukan tentang menghilang. Ia tentang melonggarkan genggaman atas “aku” yang palsu, agar Aku yang sesungguhnya bisa mengisi ruang itu. Seperti tetes yang larut dalam samudra: ia tidak hilang, ia menjadi lebih besar dari yang ia pernah bayangkan.
Epictetus, yang lahir sebagai budak dan mati sebagai filsuf, mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan soal kebebasan tubuh. Ia soal kebebasan dari ilusi bahwa kita perlu menjadi lebih besar dari semesta. Dari kerendahan ini, yang lahir bukan kelemahan, melainkan tindakan — menolong yang terpinggirkan, hadir bagi yang tidak dilihat oleh siapa pun. Karena melayani mereka adalah satu-satunya cara kita bisa menyentuh Yang Tak Terjangkau.
IV. TITIK DI MANA PUJIAN BERBALIK MENJADI DIAM
سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
Mahasuci Dia dan dengan puji bagi-Nya, Mahasuci Dia dan Mahatinggi.
Subḥānahu wa biḥamdihi subḥānahu wa taʿālā. Di sini, di ujung tasbih ini, lidah sampai pada batasnya. Seluruh eksistensi kita tidak akan pernah mampu membentuk pujian yang benar-benar layak bagi-Nya. Kesadaran ini menggetarkan: bahwa seluruh pujian kita hanyalah bayangan yang sangat jauh dari Cahaya yang sesungguhnya.
Ada sebuah jenis keheningan yang lebih penuh dari suara apa pun. Murakami menulis tentang sumur — sebuah sumur gelap yang dalam, tempat seseorang turun untuk bertemu dengan lapisan dalam diri yang tidak bisa dicapai di permukaan. Di titik itu, pujian berbalik menjadi diam. Dan diam itu sendiri adalah bentuk pujian yang paling jujur.
Subḥānahu wa biḥamdihi subḥānahu wa taʿālā. Ketika kalimat ini diucapkan seratus kali, ada kesadaran bahwa kemampuan untuk memuji itu sendiri adalah pemberian dari Yang Dipuji. Bahwa kita tidak punya apa-apa — bahkan pujian pun bukan milik kita. Han Kang, dalam keheningannya yang dingin, menulis tentang tubuh yang menjadi bahasa ketika bahasa gagal. Tubuh yang berpuasa ini adalah kalimat yang tidak bisa ditulis dengan tinta.
Bayangkan bila seorang hamba mendengar bak Nabi Musa a.s. sebuah Suara Agung: “Duhai hamba-Ku, ketika Aku sakit, mengapa engkau tidak menjenguk-Ku?” Dan jawaban yang datang: “Hamba-Ku yang itu sakit. Jika engkau menjenguknya, kau akan mendapati Aku di sisinya.”
Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami dengan tubuh — dengan kaki yang benar-benar berjalan ke rumah orang yang sakit, dengan tangan yang benar-benar menyentuh tangan yang dingin. Di situlah, kata para arif, terletak Jannatul Liqā’ — Surga Pertemuan. Bukan di langit ketujuh yang jauh, tetapi di sisi orang yang paling tidak diperhatikan.

KH Jalaluddin Rakhmat berkata bahwa jalan tercepat menuju-Nya adalah perkhidmatan. Bukan ritual, melainkan tangan yang memberi, kaki yang datang, dan telinga yang mendengar tanpa agenda. Ketulusan adalah kuncinya — kebaikan yang terjadi karena ia tidak bisa tidak terjadi, seperti matahari yang tidak bisa memutuskan untuk tidak bersinar.
Dalam Stoikisme, kebajikan tertinggi adalah virtus — tindakan baik yang tidak membutuhkan pengakuan. Marcus Aurelius menulis catatan hariannya bukan untuk diterbitkan, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri. Itulah ketulusan yang paling sunyi.
KODA. SEBELUM BERBUKA
Siang ini hampir selesai. Sebentar lagi azan akan terdengar. Tubuh yang berpuasa ini akan kembali menerima makanan dan air. Tetapi sebelum itu, ada sejenak yang ingin aku jaga. Bukan karena ia istimewa, melainkan karena ia biasa. Lapar biasa. Tasbih yang diulang-ulang sampai mulut hampir lupa maknanya, lalu tiba-tiba mengerti maknanya lebih dalam dari sebelumnya.
Hayy ibn Yaqzan, setelah bertahun-tahun sendirian, akhirnya bertemu manusia lain. Ia menyadari betapa sulitnya menjelaskan apa yang ia pahami melalui sunyi. Aku mengenali kebisuan Hayy itu. Ada yang tidak bisa aku jelaskan tentang siang ini.
Hanya ini yang bisa aku katakan: bahwa lapar mengajariku tentang ketergantungan, ketergantungan mengajariku tentang kerendahan, dan kerendahan membuka sesuatu dalam dada yang biasanya tertutup. Dari lubang kecil itu, cahaya masuk — bukan dari luar, melainkan dari dalam.
Mereka yang mencapai Jannatul Liqā’ adalah mereka yang paling banyak hadir untuk manusia. Suka dan duka datang silih berganti seperti musim, dan mereka menerimanya sebagai undangan untuk melihat Tangan yang sama di balik semuanya. Terus berjalan, terus memberi, terus mencintai — bukan karena tidak lelah, tetapi karena tidak ada pilihan lain yang lebih masuk akal bagi jiwa yang telah mengenal Sumber dari segala sesuatu.
Goethe konon menulis di akhir hidupnya: “Mehr Licht” — lebih banyak cahaya. Aku berdoa semoga mereka yang berpuasa hari ini mendapatkan cahaya itu. Bukan cahaya yang membutakan, melainkan cahaya yang menghangatkan, yang membuat kita tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat mereka yang miskin, yang sakit, dan yang tak bernama. Karena di sisi mereka itulah, kata-Nya, Ia hadir. Menunggu.
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
Tidaklah taufikku kecuali dari Allah, kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali.
4 Ramadan 1447 H
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ