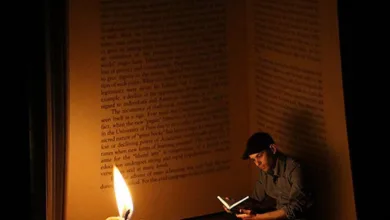Roz, si Lapar yang Diusir dari Dunia
Oleh Abdul Karim
“Aku lapar, Mama, aku ingin sekali makan yang manis-manis.” Dalam satu kalimat, Roz telah mengungkapkan seluruh paradoks kemanusiaan yang porak-poranda di Gaza. Ia tidak meminta gencatan senjata, tidak meminta pengadilan internasional, tidak menyebutkan hak asasi atau negosiasi damai. Ia hanya lapar. Dan dalam kelaparan itu ia bermimpi, bukan tentang rumah, bukan tentang sekolah, bukan tentang masa depan, tapi hanya sepotong manis-manis—yang barangkali bahkan tidak sempat pernah dikenalnya. Dunia menyaksikan tubuh mungilnya hancur bersama impiannya, hanya beberapa detik setelah ucapannya terbang bersama nyawa yang ditarik dari bumi oleh drone bunuh diri. Roz pergi, kata ibunya, Israa Abu Shawish, dalam bisikan yang lebih tajam dari ledakan mana pun: Roz sudah pergi, si lapar, si ceria, si lembut.
Tidak ada metafora yang lebih tragis, tidak ada lambang genosida yang lebih telanjang daripada kematian seorang anak yang kelaparan di tengah lautan makanan yang dijaga blokade, drone, dan kebungkaman global. Namun, dalam retorika internasional, peristiwa semacam ini kerap dibingkai bukan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, melainkan sebagai “dampak sampingan” dari pertahanan diri sebuah negara. Edward W. Said, dalam The Question of Palestine, sejak awal menegaskan bahwa apa yang menimpa rakyat Palestina bukan sekadar konflik. Itu adalah proyek sistematis penghapusan, penyingkiran, dan penghilangan dari sejarah, peta, dan kesadaran publik. Roz bukan sekadar korban perang. Ia adalah bukti hidup bahwa kolonialisme modern tidak hanya membunuh tubuh, tapi juga mimpi dan rasa lapar anak-anak.
Said menyebutkan bahwa Palestina adalah “kontes antara sebuah kehadiran dan sebuah interpretasi.” Roz adalah kehadiran itu—bukan dalam pidato politik, tapi dalam suara lirih yang menyebut ‘manis-manis’ di antara reruntuhan. Sementara interpretasi dunia, seperti dibongkar Said, justru menutupi kehadiran itu dengan narasi-narasi besar: tentang hak membela diri, tentang perjanjian damai, tentang ‘Israel sebagai satu-satunya demokrasi di Timur Tengah’. Narasi ini menjadi tameng untuk menolak mengakui realitas pahit yang dialami Roz dan jutaan anak Palestina lain yang hidup dalam pengungsian permanen.
Bagi Said, ini bukan sekadar penyangkalan, tapi pemusnahan dalam makna wacana. Roz, dalam sistem dunia hari ini, tidak ditulis dalam catatan sejarah. Ia tidak disebut dalam laporan Dewan Keamanan PBB, tidak dikenang dalam editorial surat kabar besar, tidak ditampilkan sebagai wajah dari penderitaan global. Inilah yang disebut Said sebagai “denial of presence”: sebuah bentuk paling canggih dari kolonialisme, ketika yang tertindas tidak lagi hanya dikuasai secara fisik, tapi juga dihapus dari kesadaran dunia.
Ketika Edward Said menulis bahwa “Palestinians have been known only as refugees, or as extremists, or as terrorists,” ia sesungguhnya sedang mengingatkan dunia bahwa penyempitan identitas adalah bagian dari strategi pemusnahan. Roz, dalam skema semacam ini, tidak mungkin dikenang sebagai anak kecil yang kelaparan. Ia akan ditulis, jika pun ada yang menulis, sebagai bagian dari statistik kematian sipil yang “tak terhindarkan” dalam perang. Dalam retorika seperti ini, tidak ada ruang untuk mengakui bahwa yang terbunuh bukan sekadar angka, tapi seseorang yang bermimpi makan yang manis-manis.
Said sangat kritis terhadap cara dunia, khususnya Barat, merespons penderitaan Palestina. Ia menunjuk ketimpangan dalam narasi media, yang bisa meluapkan kemarahan kolektif ketika sebuah bom meledak di pasar Yerusalem, namun tetap dingin dan netral ketika kamp pengungsi Palestina dibombardir habis-habisan. Said mengutip wawancara mengerikan dengan Jenderal Gur, yang dengan enteng berkata bahwa Israel memang menargetkan populasi sipil sebagai strategi perang. Ketika seorang jenderal dapat berbicara seperti itu dan tetap diposisikan sebagai figur keamanan yang sah, maka matilah kemanusiaan. Dan dalam dunia yang sudah kehilangan rasa malu ini, Roz hanya akan menjadi catatan kaki.
Namun Said tidak berhenti pada kecaman. Ia menulis dengan kemarahan yang terukur, kemarahan yang dibangun dari keyakinan bahwa penghapusan eksistensi Palestina adalah penghapusan atas nilai-nilai universal. Ia percaya bahwa perjuangan rakyat Palestina bukan hanya untuk wilayah geografis, tapi untuk hak dasar manusia: untuk dikenali, diakui, didengarkan. Dan kisah Roz, yang bisa saja hilang tanpa jejak jika tidak ditulis oleh sang ibu, adalah salah satu fragmen dari perjuangan besar itu.
Palestina, kata Said, menjadi lambang dari pertarungan antara interpretasi kekuasaan dan kesaksian korban. Dalam konteks ini, Roz adalah testimoni yang tidak dapat disangkal, tidak bisa dibungkam. Ketika suara Roz—“Aku lapar, Mama”—diabaikan oleh institusi-institusi global, maka suara itu justru makin menguat di hati nurani mereka yang masih bersisa rasa adil. Ia adalah jerit diam dari yang tertindas, yang menjebol semua justifikasi kekuasaan yang licin.
Jika Roz adalah simbol, maka ia adalah simbol dari anak-anak yang dilenyapkan sebelum mereka punya kesempatan menjadi sejarah. Mereka yang tidak diizinkan menulis masa depan mereka sendiri. Dan ini, dalam pemahaman Said, adalah bentuk tertinggi dari kekerasan: bukan hanya membunuh tubuh, tapi memusnahkan kemungkinan akan eksistensi, menulis ulang masa depan menjadi ruang kosong, dan mengajarkan kepada dunia bahwa ada penderitaan yang bisa dilupakan.
Said memulai bukunya dengan pengakuan bahwa ia menulis bukan sebagai pengamat netral, melainkan sebagai bagian dari sejarah yang dipertaruhkan. Dalam semangat itu, kita pun tidak bisa membaca kisah Roz dari kejauhan. Kita harus menulisnya, mengulangnya, memeluknya dengan kata-kata yang tidak membiarkannya mati dua kali—pertama oleh drone, kedua oleh lupa. Karena genosida yang paling sempurna adalah yang tidak dikenang.
Dan jika dunia hari ini masih mempertanyakan apakah benar ada genosida di Palestina, maka jawaban yang paling jujur tidak datang dari data satelit atau resolusi politik. Jawabannya ada di bisikan Israa, ibu Roz, yang memeluk tubuh anaknya yang sudah tidak bernyawa dan berkata: “Roz sudah pergi, si lapar, si ceria, si lembut.” Sebab dalam setiap luka seorang ibu Palestina, dunia yang mengaku beradab sedang ditelanjangi.
Daftar Pustaka:
Said, Edward W. The Question of Palestine. Vintage Books, 1980.

Abdul Karim
Guru matematika SMUTH 2000 - 2005 dan praktisi pendidikan matematika dan IT