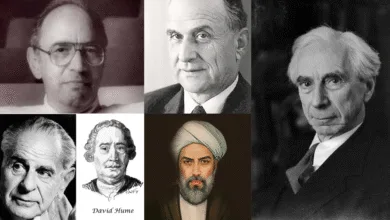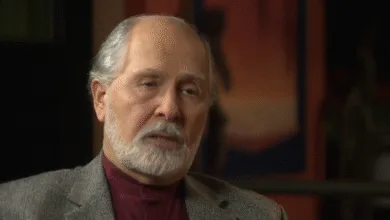Tingkatan Jiwa

Oleh Mohammad Adlany, Ph.D. (Anggota Dewan Syura IJABI)
Dalam khazanah intelektual Islam, baik dalam tradisi irfan (tasawuf filosofis) maupun filsafat, persoalan jiwa (al-nafs) merupakan tema sentral yang mendapat perhatian mendalam. Jiwa dipandang sebagai wadah bagi perjalanan spiritual (sair wa suluk) menuju Allah, dan sekaligus sebagai medan dialektis bagi pencapaian kesempurnaan insani.
Berbeda dengan perjalanan material yang menuntut perpindahan ruang, perjalanan spiritual berlangsung dalam dimensi batin manusia itu sendiri. Salik (pejalan spiritual) tidak bergerak meninggalkan dirinya, melainkan bergerak melintasi tingkatan-tingkatan jiwanya, dari derajat paling rendah menuju derajat paling tinggi. Dengan demikian, jalan, tujuan, sekaligus pejalan itu sendiri berada dalam satu entitas: jiwa manusia.
Karena itu, para arif, para filsuf, bahkan al-Qur’an menggunakan terminologi yang beragam untuk menjelaskan tingkatan-tingkatan jiwa. Perbedaan istilah tersebut mencerminkan perbedaan metodologi, tetapi secara substansial sama-sama bertujuan memetakan titik awal perjalanan jiwa dan maqam akhir yang hendak dicapai.
Tingkatan Jiwa menurut Pandangan Arif
Para arif menguraikan perjalanan jiwa dalam kerangka lathaif sab‘ah (tujuh lapisan halus jiwa). Konsep ini sering diungkapkan dalam literatur tasawuf, misalnya oleh Jami yang memuji ‘Attar Nisyaburi dengan ungkapan: “‘Attar telah melintasi tujuh kota cinta, sementara kita masih terjebak di satu lorong.”
Ungkapan tersebut merujuk pada tujuh tingkatan jiwa yang harus dilalui salik. Prosesnya bersifat gradual dan hierarkis: pencapaian suatu tingkatan hanya dimungkinkan jika tingkatan sebelumnya telah dilewati dengan sempurna. Tingkatan-tingkatan itu diibaratkan anak tangga menuju maqam tertinggi, yakni fana’ dalam Tuhan.
Menurut tradisi irfan, tujuh tingkatan tersebut adalah:
1. Badan, sebagai asal gerak dan diam di alam materi.
2. Jiwa, sebagai asal persepsi parsial.
3. Qalb (hati) atau ‘aql (akal), sebagai asal persepsi universal.
4. Ruh, yang bersifat kreatif karena berasal dari sisi Rbubiyyah.
5. Sirr (rahasia), yakni fana dalam akal aktif atau alam akal eksternal.
6. Khafi (yang tersembunyi), yakni fana dalam maqam wahidiyyah.
7. Akhfa (yang paling tersembunyi), yakni fana dalam maqam ahadiyyah. (Al-Fawa’id al-‘Amuli, jilid 1, hlm. 131)
Dengan demikian, titik awal perjalanan salik adalah tingkatan badan di alam materi, yakni kondisi manusia dalam dimensi material yang masih serupa dengan hewan: memiliki gerak dan diam, tetapi belum menampakkan kesempurnaan insani. Ia masih merupakan “hewan aktual” dan “manusia potensial”. Perjalanan spiritual kemudian menuntut pengangkatan jiwa dari derajat kehewanan menuju kesempurnaan insani, hingga mencapai fana’ dalam Tuhan.
Tingkatan Jiwa menurut Pandangan Filsuf
Para filsuf Islam, seperti al-Farabi, Ibn Sina, dan kemudian dimatangkan oleh Mulla Sadra, juga menyusun hierarki perkembangan jiwa. Mereka menjelaskan dinamika jiwa dalam kerangka epistemologis dan ontologis yang sistematis.
Sebagaimana para arif, mereka menyebutkan adanya tujuh tingkatan, yaitu:
1. ‘Aql al-hayulani (akal potensial), ketika jiwa masih kosong dari aktualitas, namun memiliki kesiapan untuk menerima kesempurnaan.
2. ‘Aql bi al-malakah (akal habitual), ketika jiwa mulai memiliki pengetahuan aksiomatis yang bersifat dasar.
3. ‘Aql bi al-fi‘l (akal aktual), ketika jiwa mampu menyusun silogisme untuk memperoleh pengetahuan teoretis dari prinsip-prinsip aksioma.
4. ‘Aql al-mustafad (akal perolehan), ketika seluruh ilmu hadir dalam jiwa sehingga ia menjadi “alam ilmiah” yang paralel dengan alam objektif.
5. Mahw (penghapusan), yakni tauhid perbuatan: kesadaran bahwa seluruh perbuatan fana dalam perbuatan Allah.
6. Thams (penghapusan mendalam), yakni tauhid sifat: kesadaran bahwa seluruh sifat kesempurnaan fana dalam sifat Allah.
7. Mahq (pelenyapan total), yakni tauhid wujud: kesadaran bahwa wujud diri fana sepenuhnya dalam wujud Allah. Artinya, ia tidak melihat keberadaan dirinya secara independen dari keberadaan Allah, bahkan ia memandang eksistensinya semata-mata bergantung dan murni terkait pada eksistensi Allah. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk seluruh selain Allah, ia tidak menemukan adanya wujud yang benar-benar dapat disebut sebagai realitas hakiki. (Al-Fawa’id al-‘Amuli, jilid 1, hlm. 132)
Jika dibandingkan dengan para arif, terlihat bahwa filsuf lebih menekankan aspek epistemologis pada empat tingkatan awal, lalu berpindah ke aspek ontologis dan teologis pada tiga tingkatan terakhir. Hal ini menunjukkan kesinambungan antara filsafat dan irfan: keduanya sama-sama menempatkan tujuan akhir jiwa pada tauhid eksistensial, meski dengan pendekatan terminologis yang berbeda.
Walhasil, baik dalam irfan maupun filsafat Islam, jiwa dipahami sebagai entitas yang memiliki dinamika bertingkat. Titik awal perjalanan selalu dimulai dari kondisi potensial yang masih terikat pada dimensi material, dan berakhir pada kondisi transenden di mana jiwa fana dalam Tuhan.
Perbedaan utama keduanya terletak pada penekanan: irfan menekankan aspek praktis-sufistik dengan bahasa simbolis (badan, qalb, ruh, sirr, dll.), sementara filsafat menekankan aspek teoretis-epistemologis (akal potensial, akal aktual, akal mustafad, dll.). Namun, keduanya bersepakat bahwa kesempurnaan tertinggi jiwa adalah pencapaian tauhid wujud, yakni penyaksian eksistensi murni Allah sebagai realitas absolut, dan kefanaan total segala selain-Nya.