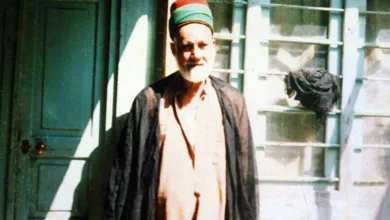Ketika Lapar Memiliki Nada Sendiri : Sebuah Renungan Kecil dari Wirid Siang Hari Bulan Puasa

Penulis: Dr. Dimitri Mahayana (Sekretaris Dewan Syura IJABI)
I. Di luar sudah tidak ada bayangan. Bukan karena mendung, tetapi karena matahari sedang tepat di atas kepala dan semua bayangan sudah menyembunyikan dirinya ke bawah benda masing-masing, seperti kucing yang bersembunyi di bawah kasur ketika ada tamu datang. Siang Ramadhan punya sifat itu—semua hal menjadi sangat diri mereka sendiri.
Aku duduk di kursi kayu tua dekat jendela dan mulai mengucapkan kalimat yang sama seratus kali. Seratus kali adalah jumlah yang aneh. Terlalu sedikit untuk menjadi meditasi, terlalu banyak untuk disebut sekadar doa singkat. Seperti mendengarkan satu lagu yang sama seratus kali berturut-turut—pada pengulangan ke-30 kamu berhenti mendengar liriknya, pada pengulangan ke-60 kamu mulai mendengar sesuatu yang lain, sesuatu di balik lirik, dan pada pengulangan ke seratus kamu tidak lagi yakin apakah kamu yang mendengarkan lagu itu atau lagu itu yang mendengarkan kamu.
سُبْحَانَ الضَّارِّ النَّافِعِ
Maha Suci Zat yang Memberi Mudharat dan Manfaat.
Kalimat itu berbunyi seperti ini di dalam kepalaku: sesuatu yang melukai dan sesuatu yang menyembuhkan berasal dari tangan yang sama. Aku tidak bisa memutuskan apakah itu menghibur atau menakutkan.
Ada seorang yang pernah aku kenal—namanya tidak penting, atau mungkin sudah aku lupakan, atau mungkin memang tidak pernah ada namanya dalam cerita yang sedang aku tulis ini—yang berkata kepadaku suatu sore: “Hal-hal yang menyakitimu dan hal-hal yang menyelamatkanmu sering kali adalah hal yang sama. Tergantung dari jam berapa kamu melihatnya.” Aku waktu itu berpikir dia sedang bicara tentang kopi. Sekarang aku tidak begitu yakin.
Lapar di siang bulan Ramadhan ini punya kualitas yang sama. Ia tidak menyenangkan dengan cara yang sederhana, tetapi ia juga tidak tidak menyenangkan dengan cara yang sederhana. Ia ada di antara keduanya, di wilayah abu-abu yang luas dan sunyi, tempat di mana kebanyakan hal yang penting dalam hidup berlangsung tanpa banyak penonton. Perutku berbicara dengan bahasa yang tidak menggunakan kata-kata. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku mendengarkan.
Yang ia katakan, kalau aku terjemahkan sebaik yang aku bisa, adalah ini: ingatkah kamu bahwa ada orang-orang yang merasakan ini bukan karena pilihan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa dimakan? Di Gaza. Di tempat-tempat yang kamu lewati dalam berita dan langsung kamu scroll ke bawah karena terlalu berat untuk ditonton sebelum sarapan. Di lorong-lorong yang tidak punya nama di peta mana pun. Perutku yang lapar adalah jembatan kecil. Rapuh, ya. Tidak nyaman, ya. Tetapi cukup untuk dilewati—kalau kamu mau repot-repot melewatinya.
II. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku kendalikan. Ini bukan penemuan baru. Tetapi setiap kali aku mengucapkan kalimat itu, ia terasa seperti baru ditemukan lagi—seperti kacamata yang sudah kamu cari setengah jam tetapi ternyata ada di kepalamu sendiri.
سُبْحَانَ الْقَاضِي بِالْحَقِّ
Maha Suci Zat yang Menetapkan dengan Kebenaran.
Aku memikirkan seorang lelaki yang pernah aku baca tentangnya—atau mungkin dia tokoh fiksi, aku tidak selalu bisa membedakannya—yang kehilangan seseorang secara tiba-tiba. Tanpa peringatan. Tanpa kesempatan untuk bersiap. Selama berbulan-bulan sesudahnya ia hidup seperti orang yang sedang mencari sesuatu di dalam rumah gelap, tidak tahu apa yang dicari, tidak ingat di mana terakhir kali menaruhnya. Yang menyelamatkannya bukan jawaban. Tidak pernah ada jawaban yang memuaskan untuk jenis kehilangan itu. Yang menyelamatkannya adalah kemampuan untuk terus berjalan di dalam rumah gelap itu—sambil perlahan-lahan mulai menghafal letak furniturnya, supaya ia tidak terus-terusan menabrak sudut yang sama.
Ridha, menurutku, adalah sesuatu seperti itu. Bukan diam. Bukan menerima dalam pengertian membiarkan segalanya terjadi tanpa bergerak. Tetapi semacam berdiri tegak di dalam sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, dan dari posisi tegak itu, mencari apa yang masih bisa kamu lakukan. Kalau ada yang lapar di depanmu, kamu tidak bilang “sudah takdir” dan meneruskan makanmu. Kamu berbagi. Bukan karena kamu sudah memecahkan misteri semesta, melainkan karena itu yang bisa kamu lakukan dari titik berdirimu sekarang.
Aku rasa ada kaisar Romawi yang juga sampai pada kesimpulan yang kurang lebih sama, tetapi dia menulisnya dengan bahasa yang lebih indah di buku catatannya yang tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca orang lain. Ada ironi yang menyenangkan di situ—pemikiran terbaik sering lahir ketika kita tidak berusaha terlihat pintar.
Setiap hal yang tampak seperti musibah, kata kalimat yang aku ulang itu, adalah ujian. Bukan dalam pengertian ujian sekolah yang punya jawaban benar dan salah yang jelas. Lebih seperti ujian yang pertanyaannya adalah: “Siapa kamu sebenarnya, di momen seperti ini?” Aku tidak selalu suka jawabannya, tetapi setidaknya pertanyaannya jujur.
III. Pernah aku bermimpi tentang sumur. Bukan sekali. Beberapa kali, dengan interval yang tidak beraturan, sumur itu datang kembali dalam tidurku. Selalu sumur yang sama: dalam, gelap, dingin. Tidak ada cahaya yang sampai ke dasarnya. Tidak ada suara kecuali gema air yang menetes dari suatu tempat yang tidak bisa aku temukan.
Dalam mimpi-mimpi itu aku tidak takut. Aku hanya turun. Perlahan, dengan tali yang tidak kelihatan, menuju bawah yang tidak kelihatan. Dan anehnya, semakin dalam aku turun, semakin jernih sesuatu di dalam kepalaku. Seperti kepala yang terisi di atas ternyata harus dikosongkan sebelum bisa diisi dengan sesuatu yang lebih penting.
سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى
Maha Suci Zat yang Maha Tinggi lagi Tertinggi.
Yang Maha Tinggi. Ada paradoks di sana yang tidak bisa aku selesaikan dengan logika, jadi aku sudah berhenti mencoba. Semakin tinggi sesuatu, semakin kecil kamu merasa di hadapannya—dan anehnya, perasaan kecil itu bukan merendahkan. Ia justru membebaskan. Seperti melepas jaket tebal di hari yang ternyata tidak sedingin perkiraan.
Lapar hari ini mengajarkan hal yang serupa. Tubuhku yang terbiasa merasa cukup, tiba-tiba diingatkan betapa bergantungnya ia. Pada seteguk air. Pada sepiring nasi. Pada napas berikutnya yang tidak pernah aku ingat untuk disyukuri karena selalu datang tepat waktu. Ketergantungan itu bukan memalukan. Ia hanya jujur. Informasi tentang apa yang sebenarnya aku ini.
Epictetus lahir sebagai budak. Aku tidak tahu mengapa aku selalu ingat fakta itu ketika memikirkan tentang kebebasan. Mungkin karena ada sesuatu yang sangat gamblang tentangnya: seorang budak yang menulis tentang kebebasan jiwa, yang mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milikmu adalah responsmu terhadap apa yang terjadi padamu. Bukan hartamu. Bukan kesehatanmu. Bahkan bukan orang-orang yang kamu cintai. Hanya itu—caramu merespons.
Kerendahan hati, dalam pengertian ini, bukan sikap yang dibuat-buat. Ia adalah pengenalan yang akurat terhadap situasi yang sebenarnya. Bahwa kamu adalah satu tetes dari sesuatu yang jauh lebih luas dari kemampuan imajinasimu untuk menggambarkannya. Dan dari pengenalan yang akurat itu, lahir bukan keputusasaan, melainkan gerakan—menolong yang terpinggirkan, hadir bagi yang tidak terlihat, menjadi sesuatu yang berguna di dalam semesta yang lebih besar darimu.
IV. Ada jenis keheningan yang lebih ramai dari keributan. Ini yang aku temukan pada pengulangan ke-89.
سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
Maha Suci Dia dan dengan puji bagi-Nya, Maha Suci Dia dan Maha Tinggi.
Pada pengulangan ke-93, aku menyadari sesuatu yang kecil tetapi aneh: bahwa kemampuanku untuk memuji berasal dari Yang aku puji. Bahwa aku tidak punya apa-apa—bahkan kata-kata pun bukan milikku. Bahwa seluruh pujianku adalah seperti seseorang yang meminjam uang dari banknya, lalu menyerahkan uang itu kembali kepada bank sebagai setoran. Lingkaran yang memusingkan jika dipikirkan terlalu lama, tetapi entah kenapa terasa seperti kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan. Pada pengulangan ke seratus, mulutku masih bergerak tetapi aku tidak lagi mendengar suara.
Ada sebuah kata dalam bahasa yang tidak aku kuasai sepenuhnya—fana—yang artinya kurang lebih: penghilangan diri. Para mistikus menggunakannya untuk menggambarkan saat ketika ego berhenti menjadi pusat dari segalanya. Aku tidak pernah mengalami fana dalam pengertian yang dramatis—cahaya besar, kesadaran kosmis, semua itu. Yang aku alami lebih sederhana dan lebih membingungkan: ada momen-momen tertentu, biasanya ketika aku sedang melakukan sesuatu yang sangat biasa, ketika batas antara aku dan apa yang ada di sekitarku menjadi kurang jelas dari biasanya. Bukan hilang. Hanya kurang tegas. Seperti kabut di tepi danau pagi hari. Air masih ada. Udara masih ada. Tetapi di antara keduanya ada wilayah di mana tidak mudah untuk mengatakan di mana yang satu berakhir dan yang lain dimulai.
Seorang yang bijak pernah berkata—atau mungkin aku membacanya, atau mungkin seseorang menceritakannya kepadaku di sebuah percakapan yang sudah aku lupa kapan dan di mana berlangsung—bahwa jalan tercepat menuju Yang kita cari adalah dengan melayani yang lain. Bukan ritual. Bukan pengetahuan. Pelayanan. Tangan yang memberi. Kaki yang datang. Telinga yang mendengar tanpa agenda.
Dan ketulusan itu penting. Sangat penting. Perbuatan yang dilakukan supaya terlihat baik adalah sesuatu yang lain—bukan kejahatan, tetapi juga bukan apa yang sedang kita bicarakan. Yang sedang kita bicarakan adalah kebaikan yang terjadi karena ia tidak bisa tidak terjadi. Seperti matahari yang tidak memutuskan untuk bersinar setiap pagi. Ia hanya bersinar.
Bayangkan seorang hamba. Ia disapa Tuhan bak Nabi Musa a.s. disapa Tuhan. “Ketika Aku sakit, mengapa kamu tidak datang menjenguk-Ku?” Dan hamba itu bingung karena pertanyaan itu tidak masuk akal dengan cara yang biasa. Jawabannya: di sisi hamba-Ku yang sakit itu, kamu akan menemukan Aku.
Aku sudah membaca banyak hal tentang teologi, filsafat, dan mistisisme. Tetapi kalimat itu—dengan kesederhanaannya yang mengejutkan—adalah salah satu yang paling sulit aku lupakan. Ia mengatakan sesuatu tentang di mana hal-hal yang paling penting berada. Bukan di tempat yang jauh dan sulit dijangkau. Di sisi orang-orang yang sakit, lapar, dan tidak punya nama di halaman mana pun.
V. (MENJELANG MAGHRIB)
Sebentar lagi azan akan terdengar. Aku tahu ini bukan karena jam—aku tidak melihat jam—tetapi karena cahaya di luar jendela sudah berubah warna. Oranye yang khas itu. Oranye yang hanya ada di dua waktu: fajar dan petang. Oranye yang membuat segala sesuatu terlihat seperti adegan terakhir dari film yang belum selesai. Tubuhku sudah tahu apa yang akan terjadi beberapa menit lagi dan sudah mulai bersiap-siap dengan cara tubuh bersiap-siap—sedikit lebih waspada, sedikit lebih antusias, sedikit lebih hadir dari beberapa jam sebelumnya.
Tetapi ada yang ingin aku jaga sebentar sebelum waktu itu datang. Sesuatu yang terjadi hari ini—dalam dua ratus kata yang diulang-ulang itu, dalam lapar yang tidak pernah benar-benar menjadi tidak tertahankan tetapi juga tidak pernah benar-benar pergi—sesuatu yang tidak bisa aku beri nama dengan tepat. Bukan pencerahan. Aku tidak percaya pencerahan datang dalam satu siang seperti ini. Lebih seperti geseran kecil. Seperti ketika kamu menggerakkan kacamata satu milimeter dan tiba-tiba segala sesuatu sedikit lebih tajam dari tadi. Tidak dramatis, tetapi nyata.
Mereka yang mencapai apa yang para arif sebut Jannatul Liqa—surga pertemuan—bukan mereka yang paling banyak tahu. Mereka adalah yang paling banyak hadir. Yang datang sebelum diminta. Yang diam setelah pergi tanpa menunggu terima kasih. Mereka melihat suka dan duka dengan cara yang sama—bukan karena mereka tidak merasakannya, melainkan karena mereka sudah cukup lama mengenal tangan di balik keduanya untuk tidak terlalu terkejut lagi.
Ini yang ingin aku jadikan—bukan dalam pengertian yang besar dan ambisius. Dalam pengertian yang kecil dan hari ini. Dalam pengertian siang Ramadhan ini, jendela ini, kursi kayu ini, seratus pengulangan ini.
Di luar, seseorang sedang menyiram tanaman. Suara air jatuh ke tanah yang kering terdengar sampai ke sini. Sesuatu yang sangat biasa dan sangat sempurna pada saat yang sama. Aku tidak tahu apakah orang itu sedang memikirkan hal-hal seperti yang aku pikirkan, atau apakah ia sedang memikirkan hal yang sama sekali lain—mungkin apa yang akan ia masak untuk berbuka, mungkin seseorang yang sudah lama tidak ia hubungi, mungkin tidak ada apa-apa, mungkin hanya air dan tanaman dan sore yang biasa.
Tetapi untuk sesaat, dalam suara air yang jatuh itu, semuanya terasa cukup. Tidak berlebihan. Tidak kurang. Hanya cukup. Dan “cukup” adalah kata yang sudah lama tidak aku ucapkan dengan cara yang benar-benar aku maksudkan.
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
Tidaklah taufikku kecuali dari Allah, kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali.
3 Ramadhan 1447 H اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ