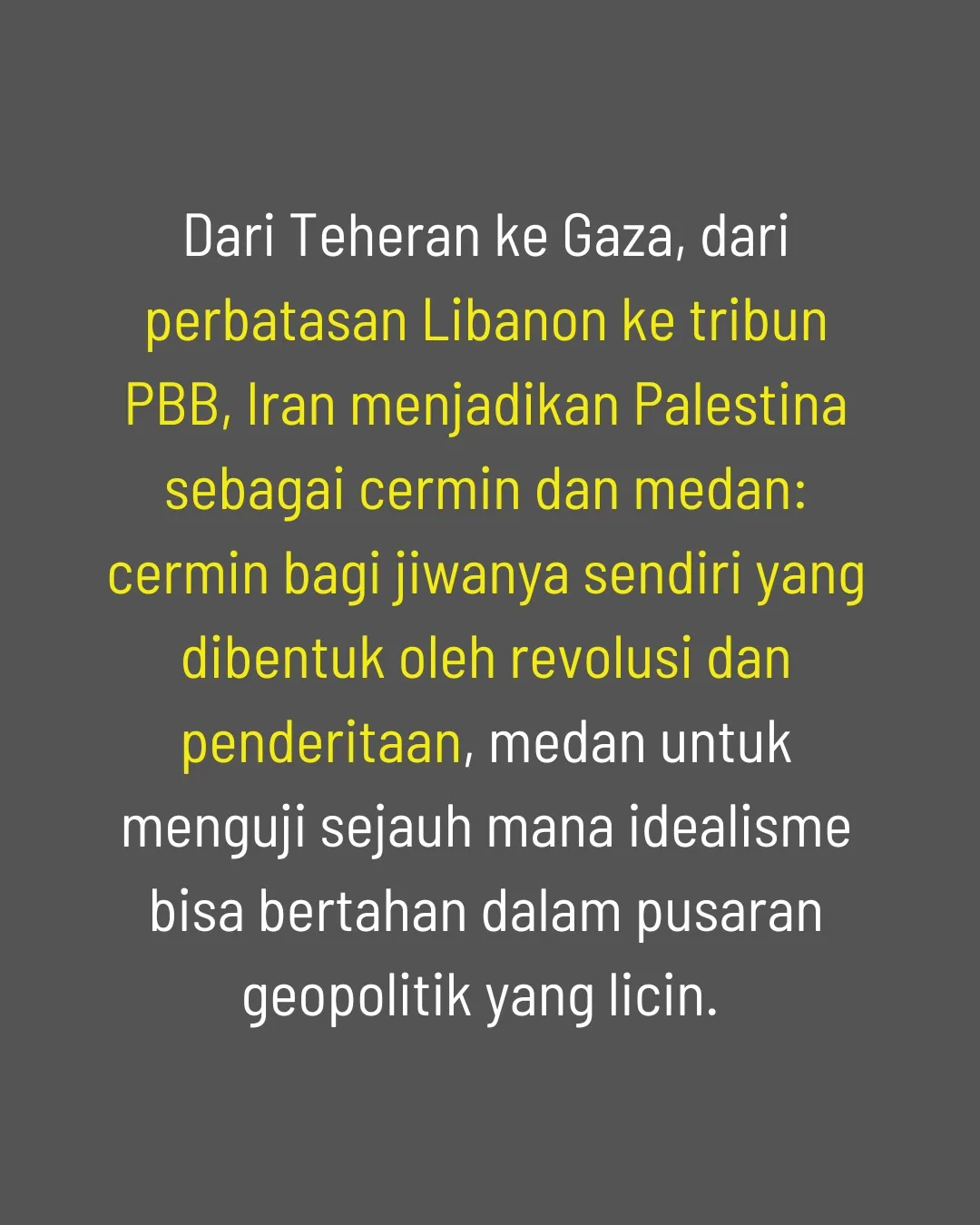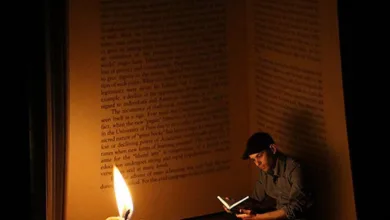Penjaga Palestina dari Teheran
Oleh Abdul Karim
“Perlawanan Islam adalah perwujudan dari politik spiritual yang menolak imperialisme dalam segala bentuknya — sebuah jihad bukan untuk dominasi, tapi untuk keadilan.”— Eric Walberg
Sejarah pembelaan Republik Islam Iran terhadap Palestina bukan sekadar serangkaian kebijakan luar negeri, melainkan kristalisasi dari identitas revolusioner yang sejak awal menolak ketundukan pada hegemoni Barat dan Zionisme. Dalam lanskap Timur Tengah yang penuh ketegangan, Iran menjelma bukan hanya sebagai pemain negara, tetapi sebagai pelopor poros perlawanan yang menjadikan Palestina sebagai tolok ukur moral perjuangan global. Sejak Revolusi Islam 1979 menggulingkan monarki Pahlavi yang pro-Barat, arah politik luar negeri Iran mengalami perubahan mendalam. Palestina bukan lagi isu Arab, melainkan amanah Islam. Dan dalam narasi itu, Iran berdiri sebagai penjaga paling konsisten dari luka dan harapan rakyat Palestina.
Pada awal Revolusi, pembelaan terhadap Palestina menjadi simbol pemutusan total dengan kebijakan Shah yang cenderung mendekat ke Amerika Serikat dan secara diam-diam menjaga hubungan dengan Israel. Kantor kedutaan besar Israel di Teheran ditutup dan digantikan oleh Kedutaan Besar Palestina, menandai bukan hanya transformasi diplomatik, tetapi juga posisi normatif Iran di antara bangsa-bangsa dunia. Dalam kerangka yang disebut oleh Przemysław Osiewicz sebagai “ideologi revolusioner berbasis syi’ah dengan visi universal Islam politik,” Iran menjadikan Palestina sebagai medan paling suci dari jihad perlawanan terhadap kezaliman. Tidak hanya slogan, tapi aksi nyata: dari pelatihan militer hingga dukungan finansial, dari jejaring diplomasi di PBB hingga kampanye media internasional, Iran menanamkan komitmennya dalam semua dimensi perlawanan.
Apa yang membedakan pembelaan Iran dari kebanyakan negara lain bukan hanya keberlanjutan, tetapi kualitas ideologis yang menyatu dengan logika strategis. Buku Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: Between Ideology and Pragmatism menjelaskan bahwa bahkan ketika Iran harus menyesuaikan diri dengan realitas geopolitik dan tekanan sanksi, dukungan terhadap Palestina tetap menjadi elemen tak tergoyahkan dari konsensus domestik dan regional. Walaupun ada dinamika internal yang melibatkan Majelis Keamanan Nasional, Dewan Keulamaan, dan militer seperti IRGC, kebijakan terhadap Palestina nyaris tidak pernah diperdebatkan secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa Palestina telah menjadi bagian dari “struktur simbolik” Iran sebagai bangsa yang menolak penindasan global.
Dalam kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Raymond Hinnebusch dan Anoushiravan Ehteshami dalam The Foreign Policies of Middle East States, pendekatan Iran terhadap Palestina tidak dapat dipisahkan dari apa yang mereka sebut sebagai “transstate identity wars.” Iran tidak hanya membela negara yang dijajah, tetapi membela kesatuan umat yang tercerai-berai oleh penjajahan, perpecahan sektarian, dan kepentingan Barat. Ini menjelaskan mengapa Iran menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok perlawanan dari berbagai spektrum ideologis, baik Sunni seperti Hamas dan Jihad Islam, maupun Syi’ah seperti Hizbullah. Politik luar negeri Iran terhadap Palestina adalah bentuk konkret dari solidaritas lintas batas yang mengganggu peta kekuasaan tradisional di Timur Tengah yang selama dekade-dekade sebelumnya didominasi oleh Arab Saudi, Mesir, dan Yordania dengan pendekatan pragmatis yang lebih condong ke AS dan Israel.
Eric Walberg dalam Islamic Resistance to Imperialism menggambarkan peran Iran sebagai perwujudan dari “politik spiritual” yang menolak keterlibatan dalam struktur imperialisme global. Menurut Walberg, Iran tidak sekadar memainkan peran geopolitik, tapi juga menyuntikkan dimensi spiritual dan historis ke dalam arena perlawanan. Dalam hal ini, Iran menawarkan alternatif atas tatanan dunia yang ditentukan oleh kekuatan militer dan pasar modal. Palestina menjadi medan ujian, tempat Iran mempertaruhkan identitasnya sebagai pelopor dunia Islam yang bebas dan bermartabat. Ketika banyak negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel atau terlibat dalam proyek-proyek ekonomi pasif, Iran justru memperdalam hubungan ideologis, logistik, dan strategis dengan kelompok-kelompok perlawanan Palestina, bahkan ketika itu berarti menghadapi isolasi ekonomi dan ancaman militer.
Namun, komitmen ini tidak selalu berjalan tanpa komplikasi. Iran harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian kelompok Palestina, terutama di era awal, masih terpengaruh oleh nasionalisme Arab yang curiga terhadap Revolusi Islam. Tapi waktu dan sejarah berpihak pada Iran. Ketika negara-negara Arab satu per satu mundur dari konfrontasi langsung dengan Israel, Iran justru maju ke garis depan. Hubungan dengan Hamas dan Jihad Islam berkembang pesat sejak Intifadah Kedua, terutama setelah Hizbullah yang didukung Iran berhasil memaksa Israel mundur dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Kemenangan ini mengubah persepsi kekuatan dan memperkuat narasi bahwa poros perlawanan yang didukung Iran lebih efektif daripada diplomasi pasif yang dipromosikan oleh Arab Saudi atau Mesir.
Peran Iran dalam mendukung Palestina juga tidak dapat dipisahkan dari pembentukan identitas nasional Iran pasca-Revolusi. Dalam struktur politik yang dijelaskan oleh Osiewicz, hubungan antara Wilayat al-Faqih, IRGC, dan lembaga-lembaga sipil menghasilkan mekanisme konsensus ideologis di mana Palestina menempati posisi sentral. Bahkan dalam retorika domestik, para pemimpin Iran, dari Imam Khomeini hingga Ayatollah Khamenei, selalu menekankan bahwa “membela Palestina adalah kewajiban agama dan nasional.” Ungkapan-ungkapan seperti “Hari Quds Internasional” bukan hanya simbolisme retoris, tetapi menjadi ruang artikulasi kolektif yang memperkuat solidaritas domestik dan internasional terhadap penderitaan Palestina.
Bahkan ketika Iran mengalami gelombang tekanan sanksi dan konflik domestik, dukungan terhadap Palestina tetap dijaga. Dalam perspektif Islamic Resistance to Imperialism, hal ini mencerminkan kekukuhan Iran sebagai negara yang telah melampaui kalkulasi realpolitik. Negara ini menjadi semacam penjaga semangat revolusioner yang menolak untuk tunduk pada kekuatan dominan, bahkan jika itu berarti menempuh jalan panjang yang sunyi. Palestina bukan sekadar tujuan diplomatik, tetapi bagian dari proyek spiritual dan historis yang lebih luas, yakni membangun tatanan dunia yang adil bagi mereka yang tertindas.
Konsistensi ini menciptakan dampak global yang signifikan. Iran bukan hanya dianggap sebagai sponsor kelompok perlawanan, tetapi juga sebagai simbol keteguhan dalam menghadapi proyek normalisasi yang dilakukan oleh Israel dan sekutunya. Di tengah dunia Arab yang terpecah, Iran menjadi titik kutub yang memproyeksikan perlawanan bukan sebagai ekstremisme, tetapi sebagai pembelaan terhadap kemanusiaan. Dalam bahasa Walberg, inilah “jihad keadilan” yang menolak untuk tunduk bahkan ketika jalan yang ditempuh begitu terjal.
Iran menjadikan perlawanan sebagai identitas kolektif, bukan sebagai alat. Palestina bukan alat tawar-menawar, melainkan representasi konkret dari amanah sejarah dan iman. Dalam pemikiran Hinnebusch, inilah bentuk dari foreign policy yang tidak hanya berbasis pada kalkulasi kekuasaan, tetapi juga dipandu oleh memori dan narasi. Iran memahami bahwa dalam lanskap internasional yang penuh tipuan dan kompromi, satu-satunya kekuatan sejati yang mampu bertahan adalah yang bersandar pada prinsip. Dan prinsip itu bagi Iran adalah: Palestina harus merdeka, dan kezaliman harus runtuh.
Dari Teheran ke Gaza, dari perbatasan Libanon ke tribun PBB, Iran menjadikan Palestina sebagai cermin dan medan: cermin bagi jiwanya sendiri yang dibentuk oleh revolusi dan penderitaan, medan untuk menguji sejauh mana idealisme bisa bertahan dalam pusaran geopolitik yang licin. Sejarah hubungan ini adalah sejarah dari janji yang tidak pernah dibatalkan: bahwa selama masih ada rakyat yang terjajah, Iran akan berdiri bersama mereka, bukan karena kepentingan, tetapi karena iman.
Daftar
Pustaka:Osiewicz, Przemysław. Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: Between Ideology and Pragmatism. Routledge, 2020.
Hinnebusch, Raymond & Ehteshami, Anoushiravan (Eds.). The Foreign Policies of Middle East States (Second Edition). Lynne Rienner Publishers, 2014.
Walberg, Eric. Islamic Resistance to Imperialism. Clarity Press, 2015.

Abdul Karim
Guru matematika SMUTH 2000 - 2005 dan praktisi pendidikan matematika dan IT