
Oleh : Dimitri Mahayana
Amerika Serikat telah menempuh perjalanan panjang dari republik agraria di bawah George Washington hingga menjadi imperium global yang kini menghadapi ketidakstabilan politik dan tantangan geopolitik, termasuk eskalasi konflik Israel-Iran. Di era George Washington (1789–1797), AS berdiri di atas prinsip republikanisme klasik, menekankan pemerintahan terbatas dan netralitas luar negeri. Dalam Farewell Address (1796), Washington memperingatkan terhadap aliansi asing dan faksi politik. Namun, Chomsky akan menyoroti bahwa republik ini melindungi elite properti, sementara perbudakan—Washington sendiri memiliki ratusan budak—dan pengusiran penduduk asli mengungkap kontradiksi. West menegaskan bahwa rasisme sistemik ini menjadi akar ketimpangan modern, seperti penjara massal. Zinn menegaskan bahwa sejarah “kebebasan” AS adalah mitos, mengabaikan penderitaan rakyat biasa.
Pada awal abad ke-20, sebelum Perang Dunia I, AS mulai menunjukkan ambisi imperial melalui Monroe Doctrine (1823) dan Perang Spanyol-Amerika (1898), mencaplok Filipina dan Puerto Rico. Korporasi seperti Standard Oil mendominasi, sementara buruh imigran dan undang-undang Jim Crow mencerminkan eksploitasi, seperti dicatat Zinn. Hedges melihat era ini sebagai kelahiran kapitalisme predator, dengan negara melayani oligarki industri. Greenwald menyoroti penindasan aktivis buruh sebagai cikal bakal national security state.Pasca-Perang Dunia I, AS sempat mengadopsi isolasionisme, menolak Liga Bangsa-Bangsa. Roaring 20s memperlebar kesenjangan ekonomi, dan Depresi Besar (1929) memicu New Deal, yang menurut Hedges hanya menyelamatkan kapitalisme, bukan mereformasi ketidakadilan. Zinn menyoroti pengabaian terhadap rasisme sistemik, sementara Greenwald mencatat penahanan warga Jepang-Amerika selama PD II sebagai pelanggaran HAM atas nama keamanan. PD II menjadikan AS adidaya, dengan Marshall Plan dan Bretton Woods (IMF, World Bank) mengukuhkan hegemoni ekonominya.

Selama Perang Dingin (1945–1991), AS menjadi polisi dunia, menggunakan anti-komunisme untuk membenarkan intervensi di Vietnam, Guatemala, dan Chile. Zinn menyebut Perang Vietnam sebagai kejahatan perang yang didorong korporasi seperti Dow Chemical. Hedges melihat Perang Dingin sebagai alat kontrol sosial, sementara Greenwald menyoroti pengawasan domestik melalui COINTELPRO sebagai bukti rapuhnya demokrasi. Military-industrial complex, yang diperingatkan Eisenhower, mengakar dengan anggaran militer yang melonjak.
Pasca-runtuhnya Uni Soviet (1991), AS memaksakan Washington Consensus melalui deregulasi dan privatisasi, memperluas pengaruh melalui IMF dan WTO. War on Terror pasca-9/11 melahirkan PATRIOT Act dan pengawasan massal NSA, yang dibongkar Greenwald melalui Snowden Leaks. Hedges menyebut neoliberalisme sebagai “kapitalisme bunuh diri” yang terlihat dari Citizens United (2010), yang melegalkan korupsi politik. Zinn memuji perlawanan rakyat melalui Occupy Wall Street dan Black Lives Matter sebagai harapan perubahan.
Kini, pada Juni 2025, AS menghadapi polarisasi politik ekstrem krisis ekonomi dengan utang nasional $33 triliun, dan dominasi korporasi teknologi. Dukungan tanpa syarat untuk Israel ($3,8 miliar/tahun) tetap menjadi pilar kebijakan, meskipun memicu ketegangan domestik dari sayap progresif. Konflik Israel-Iran meningkat tajam sejak serangan Iran pada April 2024 sebagai balasan atas pembunuhan pejabat IRGC di Damaskus, diperparah oleh serangan proksi Hezbollah dan Houthi serta ancaman Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Dengan mempertimbangkan eskalasi terkini, termasuk laporan intelijen tentang peningkatan aktivitas militer Iran dan tekanan lobi pro-Israel di Kongres, probabilitas keterlibatan AS adalah sebagai berikut.
1. Dukungan Logistik tanpa Perang Langsung (Probabilitas: 19,99%): AS kemungkinan tetap memperkuat Israel dengan intelijen, Iron Dome, dan sanksi terhadap Iran, tanpa mengirim pasukan darat. Trump berupaya menghindari krisis ekonomi menjelang pemilu 2028, tetapi tekanan dari lobi AIPAC dan protes domestik memperumit posisinya. Greenwald memperingatkan bahwa media korporat akan membingkai dukungan ini sebagai “pertahanan demokrasi”, menyembunyikan motif ekonomi seperti kontrak senjata. Namun, kebijakan ini justru memperburuk citra AS di mata dunia. Media korporat mungkin membingkai dukungan ini sebagai “pertahanan demokrasi,” tetapi kenyataannya, motif utamanya adalah kepentingan industri senjata. Solidaritas Muslim global yang semakin menguat pasca-serangan ke Tehran akan memperburuk isolasi diplomatik Israel, sementara sanksi terhadap Iran justru mendorong negara itu semakin dekat dengan Rusia dan Tiongkok. Hasilnya, AS terjebak dalam perang tanpa akhir yang menguras sumber daya tanpa kemenangan jelas.
2. Perang Terbatas dengan Serangan Udara dan Laut (Probabilitas: 49,99%): Karena Israel menyerang Iran, dan saat ini Iran membalas serangan ini dengan menyerang fasilitas-fasilitas strategis Israel, sangat mungkin bagi AS terlibat dengan melancarkan serangan udara terhadap IRGC dan blokade laut di Teluk Persia. Probabilitas besar, sekitar 50%, karena ancaman terhadap pasokan minyak global (jika harga melebihi $100/barel) dan tekanan lobi pro-Israel semakin kuat. Namun, langkah ini berisiko memicu lonjakan harga minyak di atas $100 per barel, memperburuk ekonomi global. Perang terbatas juga tidak akan menghancurkan kapasitas asimetris Iran, termasuk jaringan proxy seperti Hizbullah dan Houthi yang siap menyerang balik. Blokade laut pun bisa digagalkan oleh bantuan logistik Rusia atau Tiongkok. Sementara itu, anggaran militer AS yang sudah mencapai $886 miliar per tahun semakin tidak terjangkau di tengah krisis utang. Yang lebih berbahaya, perang ini akan memicu mobilisasi global—tidak hanya dari dunia Muslim, tetapi juga dari aktivis anti-perang dan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS). Pada akhirnya, AS akan terjebak dalam konflik berkepanjangan, sementara Israel menghadapi ancaman keamanan yang semakin besar. Hedges melihat ini sebagai langkah menuju “kehancuran imperium” karena anggaran militer ($886 miliar/tahun) tidak berkelanjutan di tengah krisis utang.

3. Perang Besar dengan Keterlibatan Penuh (Probabilitas: 19,99%): Jika Iran menutup Selat Hormuz, memicu krisis minyak global (harga >$150/barel), AS mungkin mengerahkan pasukan darat terbatas atau serangan nuklir taktis jika Iran mengancam senjata nuklir. Chomsky menyoroti bahwa logika imperialisme akan memperkuat military-industrial complex, meskipun melemahkan legitimasi global AS. Probabilitasnya ada, – menurut hemat kami tidak terlalu besar, – sekitar 20%-, mengingat Amerika Serikat mau tidak mau harus memperhitungkan potensi keterlibatan kaum Muslimin sedunia yang saat ini berlomba-lomba mendukung Iran, – yang merupakan kekuatan sangat besar, pervasive dan tidak bisa diprediksikan batasnya- maupun kemungkinan Rusia dan Cina maupun Korea Utara ikut mendukung Iran. Lebih lanjut, langkah ini akan memicu reaksi berantai yang menghancurkan. Rusia dan Tiongkok bisa mengirim bantuan militer ke Iran, sementara kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Houthi melancarkan serangan besar-besaran ke Israel. Jika AS menggunakan senjata nuklir taktis, ancaman eskalasi nuklir dengan Rusia atau Tiongkok menjadi nyata. Di tingkat global, hegemoni AS akan runtuh: NATO bisa pecah, Eropa enggan terlibat, dan dunia beralih ke tatanan baru.
Sejarah AS, dari Washington hingga kini, menunjukkan pola pelayanan terhadap elite, dari perbudakan hingga korporatisme dan perang abadi. Konflik Israel-Iran adalah ujian terbaru: meskipun AS lebih mungkin menghindari perang langsung, eskalasi terkini meningkatkan risiko intervensi terbatas. Hedges memperingatkan, “Empires never learn. They only collapse.” Dan risiko terkecil bagi bangsa adidaya ini adalah, inilah saatnya baginya untuk mengoreksi diri, dan mencegah diri dari keterlibatan dalam konflik Iran Israel. Apakah ini mungkin? Probabilitasnya tetap ada. Mengingat adanya free will, kehendak bebas publik , aktifis, parlemen maupun kabinet Trump. Wallahu a’lam
Referensi: Chomsky, N. (2003). Hegemony or Survival. West, C. (1993). Race Matters. Zinn, H. (1980). A People’s History. Hedges, C. (2002). War Is a Force That Gives Us Meaning. Greenwald, G. (2011). With Liberty and Justice for Some. Mearsheimer, J. (2018). The Great Delusion. Laporan RAND Corporation (2023).




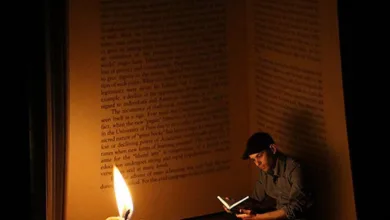



Terima kasih Ustadz, telah berbagi artikel yang aktual, menarik dan bermanfaat.