MELANGGENGKAN DZIKIR DI ERA DIGITAL: KAJIAN TEOLOGIS-EKSISTENSIAL ATAS MUNAJAT SHA’BANIYYAH

Penulis : Dr. Dimitri Mahayana (Sekretaris Dewan Syura IJABI)
Abstrak
Makalah ini mengkaji implikasi teologis dan eksistensial dari sebuah penggalan doa dalam Munajat Sha’baniyyah yang memohon kontinuitas dzikir, kesetiaan pada janji ilahi, kesyukuran yang berkesinambungan, dan keseriusan dalam menjalankan urusan Allah. Melalui pendekatan hermeneutis yang mengintegrasikan tafsir serta dialog dengan filsafat eksistensial, kajian ini menunjukkan bahwa kelalaian spiritual (ghaflah) di era digital mengakibatkan kehidupan yang tidak autentik. Walayah Rasulullah Saw dan Ahlul Bait as, dalam konteks ini, dipahami sebagai jalan menuju autentisitas eksistensial yang memberikan makna pada setiap detik kehidupan manusia. Makalah ini juga mengeksplorasi relevansi ajaran spiritual Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti surveillance capitalism, bias algoritmik, dan fragmentasi kesadaran kolektif.
Kata kunci: Munajat Sha’baniyyah, dzikir, ghaflah, autentisitas eksistensial, walayah, era digital
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Munajat Sya’baniyah (bahasa Arab:المناجاة الشعبانية) adalah munajat yang diajarkan oleh Imam Ali as dan dibaca pula oleh imam-imam setelahnya. Doa ini secara tradisional dibaca pada bulan Sya’ban sebagai persiapan spiritual menjelang Ramadhan. Munajat ini memiliki karakteristik khas berupa ungkapan cinta kepada Allah (‘ishq ilahi) yang murni, putusnya ketergantungan total kepada selain Allah (inqita’ tamm), dan pengenalan mendalam akan Allah (ma’rifah ‘amiqah).
Salah satu penggalan dalam Munajat Sha’baniyyah berbunyi:
إِلٰهِي اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُدِيمُ ذِكْرَكَ، وَلاَ يَنْقُضُ عَهْدَكَ، وَلاَ يَغْفُلُ عَنْ شُكْرِكَ، وَلاَ يَسْتَخِفُّ بِأَمْرِكَ
Yang dapat diterjemahkan: “Ya Tuhanku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang melanggengkan mengingat-Mu (yudīmu dhikrak), tidak memutuskan janji kepada-Mu (lā yanquḍu ‘ahdak), tidak lalai dari bersyukur kepada-Mu (lā yaghfulu ‘an shukrik), dan tidak memandang ringan urusan-Mu (lā yastakhiffu bi amrik).”
Penggalan doa ini bukanlah sekadar permohonan untuk kontinuitas praktik ritual, melainkan permohonan untuk sebuah kondisi spiritual yang berkesinambungan (hal da’im), bukan spiritualitas yang berbasis momen semata. Dalam konteks kehidupan kontemporer yang ditandai oleh fragmentasi atensi, banjir informasi, dan alienasi digital, ajaran yang terkandung dalam doa ini memiliki relevansi yang sangat mendalam.
B. Rumusan Masalah
Makalah ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kelupaan akan Asal, Tujuan, dan Realitas Kasih Ilahi yang menyertai setiap detik kehidupan mengakibatkan kehidupan yang tidak autentik dan tidak bermakna? Kedua, apa saja karakteristik spiritual dari mereka yang melanggengkan dzikir sebagaimana disebutkan dalam Munajat Sha’baniyyah, yakni tidak memutuskan janji, tidak lalai dari syukur, dan tidak memandang ringan urusan Allah? Ketiga, bagaimana ketiga karakteristik tersebut terkait dengan walayah Nabi saw dan Ahlul Bait as, khususnya dalam penafsiran konsep “syukr” dan “amr” menurut tradisi tafsir Syiah?
C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode hermeneutis-teologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer yang digunakan adalah teks Munajat Sha’baniyyah, Al-Quran, hadits-hadits dari Ahlul Bait as. Sumber sekunder meliputi karya-karya tafsir, khususnya Tafsir al-Mizan karya Allamah Tabataba’i dan Tafsir Nurul Qur’an karya Allamah Kamal Faqih Imani. Kajian ini juga melakukan dialog kritis dengan filsafat eksistensial, khususnya pemikiran Martin Heidegger tentang autentisitas, untuk memperkaya analisis tentang kondisi manusia kontemporer.
II. WAKTU YANG TERSEDIA: TRAGEDI KELUPAAN EKSISTENSIAL

A. Penyesalan di Hari Akhir dalam Perspektif Qur’ani
Al-Quran secara berulang memperingatkan tentang penyesalan yang akan dialami manusia di akhirat ketika mereka menyadari bahwa waktu kehidupan dunia telah terbuang dalam kelalaian. Salah satu ayat yang paling tajam menggambarkan kondisi ini terdapat dalam Surah Al-Mu’minun ayat 99-100:
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
“Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata: ‘Ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia), agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan.’ Sekali-kali tidak! Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding (barzakh) sampai hari mereka dibangkitkan.”
Ayat ini mengungkapkan bahwa penyesalan terbesar di akhirat bukanlah semata-mata karena dosa-dosa besar yang dilakukan, melainkan karena waktu yang terbuang dalam kelalaian. Manusia hidup seolah-olah Allah tidak ada, seolah-olah tidak akan kembali kepada-Nya, seolah-olah dunia adalah tujuan akhir. Ketika tirai kematian terangkat, barulah tersingkap dengan jelas betapa sia-sianya setiap detik yang tidak diinvestasikan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kasih.
Dalam konteks ini, permohonan untuk “melanggengkan dzikir” (yudīmu dhikrak) dalam Munajat Sha’baniyyah dapat dipahami sebagai permohonan untuk terhindar dari tragedi kelupaan eksistensial tersebut. Dzikir di sini bukan hanya pengulangan formula-formula verbal tertentu, melainkan kesadaran kontinyu akan tiga realitas fundamental: Asal, Tujuan, dan Realitas Kasih Ilahi yang menyertai setiap detik kehidupan.
B. Tiga Dimensi yang Terlupakan
1. Al-Aṣl (Asal): Dari Mana Kita Berasal
Dimensi pertama yang harus senantiasa diingat adalah asal-usul ontologis manusia. Al-Quran dalam Surah Al-A’raf ayat 172 menceritakan tentang perjanjian primordial (mitsaq) antara Allah dan seluruh jiwa manusia:
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ
“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): ‘Bukankah Aku ini Tuhanmu?’ Mereka menjawab: ‘Betul (Engkau Tuhan kami).'”
Allamah Tabataba’i dalam Tafsir al-Mizan menafsirkan ayat ini sebagai wāqi’ah takwīniyyah, yakni realitas ontologis, bukan sekadar metafora atau alegori.
“ Jiwa pada setiap yang berjiwa memiliki aspek-aspek keterkaitan dan hubungan dengan selain dirinya. Manusia dapat dimintai kesaksian tentang sebagian aspek tersebut tanpa sebagian yang lain. Namun firman-Nya: “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” menjelaskan apa yang mereka dimintai kesaksian untuknya dan apa yang dikehendaki kesaksian mereka terhadapnya, yaitu agar mereka bersaksi tentang Ketuhanan-Nya, Maha Suci Dia, bagi mereka, sehingga mereka menunaikannya ketika ditanya.
Maka manusia, meskipun mencapai tingkat kesombongan dan keangkuhan yang sangat tinggi, dan tertipu oleh bantuan sebab-sebab yang membantunya dan mempesonanya, tidak mungkin baginya untuk mengingkari bahwa ia tidak memiliki eksistensi dirinya sendiri dan tidak mandiri dalam mengatur urusannya. Seandainya ia memiliki dirinya sendiri, niscaya ia akan melindunginya dari apa yang ia benci, yaitu kematian dan berbagai penderitaan serta musibah kehidupan. Dan seandainya ia mandiri dalam mengatur urusannya, ia tidak akan membutuhkan untuk tunduk di hadapan sebab-sebab kosmis dan sarana-sarana yang ia pandang bahwa ia menguasai dan memerintahnya. Padahal sarana-sarana itu seperti manusia dalam kebutuhan kepada apa yang di baliknya, dan ketundukan kepada penguasa yang ghaib darinya yang memerintah padanya, untuk kepentingannya atau melawannya. Dan bukan terserah kepada manusia untuk memenuhi kekosongan sarana-sarana itu dan menghilangkan kebutuhannya.
Maka kebutuhan kepada Rabb—Pemilik dan Pengatur—adalah hakikat manusia. Kefakiran tertulis pada jiwanya. Kelemahan tertera pada dahinya. Ini tidak tersembunyi bagi manusia mana pun yang memiliki kesadaran kemanusiaan yang paling sederhana sekalipun. Orang yang berilmu dan yang bodoh, yang kecil dan yang besar, yang mulia dan yang hina, dalam hal ini adalah sama.
Maka manusia, di mana pun ia berada dari tingkatan-tingkatan kemanusiaan, ia menyaksikan dari dirinya sendiri bahwa ia memiliki Rabb yang memilikinya dan mengatur urusannya. Bagaimana mungkin ia tidak menyaksikan Rabbnya, padahal ia menyaksikan kebutuhannya yang dzati? Bagaimana mungkin terjadi perasaan tentang kebutuhan tanpa perasaan terhadap Yang ia butuhkan?
Maka firman-Nya: “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” adalah penjelasan tentang apa yang dimintai kesaksian terhadapnya. Dan firman-Nya: “Mereka menjawab: ‘Betul, kami bersaksi'” adalah pengakuan dari mereka tentang terjadinya kesaksian dan apa yang mereka saksikan.
Oleh karena itu dikatakan: Sesungguhnya ayat ini menunjuk kepada apa yang manusia saksikan dalam kehidupan duniawinya bahwa ia membutuhkan dalam semua aspek kehidupannya—dari eksistensinya dan apa yang terkait dengan eksistensinya berupa konsekuensi-konsekuensi dan hukum-hukum. Makna ayat adalah: Sesungguhnya Kami menciptakan Bani Adam di bumi, dan memisahkan mereka serta membedakan sebagian mereka dari sebagian yang lain melalui kelahiran dan keturunan, dan Kami menjadikan mereka sadar akan kebutuhan mereka dan sifat terpelihara mereka oleh Kami, maka mereka mengakui hal itu dengan berkata: “Betul, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami.”
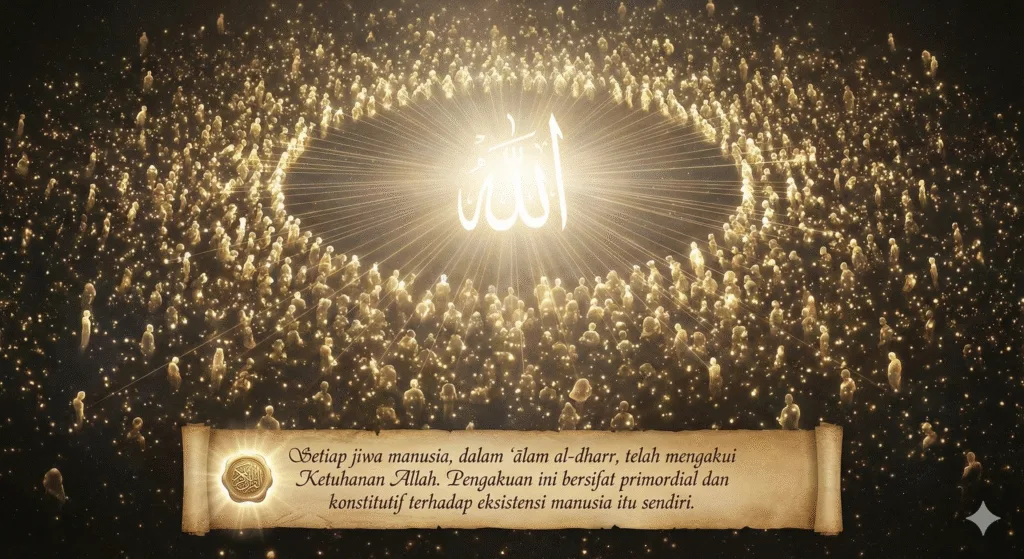
Setiap jiwa manusia, dalam ‘ālam al-dharr (alam partikel atau atom spiritual), telah mengakui Ketuhanan Allah. Pengakuan ini bersifat primordial dan konstitutif terhadap eksistensi manusia itu sendiri.
“Ingatkanlah kepada mereka sebuah tempat sebelum dunia di mana Tuhanmu “mengambil dari Bani Adam, dari punggung mereka, keturunan mereka.” Tidak ada seorang pun dari mereka kecuali ia mandiri dari yang lain dan berbeda darinya. Mereka berkumpul di sana semua dalam keadaan terpisah-pisah. Allah memperlihatkan kepada mereka diri mereka yang terkait dengan Rabb mereka, “dan Dia mengambil kesaksian mereka terhadap diri mereka sendiri.” Mereka tidak terhalang dari-Nya dan mereka menyaksikan bahwa Dia adalah Rabb mereka, sebagaimana setiap sesuatu dengan fitrahnya menemukan Rabbnya dari dirinya sendiri tanpa terhalang dari-Nya. Ini adalah zhahir (makna yang jelas) dari ayat-ayat Al-Quran seperti firman-Nya: “Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka.” (Al-Isra: 44)”
Kelupaan akan asal ini menimbulkan berbagai bentuk krisis eksistensial. Yang pertama adalah azmat al-huwiyyah (krisis identitas), di mana manusia bertanya-tanya “Siapa aku sebenarnya?” tanpa menemukan jawaban yang memuaskan. Yang kedua adalah fuqdan al-ma’na (kehilangan makna), di mana hidup terasa tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga adalah al-ightirāb al-wujūdī (alienasi eksistensial), di mana manusia merasa asing di dunia, terlempar ke dalam eksistensi tanpa makna.
Filsuf eksistensialis Martin Heidegger menyebut kondisi ini sebagai Geworfenheit, yakni “terlempar-nya” manusia ke dalam eksistensi tanpa pilihan dan tanpa makna yang jelas. Namun Islam memberikan jawaban yang fundamental: manusia tidak “terlempar”, melainkan dipilih dan dipercaya. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Ahzab ayat 72, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersedia memikul amanah yang ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Ini menunjukkan bahwa eksistensi manusia bukanlah kebetulan, melainkan pilihan sadar dalam alam pra-eksistensial.
Dengan demikian, dzikir sebagai tadhkīr (pengingatan kembali) akan asal ini berfungsi sebagai jangkar ontologis yang memberikan makna pada setiap nafas. Ketika manusia ingat bahwa ia berasal dari Allah dan eksistensinya adalah manifestasi dari kehendak Ilahi, maka setiap momen kehidupannya menjadi bermakna.
2. Al-Ghāyah (Tujuan): Ke Mana Kita Kembali
Dimensi kedua yang harus senantiasa diingat adalah tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia. Al-Quran dalam Surah Al-Insyiqaq ayat 6 menyatakan:
يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ
“Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.”
Kata kādiḥ dalam ayat ini berarti bekerja keras atau berjuang dengan susah payah, sementara frasa ilā rabbik menunjukkan arah dari semua usaha tersebut, yakni menuju Tuhan. Tabataba’i menafsirkan bahwa hidup manusia pada hakikatnya adalah sayr ilā Allāh (perjalanan menuju Allah), bukan sekadar akumulasi pengalaman atau pencapaian material.
Ketika manusia lupa bahwa ujung dari semua usaha adalah al-liqā’ (perjumpaan dengan Allah), maka terjadi inversi nilai yang fundamental. Dunia yang seharusnya menjadi wasīlah (sarana) berubah menjadi ghāyah (tujuan akhir). Sukses diukur dengan metrik-metrik palsu seperti akumulasi kekayaan, ketenaran, atau kekuasaan. Kematian, yang seharusnya dipandang sebagai maw’id (janji temu yang dinanti), berubah menjadi ‘aduw (musuh yang ditakuti).
Dalam konteks kehidupan digital kontemporer, kelupaan akan tujuan ini semakin diintensifkan. Era optimalisasi algoritma membuat manusia terjebak dalam scrolling tanpa akhir yang tidak memiliki tujuan jelas (lā ghāyah). Manusia mengejar metrik-metrik digital seperti jumlah likes dan followers yang merupakan ghāyāt zā’ifah (tujuan-tujuan palsu). Kehidupan menjadi sepenuhnya berorientasi pada feed media sosial, melupakan bahwa akan ada muḥāsabah (pertanggungjawaban) di akhirat.
“Al-nāsu niyām, fa-idhā mātū intabahū” (Manusia sedang tidur, ketika mereka mati barulah mereka terbangun). Ucapan ini diriwayatkan dari Nabi Saw dan Imam ‘Ali as. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa mayoritas manusia hidup dalam semacam tidur spiritual, tidak menyadari realitas sebenarnya tentang tujuan hidup mereka. Melanggengkan dzikir (yudīmu al-dhikr) dengan demikian berarti “bangun sekarang”, sebelum terlambat, sebelum kematian memaksa kita terbangun.
3. Al-Wāqi’ (Realitas): Kasih yang Menyertai Setiap Detik
Dimensi ketiga yang harus senantiasa diingat adalah realitas Kehadiran Ilahi yang menyertai setiap detik kehidupan. Al-Quran dalam Surah Al-Hadid ayat 4 menyatakan:
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
Ma’iyyah Allāh (Kebersamaan Allah) dalam ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir, bukanlah kebersamaan spasial, melainkan ma’iyyah ‘ilmiyyah wa qadriyyah (kebersamaan dalam ilmu dan kekuasaan). Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Surah Qaf ayat 16.
Kelupaan akan Kehadiran Ilahi ini merupakan bentuk ghaflah (kelalaian) yang paling fatal. Ketika manusia hidup seolah-olah Allah tidak melihat, ia melakukan maksiat tanpa rasa malu. Ketika manusia hidup seolah-olah Allah tidak mengatur segala sesuatu, ia merasa takut kepada selain Allah. Ketika manusia hidup seolah-olah Allah tidak memberi, ia menjadi tidak bersyukur.
Munajat Sha’baniyyah dalam bagian yang lain menyatakan: “Ḥattā takhriqa abṣār al-qulūb ḥujub al-nūr fa-taṣila ilā ma’din al-‘aẓamah” (Hingga pandangan hati menembus tirai-tirai cahaya, sehingga sampai ke sumber keagungan). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dzikir yang sejati adalah raf’ al-ḥujub (mengangkat tirai) yang memisahkan antara hamba dan Tuhan, sehingga setiap saat menjadi momen mushāhadah (penyaksian) akan Kehadiran-Nya.
C. Hidup yang Tidak Autentik: Konsekuensi Kelupaan
Filsuf eksistensialis Martin Heidegger membedakan antara dua mode eksistensi manusia. Yang pertama adalah Eigentlichkeit (autentisitas), yakni hidup dengan kesadaran penuh akan kematian dan tanggung jawab eksistensial. Yang kedua adalah Uneigentlichkeit (inauthenticity), yakni hidup dalam das Man (orang kebanyakan), mengikuti arus tanpa refleksi, tanpa kesadaran akan pilihan-pilihan fundamental yang membentuk eksistensi.
Al-Quran mengungkapkan konsep yang sangat mirip dalam Surah Al-Hasyr ayat 19:
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri; mereka itulah orang-orang yang fasik.”
Ayat ini menunjukkan mekanisme kelupaan yang bersifat dialektis. Nasū Allāh (lupa kepada Allah) mengakibatkan ansāhum anfusahum (Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri), yang pada akhirnya membuat mereka menjadi fāsiqūn (keluar dari fitrah, tidak autentik).
Dari sisi pemahaman ‘irfani, ma’rifah al-nafs (pengenalan diri) tidak mungkin tercapai tanpa ma’rifah Allāh (pengenalan Allah). Hal ini karena diri manusia pada hakikatnya adalah āyah (tanda) dari Allah. Ketika tirai kelupaan menutupi pengenalan akan Allah, secara otomatis diri manusia sendiri juga tertutup dari kesadaran.
Hidup yang tidak autentik dengan demikian adalah hidup tanpa ma’nā (makna), tanpa ghāyah (tujuan yang jelas), dan tanpa aṣālah (keaslian). Manusia dalam kondisi ini dapat diibaratkan seperti zombie: bergerak tetapi tidak benar-benar hidup, bernapas tetapi tidak ḥayy (hidup dalam makna yang sebenarnya).
III. TIGA KARAKTER AHLI DZIKIR
Munajat Sha’baniyyah menyebutkan tiga konsekuensi atau karakteristik dari kontinuitas dzikir, yakni tidak memutuskan janji kepada Allah, tidak lalai dari bersyukur kepada-Nya, dan tidak memandang ringan urusan-Nya. Ketiga karakteristik ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan dalam spiritualitas yang utuh.
A. Lā Yanquḍu ‘Ahdak: Tidak Memutuskan Janji kepada-Nya
1. Konsep ‘Ahd dalam Al-Quran dan Hadits
Konsep ‘ahd (janji atau perjanjian) dalam Al-Quran memiliki dua dimensi utama. Dimensi pertama adalah ‘ahd takwīnī (janji ontologis), yakni perjanjian primordial di ‘ālam al-dharr sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-A’raf ayat 172: “Alаstu bi-rabbikum? Qālū balā” (Bukankah Aku Tuhanmu? Mereka menjawab: Ya). Dimensi kedua adalah ‘ahd tashrī’ī (janji syariat), yakni komitmen untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat, termasuk Surah An-Nahl ayat 91: “Wa awfū bi-‘ahd Allāh idhā ‘āhadtum” (Dan penuhilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji).
Dalam buku kami Jalan Cinta, ada penjelasan tentang ‘Ahdullâh.
“ ‘Ahdullâh, menurut Allamah Kamal Faqih Imani dalam Tafsir Nurul- Qur’an, bisa berarti perjanjian yang fitri yang dibawa sejak lahir, seperti cinta pada kebenaran dan cinta pada keadilan. Dahulu kita semua pernah disumpah di depan Tuhan: alastu bi rabbikum (apakah Aku ini Tuhan kalian). Kita menjawab: balâ (ya—bahwa Engkau adalah Tuhan kami). Jadi, perjanjian itu telah tertanam secara inhern secara fitri dan hakiki dalam diri kita. Ini adalah bagian dari ‘ahdillâh.
Kecintaan pada keluarga Nabi dan keluarganya juga merupakan bagian dari ‘ahdillâh. Kenapa? Karena awwalu mâ khalaqallâhu nûrî (yang pertama diciptakan Allah adalah cahayaku). Jadi, ciptaan Allah yang pertama adalah cahaya Kanjeng Nabi dan Ahlulbaitnya, dan kita semua diciptakan dari cahaya mereka. Kemudian, menurut Tafsir Nurul-Qur’an, ‘ahdillâh juga mencakup perjanjian yang rasional, yaitu bahwa akal kita mengetahui bahwa tidak mungkin ada kontradiksi dalam segala hal. Kalau semesta ini demikian teratur, maka keteraturan itu tidak mungkin tanpa ada yang mengatur. Kalau seseorang berjalan di padang pasir, lalu tiba-tiba dia menemukan sebuah rumah yang sangat indah, maka dengan akalnya yang normal, tidak mungkin dia percaya bahwa rumah itu terbangun sendiri dari debu-debu secara acak. Itu tertolak secara rasional, melanggar prinsip keteraturan, melanggar prinsip non-kontradiksi, dan melanggar prinsip sebab-akibat. Dengan kekuatan rasional itu, manusia bisa memahami bahwa semua keberadaan akan kembali kepada Al-Wajib yang wajib ada-Nya, yang tidak membutuhkan sesuatu selain diri-Nya, sementara semua yang lain bergantung kepada-Nya.
Kemudian, bagian dari seluruh alam semesta yang demikian indah dan sangat teratur ini adalah bagaimana ketika seorang bayi dilahirkan maka dia langsung mencari air susu ibunya. Susunya disediakan oleh Allah. Melalui pengaturan-Nya di alam semesta ini, dalam setiap tahap perkembangannya, setiap makhluk berjalan menuju jalan yang sudah ditentukan. Kita memiliki nafsu untuk memakan makanan tertentu, yang ketika kita makan maka itu memberikan manfaat pada diri kita.
Kita memiliki gigi yang demikian luar biasa sehingga kita bisa mengiris daging dengan mudah, tetapi setiap kali kita mengunyah, kita tidak menggigit lidah kita sendiri. Subhânallâh. Ini sungguh merupakan nikmat yang sangat besar. Untuk satu nikmat ini saja, mungkin tidak cukup umur kita untuk mensyukurinya. Belum lagi nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung banyaknya.
… Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya…. (QS Ibrâhîm [14]: 34)
Semua karunia yang demikian dahsyat ini tidak mungkin tanpa tujuan. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu maka pasti itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk kesempurnaan semua semesta agar kembali kepada-Nya.
Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya…. (QS al-Mulk [67]: 2)
Allahyarham sering berpesan bahwa yang dikehendaki bukan banyaknya amal, bukan banyaknya jumlah shalat, tetapi baiknya amal. Itu ditetapkan Allah tujuannya dalam Kitab Suci. Ini juga termasuk dalam ‘ahdullâh, yang secara potensi dan fitri sudah ada dalam diri kita.
Kemudian, yang termasuk dalam ‘ahdullâh adalah perjanjian keagamaan. Urusan keagamaan merupakan turunan dari itu semua, yang akan mengantarkan setiap manusia menuju keselamatan. Ini merupakan janji juga. Allah mengambil janji dari para Nabi, dan para Nabi mengambil kesetiaan dari kita. Menurut kitab Risâlah al-Walâyah, ketika Allamah Thabathaba’i menjelaskan tentang tauhid af ‘âl, dikutip sebuah hadis yang mengutip sebuah ayat Al-Quran. Riwayat itu masyhur, dan Ibn Arabi juga membahasnya.
Intinya, bahwa kalau kita berbaiat kepada Nabi maka itu berarti kita betul-betul telah berbaiat kepada Allah dengan persis sama. Yang layak berbaiat langsung kepada Allah hanyalah para kekasih-Nya. Adapun kita, bagaimana kita bisa berbaiat langsung kepada Allah. Kita adalah manusia biasa. Shalat kita pun tidak seratus persen khusyuk. Sebaliknya, dengan para kekasih Allah. Mereka menyebut alhamdulillâhi rabbil-‘âlamîn saja, langsung ada jawaban dari Allah yang mereka dengar. Mereka bisa berkomunikasi langsung dengan-Nya, yang tidak mungkin dapat kita lakukan. Itulah sebabnya kita berbaiat kepada para kekasih Allah melalui asyhadu an lâ ilâha illallâh wa asyhadu anna muhammadan rasûlullâh.
Dalam setiap shalat, kita berbaiat, dan itu adalah janji ketaatan 100 persen kepada Nabi saw. Kita memasrahkan diri kepada Nabi dengan sepasrah-pasrahnya dan setaat-taatnya. Jadi, semua amal ibadah, semua amal yang dilarang oleh Al-Quran, semua yang dilarang oleh Nabi, dan kemudian dijelaskan larangannya lebih jelas lagi oleh para washi, para penerus Nabi, adalah perjanjian kita dengan Allah. Ini agak berat masalahnya. Kalau kita hendak berbuat zalim kepada seseorang sekecil apa pun, itu berarti kita melanggar perjanjian kesetiaan kita dengan Nabi saw dan pelanggaran kesetiaan kita kepada Allah, bahwa kita tidak memenuhi ‘ahdillâh.
Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa dosa yang terbesar adalah menganggap kecil sebuah dosa. Kalau kita berbuat dosa kecil maka jangan dilihat dosanya, tetapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa.
Selanjutnya, kita berkomitmen terhadap janji-janji yang dibuat dengan sesama manusia, karena itu juga termasuk dalam ‘ahdillâh. Demikian menurut penjelasan Allamah Faqih Imani.
Dalam Tafsir Ash-Shâfî, dikutip sebuah hadis dari Imam Musa bin Ja‘far as yang menjelaskan bahwa ayat 20 dalam surah ar-Ra‘d—seperti yang telah dikutip di atas—diwahyukan berkenaan dengan kedudukan dan wilâyah Ahlulbait Muhammad. Ini adalah perjanjian dari Allah Swt.
Seperti telah disebutkan tadi, bahwa kita tidak bisa berjanji langsung dengan Allah. Tetapi kita sudah melakukan perjanjian dengan-Nya melalui fitrah kita. Perjanjian itu diteguhkan lagi dengan pengakuan atas wilâyah Ahlulbait Rasulullah yang menjelaskan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi saw.
Di sisi lain, kita lihat bahwa jalur wilâyah ini turun dari Allah menuju Nabi ke seluruh alam, termasuk kepada kita semua. Dari Nabi, wilâyah itu sampai kepada kita melewati para washi, para wali, dan para kekasih, yaitu keluarga Nabi. Mereka adalah pintu-pintu menuju Nabi, dan Nabi adalah pintu menuju Allah.
Jadi, salah satu arti ‘ahdillâh adalah wilâyah Ahlulbait. Jika kita tidak mengakui wilâyah Nabi, maka itu berarti kita memutus perjanjian dengan Allah Swt
“
Dalam konteks kehidupan spiritual sehari-hari, pemutusan janji ini dapat diamati dalam pola yang sangat umum. Di pagi hari, seseorang berjanji dalam hatinya: “Hari ini aku akan shalat tepat waktu.” Namun ketika siang tiba, ia sibuk dengan scrolling media sosial, rapat, atau berbagai distraksi lainnya sehingga melupakan komitmennya. Ketika maghrib tiba dan ia menyadari bahwa ia telah melewatkan shalat, ia menyesal sambil berkata: “Besok lagi deh…” Demikian siklus ini berulang-ulang.
Kontinuitas dzikir (yudīmu al-dhikr) berfungsi sebagai tadhkīr dā’im (pengingatan yang kontinyu) akan janji, sehingga tidak ada momen di mana seseorang “lupa” bahwa ia memiliki komitmen kepada Allah. Dzikir dalam pengertian ini bukan sekadar pengulangan formula verbal, melainkan kesadaran yang senantiasa hadir tentang hubungan covenant antara hamba dan Tuhan.
B. Lā Yaghfulu ‘an Shukrik: Tidak Lalai dari Bersyukur kepada-Nya
Konsep syukur dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kesadaran akan nikmat (ni’mah) yang diberikan oleh Allah. Surah At-Takatsur ayat 8 menyatakan:
ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
“Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan.”
Allamah Tabataba’i dalam Tafsir al-Mizan memberikan penjelasan yang sangat mendalam tentang ayat ini. “
Allah Ta’ala telah menciptakan manusia dan menjadikan tujuan penciptaannya—yang merupakan kebahagiaan (sa’adah) dan kesempurnaan tertingginya—adalah al-taqarrub al-‘ubūdī ilayh (pendekatan diri kepada-Nya melalui penghambaan), sebagaimana firman-Nya:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat: 56)
Tujuan ini adalah al-wilāyah al-ilāhiyyah (wilayah/kedekatan Ilahiah) bagi hamba-Nya.
Allah Subhanahu telah mempersiapkan bagi manusia segala sesuatu yang dapat membuatnya berbahagia dan memperoleh manfaat dalam perjalanannya menuju tujuan yang ia diciptakan untuknya. Segala sesuatu itu adalah al-ni’am (النعم / nikmat-nikmat). Allah telah melimpahkan kepada manusia nikmat-nikmat-Nya, baik yang zhahirah (tampak/lahiriah) maupun yang bathinah (tersembunyi/batiniah).
Penggunaan nikmat-nikmat ini dengan cara yang diridhai Allah, yang mengantarkan manusia kepada tujuan yang dikehendaki baginya, adalah jalan menuju pencapaian tujuan—dan inilah yang disebut al-thā’ah (الطاعة / ketaatan).
Adapun penggunaannya dengan cara jumūd (جمود / terpaku, stagnan) pada nikmat itu sendiri dan melupakan apa yang ada di baliknya, adalah ghayy (غي / kesesatan), dhalāl (ضلال / kesesatan), dan inqithā’ ‘an al-ghāyah (انقطاع عن الغاية / terputus dari tujuan). Inilah yang disebut al-ma’siyah (المعصية / kemaksiatan).
Allah Subhanahu telah menetapkan suatu ketetapan yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat diubah (قضاء لا يرد ولا يبدل), bahwa manusia akan kembali kepada-Nya. Di sana ia akan ditanya tentang amalnya, kemudian akan dihisab (diperhitungkan) dan diberi balasan.
…Allah Ta’ala berfirman:
﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾
“Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu-lah kesudahan (segala sesuatu).” (An-Najm: 39-42)
Maka, pertanyaan tentang amal hamba adalah pertanyaan tentang kenikmatan (al-na’īm): Bagaimana ia menggunakannya? Apakah ia bersyukur atas nikmat tersebut, ataukah ia mengingkarinya?”
Hal yang menarik juga adalah bahwa Tabatabai mengutip riwayat-riwayat bahwa yang disebut an-na’im adalah Rasulullah Saw dan Ahlubaitnya yang suci as. “Dalam Tafsir al-Qummi, dengan sanadnya dari Jamil, dari Abu Abdillah as, ia berkata: Aku bertanya kepadanya tentang ayat “Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan.” Beliau berkata: Umat ini akan ditanya tentang nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa Rasul-Nya, kemudian Ahlul Baitnya.
C. Lā Yastakhiffu bi Amrik: Tidak Memandang Ringan Urusan-Nya
1. Konsep Amr dalam Al-Quran
Kata amr dalam Al-Quran memiliki dua makna utama yang saling terkait. Makna pertama adalah amr takwīnī (perintah penciptaan), sebagaimana disebutkan dalam Surah Yasin ayat 82: “Innamā amruhu idhā arāda shay’an an yaqūla lahu kun fa-yakūn” (Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: ‘Kun (jadilah)’, maka jadilah ia). Makna kedua adalah amr tashrī’ī (perintah syariat), sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 63: “Fa-l-yaḥdhar alladhīna yukhālifūna ‘an amrihi an tuṣībahum fitnah aw yuṣībahum ‘adhābun alīm” (Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih).
Kedua dimensi amr ini saling terkait karena keduanya merupakan manifestasi dari kehendak Ilahi. Amr takwīnī adalah kehendak Allah yang diwujudkan dalam tatanan kosmis dan hukum-hukum alam, sementara amr tashrī’ī adalah kehendak Allah yang diwujudkan dalam perintah-perintah moral dan ritual. Meremehkan salah satunya berarti meremehkan kehendak Allah itu sendiri.
2. Makna Khusus: Amrunā dalam Riwayat Ahlul Bait as
Dalam banyak hadits Ahlul Bait as, kata al-amr atau amrunā (urusan kami) memiliki makna teknis yang sangat spesifik, yakni merujuk pada walāyah ahl al-bayt, kepemimpinan dan otoritas spiritual Ahlul Bait as. Pemahaman ini sangat krusial untuk memahami dimensi walayah dalam Munajat Sha’baniyyah.
Salah satu hadits yang paling eksplisit dalam hal ini adalah pernyataan Imam Ali as:
إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ
Inna amranā ṣa’bun mustaṣ’ab, lā yaḥtamiluhu illā malakun muqarrab, aw nabiyyun mursal, aw ‘abdun imtaḥana Allāhu qalbahu li-l-īmān
(Sesungguhnya urusan kami itu sulit dan sangat berat, tidak ada yang mampu memikulnya kecuali malaikat yang didekatkan, atau nabi yang diutus, atau hamba yang hatinya telah diuji Allah untuk iman. ) (Bihar al Anwar, juz 53, hal. 81)
Menurut hemat penulis, amrunā di sini merujuk pada walāyah ahl al-bayt dan ma’rifatuhum (pengenalan mendalam terhadap mereka). Ini bukan sekadar pengakuan lahiriah atau afiliasi sektarian, melainkan al-taslīm al-tāmm (penyerahan total) kepada otoritas spiritual mereka, yang memerlukan pembersihan hati dari segala bentuk ego, prasangka, dan attachment kepada selain Allah.
Hemat penulis, al-istikhfāf (meremehkan) dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah menunda-nunda amal yang diperintahkan oleh para Rasululllah Saw dan Ahlubaitnya yang suci as. Bentuk kedua adalah mendahulukan pendapat orang lain atas ajaran mereka sholatulloh wa salamullah ‘alaihim. Bentuk ketiga adalah cherry-picking, yakni mengambil sebagian ajaran dan meninggalkan sebagian yang lain sesuai selera.
Penting untuk digarisbawahi bahwa dari riwayat yang kita kutip dari Imam ‘Ali as di atas, pemahaman sejati tentang walayah dan komitmen yang tulus kepadanya memerlukan tazkiyah (pembersihan jiwa) yang mendalam, “tidak ada yang mampu memikulnya kecuali malaikat yang didekatkan, atau nabi yang diutus, atau hamba yang hatinya telah diuji Allah untuk iman. “
Dengan demikian, tidak meremehkan urusan Allah (lā yastakhiffu bi amrik) dalam konteks walayah memiliki empat implikasi praktis.
Pertama adalah penetapan prioritas yang jelas: ajaran Rasulullah Saw dan Ahlul Bait as harus didahulukan di atas pendapat-pendapat yang populer namun tidak berdasar. Kedua adalah konsistensi dalam ketaatan, bukan ketaatan yang selektif yang hanya mengikuti ajaran yang nyaman. Ketiga adalah kesungguhan serta keikhlasan dalam mempelajari, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran mereka. Keempat adalah tazkiyah yang kontinyu, membersihkan hati dari ego, fanatisme sempit, dan ujub (bangga diri), tamak, hasad dan berbagai penyakit ruh dan penyakit hati.
3. Relevansi di Era Digital
Konsep “tidak meremehkan urusan Allah” memiliki relevansi yang sangat konkret dalam konteks kehidupan digital kontemporer. Era teknologi informasi menghadirkan tantangan-tantangan etis yang belum pernah ada dalam sejarah manusia sebelumnya, dan sikap remeh-temeh terhadap urusan Allah dapat terwujud dalam berbagai bentuk baru.
Contoh pertama adalah dalam domain algoritma dan kecerdasan buatan. Ketika seorang insinyur atau perusahaan teknologi men-deploy sistem AI yang memiliki bias diskriminatif tanpa melakukan review etis yang serius, ini merupakan bentuk meremehkan perintah Allah tentang ‘adl (keadilan). Algoritma yang mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, atau kelas sosial adalah pelanggaran terhadap prinsip fundamental Islam bahwa semua manusia memiliki dignity yang sama di hadapan Allah.
Contoh kedua adalah fenomena penyebaran fitnah dan hoax di media sosial. Ketika seseorang men-share informasi yang belum diverifikasi kebenarannya, apalagi jika informasi tersebut berpotensi merugikan orang lain, ini merupakan bentuk meremehkan perintah Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 6: “Yā ayyuhā alladhīna āmanū in jā’akum fāsiqun bi-naba’in fa-tabayyanū” (Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti). Di era digital di mana informasi dapat tersebar dengan kecepatan cahaya, tanggung jawab untuk verifikasi menjadi semakin besar.
Contoh ketiga adalah pelanggaran privasi dalam konteks kapitalisme surveilans. Ketika perusahaan-perusahaan teknologi menjual data pribadi pengguna tanpa consent yang jelas, atau ketika sistem pengawasan negara melanggar privasi warga tanpa justifikasi yang kuat, ini merupakan bentuk meremehkan amanah dan ḥurmah (kehormatan) manusia yang dijamin oleh syariat Islam.
Dengan demikian, lā yastakhiffu bi amrik di era teknologi barangkali memiliki empat komitmen konkret. Pertama adalah keseriusan dalam menerapkan nilai-nilai serta akhlak dan etika Islam pada setiap aspek pengembangan dan penggunaan teknologi. Kedua adalah ketegasan untuk tidak mengkompromikan nilai-nilai fundamental demi profit atau kenyamanan semata. Ketiga adalah keaktifan dalam advokasi untuk keadilan teknologi, berbicara menentang ketidakadilan algoritmik, kapitalisme pengawasan, dan berbagai bentuk eksploitasi digital. Keempat adalah komitmen untuk mempelajari ajaran Ahlul Bait as tentang adab dan akhlak dan menerapkannya dalam konteks digital.
IV. SINTESIS: DZIKIR, AUTENTISITAS, DAN WALAYAH DI ERA DIGITAL
A. Dzikir sebagai Praxis Eksistensial
Munajat Sha’baniyyah mengajarkan bahwa dhikr bukan sekadar ritual verbal yang kosong, melainkan ḥuḍūr wujūdī (kehadiran eksistensial) yang total. Yudīmu al-dhikr (melanggengkan dzikir) berarti hidup dalam kondisi yaqaẓah (kewaspadaan spiritual) setiap saat, di mana setiap nafas menjadi tasbīḥ, setiap detak jantung menjadi dhikr, dan setiap tindakan menjadi ‘ibādah.
Lawan dari kondisi spiritual ini digambarkan dengan sangat tajam dalam Surah Al-Kahf ayat 28: “Wa lā tuṭi’ man aghfalnā qalbahu ‘an dhikrinā wa ittaba’a hawāhu wa kāna amruhu furuṭā” (Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas). Ayat ini menunjukkan rangkaian kausal yang jelas: ghaflah (kelalaian dari dzikir) mengakibatkan ittibā’ al-hawā (mengikuti hawa nafsu), yang pada gilirannya mengakibatkan kehidupan yang furuṭā (melampaui batas, chaos, tak bermakna).
B. Tiga Pilar Hidup Autentik
Dari analisis terhadap Munajat Sha’baniyyah, dapat diidentifikasi tiga pilar kehidupan yang autentik.
Pilar pertama adalah al-wafā’ bi al-‘ahd (menepati janji), yang memiliki dimensi ontologis berupa kesadaran akan identitas sejati sebagai hamba Allah, dimensi etis berupa konsistensi antara ucapan dan perbuatan, dan dimensi spiritual berupa berpegang dalam walayah. Dalam hal ini, menjaga komitmen untuk menepati janji ini hingga mengubah adab dan akhlak yang buruk dalam diri agar selaras dengan janji tersebut merupakan hal yang tidak kalah penting.
Pilar kedua adalah al-shukr al-dā’im (syukur yang kontinyu), yang meliputi dimensi kognitif berupa kesadaran akan nikmat, dimensi afektif berupa cinta kepada Pemberi, dan dimensi praksis berupa penggunaan nikmat untuk ketaatan. Dan ini juga harus ditunjukkan dengan sikap berterimakasih serta respect (memuliakan) kepada seluruh jalannya nikmat-Nya, seperti orang-tua, guru, pasangan hidup, asisten rumah tangga, tetangga, lingkungan dan semesta alam dan dan pada dasarnya seluruh semesta sebagai makhluknya.
Pilar ketiga adalah al-jiddiyyah fī al-amr (keseriusan dalam urusan), yang mencakup penolakan untuk meremehkan perintah Allah, penetapan prioritas yang jelas dengan menempatkan Allah di atas kepentingan duniawi, dan komitmen untuk menerapkan kelembutan, kasih dan akhlak Ilahiah yang dicontohkan oleh Nabi Saw dan keluarganya yang suci as di setiap domain kehidupan.
C. Walayah sebagai Jalan Menuju Autentisitas
Pertanyaan fundamental yang perlu dijawab adalah: Mengapa walayah Ahlul Bait as esensial dalam pencapaian autentisitas eksistensial? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat ditemukan dalam hadits Nabi saw yang sangat masyhur: “Anā madīnat al-‘ilm wa ‘Aliyyun bābuhā” (Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya).
Implikasi dari hadits ini sangat mendalam. Tanpa Ahlul Bait as, manusia akan tersesat dalam lautan pendapat (madhhab-madhhab yang saling bertentangan) tanpa kompas yang jelas. Tanpa mereka, ajaran Islam rentan mengalami taḥrīf (distorsi) baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanpa mereka, manusia kehilangan kompas moral yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Rasulullah Saw dan Ahlul Baitnya as adalah Al-Qur’an berjalan. Mereka adalah teladan yang sempurna. Dan pemberi petunjuk yang sempurna yang dibutuhkan oleh manusia dan kemanusiaan.
Sebaliknya, dengan mengikuti Ahlul Bait as, jalan menuju Allah menjadi jelas karena ajaran mereka adalah ṣirāṭ mustaqīm (jalan yang lurus). Dengan mereka, standar akhlak mulia menjadi konkret karena mereka adalah uswah ḥasanah (teladan terbaik) yang hidup. Dengan mereka, harapan akan syafa’at di akhirat menjadi nyata karena mereka adalah shāfi’ūn (pemberi syafa’at) bagi pengikut mereka yang tulus. Keberadaan mereka adalah kesempurnaan eksistensial bagi manusia dan kemanusiaan. Mereka yang mengikuti Rasulullah dan Ahlul Baitnya as akan selamat dan mencapai kesempurnaan.
D. Aplikasi di Era Digital: Dari Teori ke Praksis
Ajaran dalam Munajat Sha’baniyyah bukanlah ajaran yang abstrak dan terpisah dari realitas kehidupan. Sebaliknya, ajaran ini dapat dan harus diterjemahkan ke dalam praksis konkret, termasuk dalam konteks kehidupan digital kontemporer.
Berkaitan dengan yudīmu al-dhikr (melanggengkan dzikir), terdapat beberapa praksis konkret yang mungkin dapat dilakukan. Yang pertama adalah penetapan morning sacred hour, yakni satu jam pertama setelah bangun tidur yang dibebaskan dari screen dan digunakan untuk shalat dan muhasabah. Yang kedua adalah praktek mindful notifications, di mana setiap notifikasi yang masuk diperlakukan sebagai reminder untuk bertanya pada diri sendiri: “Apa yang Allah inginkan dariku saat ini?” Yang ketiga adalah penetapan satu hari per minggu di mana seseorang sepenuhnya mencoba memperkuat dimensi spiritual kehidupan misalnya dengan mengikuti majelis ilmu atau kegiatan perkhidmatan pada sesame manusia. Spiritual grounding dari praksis-praksis ini adalah kesadaran bahwa teknologi hanya alat. Algoritma tidak seharusnya mendefinisikan prioritas hidup seseorang.

Berkaitan dengan lā yanquḍu al-’ahd (tidak memutuskan janji), terdapat beberapa aplikasi praktis. Yang pertama adalah istiqamah dalam walayah yang terwujud dalam seleksi konten yang dikonsumsi, memastikan bahwa konten tersebut align dengan ajaran Rasulullah Saw dan Ahlul Baitnya yang suci as. Yang kedua adalah konsistensi antara persona online dan offline, menolak hipokrisi yang pamer religius di media sosial namun toxic di direct message. Yang ketiga adalah konsistensi dalam advocacy, di mana jika seseorang berkomitmen pada justice secara umum, ia juga harus berkomitmen pada algorithmic justice. Spiritual grounding dari praksis ini adalah kesadaran bahwa janji kepada Allah tidak terbatas pada ruang masjid, melainkan setiap klik, share, dan comment adalah manifestasi dari pemenuhan atau pelanggaran janji tersebut.
Berkaitan dengan lā yaghfulu ‘an al-shukr (tidak lalai dari syukur), aplikasi praktisnya mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah syukur atas akses informasi yang luar biasa di era digital, di mana jutaan hadits, tafsir, dan lecture tentang Ahlul Bait dapat diakses dengan mudah, dan semua ini harus dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua adalah berkontribusi pada sesama, yakni berkontribusi pada publik dengan membuat konten berkualitas dan berbagi pengetahuan, bukan hanya menjadi konsumen pasif. Yang ketiga adalah penolakan terhadap konsumerisme digital, di mana seseorang tidak hanya scroll dan consume, melainkan menciptakan nilai. Spiritual grounding dari praksis ini adalah kesadaran bahwa nikmat terbesar adalah taufik-Nya dan hidayah-Nya kepada walayah Rasulullah Saw dan Ahlul Baitnya yang suci as, dan nikmat ini harus disyukuri dengan mempelajari, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran mereka.
Berkaitan dengan lā yastakhiffu bi al-amr (tidak meremehkan urusan), aplikasi konkretnya meliputi beberapa dimensi. Yang pertama adalah penggunaan teknologi berbasis prinsip akhlak, yakni menolak untuk menggunakan atau mendukung teknologi yang merusak. Yang kedua adalah al-amr bi al-ma’rūf wa al-nahy ‘an al-munkar dalam konteks digital, yakni berbicara, menulis dan membangun budaya kritis menentang bias algoritma, kapitalisme pengawasan, dan berbagai bentuk ketidakadilan digital. Yang ketiga adalah prioritisasi ajaran Rasulullah Saw dan Ahlul Bait as di atas trending opinion yang mungkin populer namun tidak berdasar. Spiritual grounding dari praksis ini adalah kesadaran bahwa urusan Allah di era digital mencakup keadilan dalam AI, privasi, kebenaran informasi, dan keluhuran manusia, dan semua ini bukan “pilihan” melainkan kewajiban moral.
V. PENUTUP
A. Doa sebagai Manifesto Kehidupan
Munajat Sha’baniyyah bukan hanya doa yang dibaca dengan lisan, melainkan program hidup yang harus dijalani dengan sepenuh jiwa dan raga. Setiap kalimat dalam doa ini adalah komitmen eksistensial yang mendalam.
Ketika seseorang mengucapkan “Ilāhī aj’alnī mimman yudīmu dhikrak” (Ya Tuhanku, jadikanlah aku termasuk orang yang melanggengkan mengingat-Mu), ia sedang berkomitmen untuk hidup dengan kesadaran penuh akan Allah setiap saat, tidak membiarkan satu detik pun berlalu dalam kelalaian.
Ketika seseorang mengucapkan “wa lā yanquḍu ‘ahdak” (dan tidak memutuskan janji kepada-Mu), ia sedang berkomitmen untuk istiqamah dalam janji ontologis dan janji walayah, tidak terpengaruh oleh godaan dunia atau tekanan sosial.
Ketika seseorang mengucapkan “wa lā yaghfulu ‘an shukrik” (dan tidak lalai dari bersyukur kepada-Mu), ia sedang berkomitmen untuk syukur yang berkelanjutan, terutama atas nikmat terbesar yakni hidayah kepada walayah.
Ketika seseorang mengucapkan “wa lā yastakhiffu bi amrik” (dan tidak memandang ringan urusan-Mu), ia sedang berkomitmen untuk keseriusan total dalam menjalankan urusan Allah, termasuk dalam domain teknologi dan kehidupan digital.
B. Pertanggungjawaban di Hari Akhir
Al-Quran mengingatkan bahwa di akhirat nanti, manusia akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan: “Thumma la-tus’alunna yawma’idhin ‘an al-na’īm” (Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan). Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan mencakup dimensi-dimensi yang telah dibahas dalam makalah ini.
Apakah kita yudīmu al-dhikr (melanggengkan dzikir) atau ghāfilūn (lalai)? Apakah kita wafaynā bi al-‘ahd (menepati janji) atau naqaḍnāhu (memutuskannya)? Apakah kita shākirūn (bersyukur) atau kāfirūn bi al-ni’mah (mengingkari nikmat)? Apakah kita jāddūn fī al-amr (serius dalam urusan) atau mustakhiffūn (meremehkan)?
Waktu yang tersisa antara saat ini dan kematian adalah modal terakhir yang dimiliki oleh manusia. Bagaimana modal ini diinvestasikan akan menentukan nasib abadi di akhirat. Investasi terbaik adalah dengan melanggengkan dzikir, menepati janji, tidak lalai dari syukur, dan tidak meremehkan urusan Allah.
C. Doa Penutup
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُدِيمُ ذِكْرَكَ، وَلَا يَنْقُضُ عَهْدَكَ، وَلَا يَغْفُلُ عَنْ شُكْرِكَ، وَلَا يَسْتَخِفُّ بِأَمْرِكَ
Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang melanggengkan dzikir kepada-Mu, tidak memutuskan janji kepada-Mu, tidak lalai dari bersyukur kepada-Mu, dan tidak memandang ringan urusan-Mu.
وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
Dan semoga shalawat serta salam Allah tercurah kepada Muhammad dan keluarganya yang suci lagiطاهر.
Wamaa taufiiqii illa billah ‘alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniib







