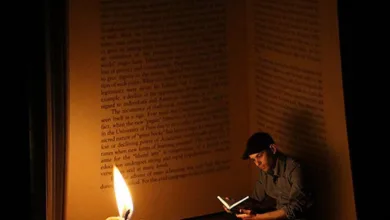Sejauh Mana Indonesia Mencapai Kedaulatan Digital?

Oleh Dr. Dimitri Mahayana, Sekretaris Dewan Syura IJABI
KEDAULATAN digital bukan sekadar jargon teknologi. Bagi penulis yang telah puluhan tahun menjadi akademisi ITB sekaligus konsultan teknologi informasi komunikasi, kedaulatan itu tentang bagaimana suatu bangsa mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri dalam mengelola data, membangun sistem, dan menegakkan aturan main di ruang digital. Namun hingga hari ini, posisi Indonesia dalam peta kedaulatan digital dunia masih jauh dari mapan. Pemanfaatan layanan berbasis maha data belum menyentuh sendi kehidupan masyarakat secara luas. Proyek besar memang mulai dijalankan, tetapi belum cukup membumi. Integrasi data antarinstansi masih berjalan lambat, dan kualitas pelayanan publik yang bergantung pengelolaan data belum menunjukkan perubahan signifikan.
Di sektor industri digital, kehadiran startup, terutama unicorn lokal, semula memberi besar harapan. Namun kenyataan, sebagian besar modal dan infrastruktur mereka masih tergantung luar negeri.
Kita masih menjadi pengguna, bukan pemilik. Bahkan situasi ironis terjadi karena founder unicorn menjual saham dan jadi sebatas karyawan.
Situasi ini sontak mengingatkan peringatan lama: jangan sampai kita kembali menjadi pesuruh di negeri sendiri. Lalu, pilar teknologi informasi dan komunikasi juga belum sepenuhnya tegak. Aturan yang mendukung kedaulatan digital sudah ada, tapi pelaksanaannya belum konsisten. Pusat data nasional belum cukup kuat menopang layanan strategis berbasis data secara mandiri. Sebagian besar lalu lintas digital nasional masih melibatkan jaringan dan server yang berada di luar negeri, membuat kita rentan secara keamanan dan ekonomi. Sementara itu, sistem pembayaran digital nasional berkembang cukup pesat. Integrasi berbagai layanan dompet digital dalam satu standar nasional sudah menjadi kenyataan. Ini langkah penting menuju kemandirian ekonomi digital. Namun adopsi layanan digital yang merata belum tercapai. Kesenjangan akses antara kota besar dan daerah pinggiran serta antara generasi digital native dan kelompok usia lanjut (baca: Baby Boomer) masih mencolok.
Kemampuan sumber daya manusia juga masih relatif lemah. Literasi digital belum menjadi bagian kebiasaan hidup sehari-hari. Banyak layanan publik berbasis teknologi yang justru membingungkan masyarakat, alih alih mempermudah; ironi di tengah gegap gempita transformasi digital. Singkatnya, kita sudah berjalan, tetapi belum sampai. Kita punya arah, tetapi jalannya masih penuh lubang. Kedaulatan digital Indonesia saat ini masih lebih berupa ambisi daripada realisasi. Ia butuh percepatan, konsistensi, dan yang terpenting gotong royong lintas sektor.
Belajar dari Zuboff
Barangkali di titik ini, kita perlu belajar dari Shoshana Zuboff. Siapakah Zuboff? Ia adalah seorang profesor emerita di Harvard Business School dan salah satu pemikir terkemuka bidang sosiologi digital, ekonomi informasi, dan dampak teknologi terhadap masyarakat.
Ia meraih gelar doktor dari Harvard dan dikenal luas melalui karya-karya pentingnya yang menganalisis hubungan antara teknologi, kekuasaan, dan kehidupan manusia. Salah satu karya paling berpengaruhnya adalah The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (2019), yang menjadi rujukan utama memahami bagaimana perusahaan teknologi besar mengeksploitasi data pribadi dalam sistem ekonomi baru yang disebutnya kapitalisme pengawasan. Karya ini menuai pujian internasional dan menjadikannya tokoh sentral dalam perdebatan global tentang privasi, etika digital, dan masa depan demokrasi.
Sebelumnya, ia juga menulis In the Age of the Smart Machine (1988) dan The Support Economy (2002), yang sama-sama menggambarkan perubahan mendalam dalam struktur kerja dan masyarakat akibat revolusi teknologi informasi. Dalam The Age of Surveillance Capitalism dikemukakan, kita sedang memasuki babak baru kapitalisme, yakni kapitalisme pengawasan. Ini bentuk kapitalisme yang tidak lagi bergantung eksploitasi tenaga kerja/sumber daya alam, melainkan pada ekstraksi data perilaku manusia.
Data yang berasal dari aktivitas sehari-hari kita (klik, gesekan layar, suara, lokasi) dikumpulkan bisa tanpa izin, diolah dengan algoritma, dan dijual untuk memprediksi serta memengaruhi perilaku kita di masa depan. Kapitalisme pengawasan, menurut Zuboff, adalah kudeta epistemik. Kudeta ini bukan menggulingkan negara, melainkan menggulingkan kedaulatan pengetahuan publik.
Di dalamnya, muncul pertanyaan mendasar yang kini dijawab sepihak oleh perusahaan teknologi: siapa yang tahu, siapa yang memutuskan siapa yang tahu, dan siapa yang memutuskan siapa yang memutuskan siapa yang tahu. Korporasi digital raksasa seperti Google, Facebook, Amazon, dan lain-lain, kini memegang kontrol pengetahuan kolektif tanpa pernah diberi mandat oleh publik. Mereka menciptakan tatanan kekuasaan baru yang tak terlihat, tak terpilih, dan nyaris tak tersentuh hukum. Kapitalisme pengawasan tidak bekerja dengan cara kekerasan fisik seperti totalitarianisme klasik. Ia menciptakan kekuasaan baru yang disebut Zuboff sebagai kekuatan instrumental—kekuatan yang bekerja secara halus, melalui prediksi, persuasi algoritmik, dan manipulasi preferensi. Pengguna tidak dipaksa, tetapi diarahkan; tidak diperbudak, tetapi dicandui.
Dalam kondisi ini, demokrasi tidak dihancurkan frontal, tetapi diurai perlahan dari dalam, melalui ketergantungan terhadap teknologi yang membentuk kesadaran dan keputusan politik kita sehari-hari. Zuboff mengkritik regulasi yang ada, baik dalam bentuk undang-undang privasi maupun kebijakan antimonopoli, tidak cukup kuat untuk menahan laju kekuasaan kapitalisme pengawasan. Dunia hukum dan kebijakan tertinggal jauh dari kecepatan teknologi. Sementara itu, berbagai fenomena sosial kontemporer, seperti kecanduan media sosial, penyebaran berita palsu, pelacakan tanpa batas, dan krisis privasi, semuanya bisa dilihat sebagai gejala logika kapitalisme pengawasan yang menempatkan keuntungan di atas hak-hak dasar manusia. Bagi Zuboff, kapitalisme pengawasan bukanlah keniscayaan teknologi, melainkan hasil pilihan ekonomi dan politik tertentu. Maka, ia bukan hanya bisa dikritik, tetapi juga harus dilawan.
Masa depan manusia di era digital tidak akan ditentukan inovasi teknologi semata, tetapi oleh keberanian politik dan etika untuk mengatakan cukup.
Dalam dunia yang semakin dikendalikan algoritma, mempertahankan martabat manusia berarti merebut kembali kedaulatan atas data, pikiran, dan masa depan kita sendiri. Dalam perspektif analisis Zuboff, kondisi kedaulatan digital di Indonesia mencerminkan tahap awal kolonisasi algoritmik, di mana negara dan masyarakat belum sepenuhnya sadar bahwa ruang digitalnya tengah diambil alih oleh kekuatan kapitalisme pengawasan global. Platform-platform asing yang mendominasi kehidupan digital masyarakat (dari pencarian informasi, belanja, hingga interaksi sosial) telah menanamkan sistem pengumpulan data masif tanpa transparansi, akuntabilitas, atau kontrol yang memadai dari negara maupun publik. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan pun masih belum cukup tangguh menghadang ekspansi kekuatan instrumental perusahaan teknologi yang, menurut Zuboff, tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga membentuk struktur pengetahuan dan perilaku kolektif.
Dalam situasi ini, Indonesia berada pada risiko kehilangan kedaulatannya bukan karena penjajahan fisik, tetapi karena ketidaksadaran epistemik. Yakni rakyat tidak lagi menjadi subjek demokrasi digital, melainkan objek prediksi dan manipulasi perilaku yang dikendalikan dari luar negeri.
Saran Hexapelix menuju kedaulatan digital
Kedaulatan digital tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah. Perlu pendekatan kolaboratif antara, tidak lagi penta/lima tapi hexa/tujuh unsur utama. Yaitu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, akademisi dan pendidikan, budayawan (tpenulis, seniman dan selebgram), serta media massa. Pemerintah harus segera menata ulang strategi digital nasional yang lebih berpihak kepentingan domestik. Salah satu contoh nyata adalah perdebatan seputar proyek pembangunan pusat data nasional yang justru sempat dikerjasamakan dengan perusahaan luar negeri. Hal ini menunjukkan ambiguitas antara semangat kedaulatan digital dan praktik yang justru membuka pintu bagi ketergantungan. Pemerintah juga belum optimal melindungi data pribadi warga. Meski UU Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, aturan turunannya lamban disiapkan dan pengawasan implementasinya masih lemah. Dalam proyek tol langit yang menjanjikan konektivitas nasional melalui satelit multifungsi, koordinasi antarlembaga dan kepastian manfaat riil bagi daerah tertinggal pun masih perlu diuji. Regulator harus menjadi pemimpin yang tegas dalam membangun infrastruktur digital yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai fasilitator proyek.
Pelaku usaha, terutama startup dan perusahaan teknologi lokal harus didorong tidak sekadar mengejar valuasi, tetapi juga memperkuat kemandirian ekosistem digital Indonesia. Investasi pada pusat data lokal, pengembangan kecerdasan buatan dalam negeri, dan model bisnis yang memberdayakan pelaku usaha mikro sangat penting untuk diperkuat. Masyarakat sipil memiliki peran utama menjaga etika digital dan mengawal transparansi penggunaan data publik. Komunitas digital dapat menjadi jembatan antara teknologi dan warga biasa, membangun kepercayaan sekaligus menjaga akuntabilitas. Lebih lanjut, mengambil perspektif Zuboff, kita perlu mengembangkan kesadaran epistemik kolektif: menyadari bahwa ruang digital bukan ruang netral, tetapi arena perebutan kekuasaan yang menentukan masa depan kita. Pemerintah harus hadir bukan sekadar sebagai fasilitator pasar digital, tetapi sebagai penjaga batas etika dan pelindung martabat warganya.
Pendidikan digital harus diarahkan membangun ketahanan terhadap manipulasi algoritmik, bukan hanya kecakapan teknis. Ekosistem startup lokal perlu dirangsang untuk mengedepankan nilai keberlanjutan dan kemandirian, bukan sekadar mengejar valuasi. Dalam semangat ini, kita tidak hanya perlu Pentahelix kolaborasi lintas sektor, tetapi juga revolusi batin yang menyadari bahwa kedaulatan digital adalah soal harga diri bangsa/harga diri manusia. Jika itu mampu tumbuh dalam kesadaran kolektif kita, maka kedaulatan digital Indonesia bukan hanya mungkin, tetapi niscaya. Dalam hal melawan kapitalisme pengawasan digital melalui membangun kesadaran epistemik dan revolusi batin, maka kampus, budayawan, serta media massa memegang peran penting membentuk kesadaran kolektif. Akademisi dan kampus harus terlibat riset strategis berorientasi kebutuhan bangsa. Pendidikan digital perlu menyentuh tidak hanya mahasiswa, tetapi juga guru, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal. Literasi digital harus menjadi program nasional lintas usia dan latar belakang. Budayawan Indonesia termasuk seniman, selebgram, penulis, musisi, dan artis memegang peran vital sebagai penjaga nalar publik dan penjaga jiwa bangsa. Mereka bukan sekadar penghibur atau pengisi ruang digital, tetapi pemahat kesadaran yang mampu menghidupkan makna, mempertanyakan norma-norma algoritmik, dan membuka ruang imajinasi alternatif atas masa depan yang lebih manusiawi. Dalam dunia yang dibanjiri konten dan dikendalikan logika viral, para budayawan harus menjadi suara yang menggugah bukan sekadar gema. Dalam hal ini, para budayawan seharusnya bersatu melawan konten-konten sampah yang mengedepankan flexing, mendorong hasrat judol, pinjol, mengedepankan konsumerisme, dan berbagai penyakit baru materialisme gaya baru. Indonesia perlu mendorong budayawannya untuk progresif dan mereka cipta karya-karya emas seperti Rindu Rasul dari Bimbo, channel Bagus Mulyadi, gaya mencerahkan Fakhruddin Faiz, Tanpa Kekasihku dari Kahitna, Padi Untuk Rakyat dari Franky Sahilatua, Rayuan Pulau Kelapa dari Ismail Marzuki, maupun mempertahankan secara kreatif warisan keragaman budaya yang luar biasanya.
Mengambil konsep Yukhui (pewaris intelektual Heideger dan Stiegler), sesungguhnya keragaman ini bagian penting dari perlawanan terhadap hegemoni data dan ditigal kapitalisme pengawasan. Kemudian, media massa lewat narasi yang kuat dan peliputan mendalam bisa mendorong kebijakan publik yang berpihak kedaulatan digital serta mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dan mandiri dalam menyikapi perkembangan teknologi. Dengan sinergi hexahelix ini, kedaulatan digital Indonesia tidak akan berhenti pada mimpi, tapi sangat mungkin menjadi kenyataan. Syaratnya yang tidak mudah: harus dikerjakan bersama berkesinambungan dengan visi tegak dan tekad tidak mudah goyah. Mampukah? Kita bisa!
Sumber : https://tekno.kompas.com/read/2025/07/14/11410337/sejauh-mana-indonesia-mencapai-kedaulatan-digital