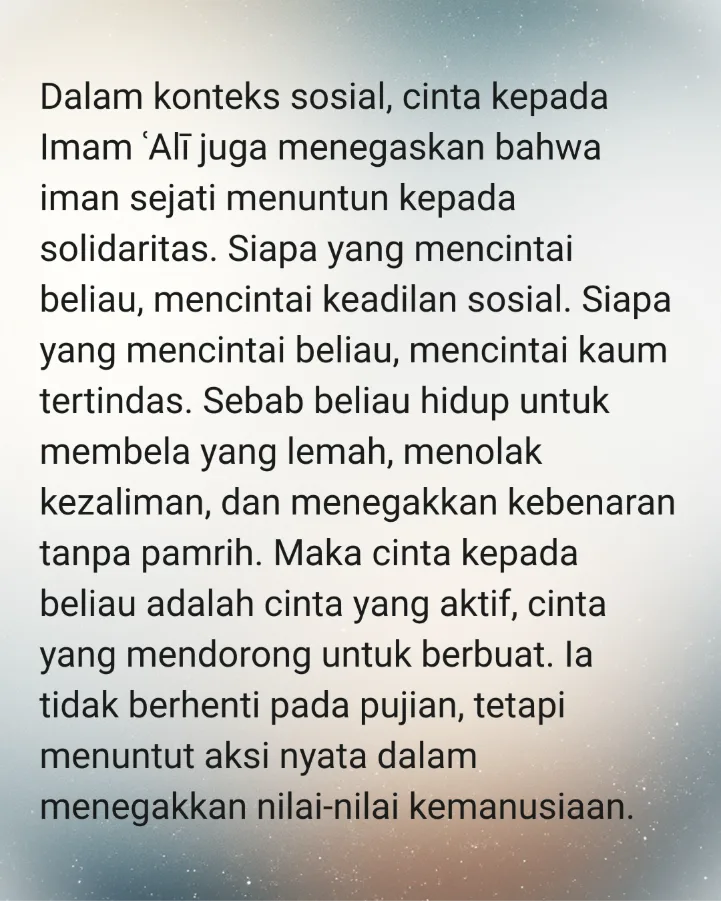Penulis Abdul Karim
Cinta selalu menjadi inti dari setiap pencarian spiritual manusia. Ia bukan hanya emosi, tetapi keadaan batin yang menghubungkan manusia dengan sumber makna yang lebih tinggi. Dalam Islam, cinta tidak sekadar perasaan yang lahir dari afeksi, melainkan bagian dari struktur iman. Cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang telah menjadi perwujudan nilai-nilai ilahiah merupakan poros bagi seluruh amal dan keyakinan. Di antara tokoh yang menjadi pusat dimensi cinta tersebut, Imam ʿAlī ibn Abī Ṭālib menempati posisi yang tak tergantikan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa mencintai Imam ʿAlī adalah tanda iman, dan membencinya adalah tanda kemunafikan. Hadis ini bukan sekadar penilaian emosional, melainkan pernyataan metafisik tentang hubungan antara pengetahuan, kebenaran, dan cinta. Imam ʿAlī menjadi simbol iman yang hidup karena dalam dirinya tercermin keseimbangan antara ilmu, amal, dan kasih.
Makna cinta kepada Imam ʿAlī sebagai tanda iman dapat dibaca dalam dua lapis makna: yang pertama bersifat eksoteris, yaitu kecintaan sebagai bentuk kesetiaan kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi; dan yang kedua bersifat esoteris, yakni cinta sebagai penyatuan batin dengan nur kenabian. Dalam dimensi pertama, mencintai beliau berarti berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, keberanian, dan keikhlasan. Dalam dimensi kedua, mencintai beliau berarti menyelaraskan hati dengan sumber hikmah yang menjadi warisan Nabi. Dengan demikian, cinta kepada Imam ʿAlī tidak berhenti pada bentuk penghormatan personal, melainkan berkembang menjadi orientasi eksistensial yang menuntun manusia menuju iman yang sejati.
Hadis yang menyebut “lā yuḥibbu ʿAlīyan illā muʾmin, wa lā yubghiḍuhu illā munāfiq” tidak hanya menggambarkan cinta sebagai ukuran iman, tetapi juga mengungkapkan keterkaitan antara batin yang beriman dan kemampuan untuk mencintai kebenaran. Dalam diri Imam ʿAlī, kebenaran itu bukan ide abstrak, tetapi kenyataan hidup. Ia menjadi manifestasi nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan manusia. Karena itu, mencintainya berarti mencintai kebenaran yang hidup, dan membencinya berarti menolak cerminan nilai-nilai Tuhan dalam dunia. Hadis tersebut menunjukkan bahwa cinta sejati tidak lahir dari kedekatan lahiriah, tetapi dari kesesuaian batin dengan hakikat kebenaran.
Iman dalam Islam selalu bersifat dinamis. Ia bukan sekadar pernyataan lisan, tetapi proses kesadaran yang berkembang melalui pengetahuan, pengalaman, dan kasih. Cinta kepada Imam ʿAlī menjadi ukuran karena ia menguji kedalaman iman seseorang terhadap nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Rasulullah. Imam ʿAlī adalah cermin keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Siapa yang mencintainya berarti mencintai keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan itu sendiri. Maka cinta kepada beliau bukan bentuk kultus personal, melainkan manifestasi cinta kepada prinsip-prinsip yang diembannya. Dengan kata lain, cinta kepada Imam ʿAlī adalah cinta kepada kebenaran yang terwujud dalam sosok manusia yang sempurna.

Dalam pandangan teologis, cinta memiliki akar yang dalam dalam struktur iman. Ia adalah bentuk tertinggi dari pengetahuan karena mengandung kesatuan antara mengetahui dan mengalami. Cinta kepada Imam ʿAlī adalah bentuk maʿrifah yang aktif, sebab ia menuntut pemahaman terhadap nilai-nilai ilahiah yang diwujudkan dalam kehidupan beliau. Cinta ini tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang meniru akhlak dan sikapnya. Seorang yang mencintai Imam ʿAlī dituntut untuk berani dalam kebenaran, sabar dalam penderitaan, dan teguh dalam prinsip. Dengan demikian, cinta menjadi sarana pembentukan moral dan spiritual yang menghidupkan iman.
Imam ʿAlī memandang cinta sebagai kekuatan yang menyatukan seluruh aspek keberadaan manusia. Ia berkata, “al-ḥubb ʿaqdun bayna al-arwāḥ qabla al-ajsād,” bahwa cinta adalah ikatan antara ruh sebelum jasad diciptakan. Kalimat ini menunjukkan bahwa cinta sejati memiliki akar kosmik, bukan sekadar hasil interaksi sosial. Maka ketika hadis menegaskan bahwa mencintai Imam ʿAlī adalah tanda iman, ia mengacu pada kesesuaian ruhani antara manusia dan sumber kebenaran. Ruh yang bersih akan mencintai cahaya, dan hati yang beriman akan mencintai keadilan. Karena itu, cinta kepada Imam ʿAlī adalah cerminan kondisi spiritual seseorang: ia menunjukkan apakah hati itu dekat dengan cahaya atau terperangkap dalam kegelapan.
Dalam konteks sejarah, cinta kepada Imam ʿAlī juga menjadi ujian kesetiaan terhadap risalah Nabi. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam menghadapi berbagai ujian politik dan moral. Di tengah pertentangan itu, kecintaan kepada Imam ʿAlī menjadi pembeda antara mereka yang berpegang pada nilai kebenaran dan mereka yang terjebak dalam ambisi duniawi. Banyak sahabat besar yang memuliakan beliau bukan karena hubungan darah, tetapi karena menyadari bahwa kebijaksanaan dan keadilan yang ia miliki adalah warisan langsung dari Nabi. Mereka memahami bahwa mencintai Imam ʿAlī adalah bagian dari mencintai Rasulullah, sebab beliau adalah penjaga risalah itu dalam bentuk yang paling murni.
Dalam tradisi tasawuf, cinta kepada Imam ʿAlī menjadi simbol dari cinta kepada kebenaran batin. Para sufi melihat beliau sebagai teladan insan kamil, manusia yang telah mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Melalui dirinya, cinta menjadi jalan menuju Tuhan. Mereka menganggap bahwa mencintai Imam ʿAlī berarti membuka diri terhadap hikmah dan maʿrifah. Karena itu, dalam banyak tarekat, silsilah spiritual berawal dari beliau. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Imam ʿAlī bukan sekadar ekspresi emosional, tetapi jalan intelektual dan spiritual yang menuntun manusia kepada penyatuan dengan sumber segala cinta.
Dari sisi filsafat moral, cinta kepada Imam ʿAlī dapat dipahami sebagai ekspresi dari virtue ethics, etika kebajikan yang menekankan pembentukan karakter melalui teladan. Dalam etika seperti ini, seseorang tidak menjadi baik karena mengikuti aturan, tetapi karena mencintai kebaikan itu sendiri. Imam ʿAlī menjadi teladan bagi kebajikan yang hidup, bukan karena teori, tetapi karena kesempurnaan praksis. Maka mencintainya berarti meniru kebajikannya, bukan mengaguminya dari kejauhan. Cinta seperti ini adalah cinta yang transformatif, yang mengubah manusia menjadi lebih bijak, lebih adil, dan lebih rendah hati.
Cinta dalam pandangan Imam ʿAlī juga adalah sumber keberanian. Ia pernah berkata, “al-qalb al-muḥibb lā yakhāf,” hati yang mencintai tidak mengenal takut. Cinta kepada kebenaran menyingkirkan rasa takut karena ia menautkan manusia kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Inilah yang menjelaskan mengapa cinta kepada beliau menjadi ukuran iman: karena iman sejati menumbuhkan keberanian moral. Orang yang benar-benar mencintai Imam ʿAlī akan berani berkata benar di hadapan penguasa, berani menegakkan keadilan meskipun merugikan dirinya, dan berani menolak kebatilan walau harus sendirian. Dalam cinta seperti ini, iman menemukan ekspresinya yang paling nyata.
Dari perspektif psikologi spiritual, cinta kepada Imam ʿAlī dapat dilihat sebagai energi penyembuh yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Cinta menumbuhkan empati, kerendahan hati, dan keinginan untuk berbuat baik. Dalam dunia yang diliputi kebencian, cinta seperti ini menjadi bukti bahwa iman masih hidup. Ketika hati manusia mencintai sosok yang meneladankan keadilan, kebijaksanaan, dan pengorbanan, maka hatinya sedang mencintai cermin dari nilai-nilai ilahiah. Cinta ini melatih jiwa untuk keluar dari ego dan menempatkan diri dalam pelayanan kepada kebenaran. Dengan demikian, cinta kepada Imam ʿAlī menjadi latihan spiritual yang menghidupkan nilai-nilai iman dalam keseharian.
Namun cinta sejati tidak lahir tanpa pengetahuan. Ia harus berakar pada pemahaman. Imam ʿAlī pernah berkata bahwa manusia mencintai sesuatu karena mereka mengenalnya, dan mereka membencinya karena mereka tidak mengenalnya. Maka cinta kepada beliau adalah hasil dari pengetahuan tentang siapa beliau dan apa yang beliau wakili. Mengetahui keberanian beliau di medan perang, kebijaksanaan dalam memutuskan hukum, dan kesederhanaan dalam hidup, akan menumbuhkan cinta yang rasional sekaligus spiritual. Pengetahuan seperti ini melindungi cinta dari taklid buta dan mengubahnya menjadi bentuk kesadaran.
Dalam masyarakat modern yang terpecah oleh ideologi, cinta kepada Imam ʿAlī dapat menjadi jembatan bagi nilai universal. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati tidak menuntut keseragaman, tetapi keadilan. Ia mencintai karena kebenaran, bukan karena golongan. Prinsip ini sangat relevan di masa kini, ketika agama sering disalahgunakan untuk membenarkan kebencian. Cinta kepada Imam ʿAlī mengajarkan bahwa iman bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling tulus dalam cinta. Dalam diri beliau, iman menjadi lembut dan kuat sekaligus: lembut dalam kasih, kuat dalam prinsip.
Dalam konteks sosial, cinta kepada Imam ʿAlī juga menegaskan bahwa iman sejati menuntun kepada solidaritas. Siapa yang mencintai beliau, mencintai keadilan sosial. Siapa yang mencintai beliau, mencintai kaum tertindas. Sebab beliau hidup untuk membela yang lemah, menolak kezaliman, dan menegakkan kebenaran tanpa pamrih. Maka cinta kepada beliau adalah cinta yang aktif, cinta yang mendorong untuk berbuat. Ia tidak berhenti pada pujian, tetapi menuntut aksi nyata dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam kerangka epistemologi spiritual, cinta kepada Imam ʿAlī menunjukkan bahwa iman bukan hanya urusan keyakinan, tetapi juga cara mengetahui. Cinta membuka jalan bagi pengetahuan yang lebih dalam, karena ia melibatkan seluruh diri: akal, hati, dan jiwa. Melalui cinta, manusia mampu memahami hal-hal yang tak terjangkau oleh logika murni. Dengan mencintai Imam ʿAlī, seseorang tidak hanya memahami beliau sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai prinsip kebenaran yang hidup dalam dirinya. Cinta menjadikan pengetahuan itu personal dan eksistensial.
Pada akhirnya, cinta kepada Imam ʿAlī adalah ukuran yang menyingkap kedalaman iman seseorang. Ia menuntut pengetahuan, keberanian, dan pengorbanan. Ia tidak bisa dipisahkan dari amal dan keadilan. Cinta seperti ini adalah cinta yang membentuk manusia, bukan cinta yang menidurkan. Dalam cinta kepada Imam ʿAlī, iman menemukan bentuknya yang paling konkret: bukan sekadar percaya, tetapi hidup dalam nilai-nilai yang beliau perjuangkan. Cinta ini bukan sekadar emosi, tetapi prinsip hidup; bukan sekadar afeksi, tetapi tindakan; bukan sekadar kata, tetapi jalan menuju Tuhan.

Abdul Karim
Guru matematika SMUTH 2000 - 2005 dan praktisi pendidikan matematika dan IT