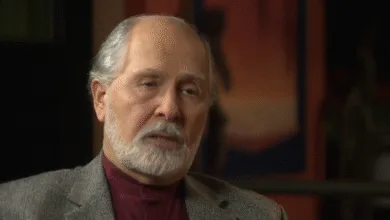Oleh : Dr. Dimitri Mahayana (Sekretaris Dewan Syura IJABI)
Induksi merupakan salah satu metode penalaran fundamental yang mendasari cara manusia memahami dunia. Secara sederhana, induksi adalah proses penarikan kesimpulan umum berdasarkan pengamatan terhadap kejadian-kejadian khusus yang berulang. Metode ini beroperasi dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari pengalaman sehari-hari hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia secara alamiah menggunakan penalaran induktif. Ketika seseorang mengamati matahari terbit dari timur setiap pagi selama bertahun-tahun, ia akan menyimpulkan bahwa matahari akan selalu terbit dari timur. Demikian pula, seorang ibu yang berkali-kali memanaskan air dan mengamati bahwa air selalu mendidih pada suhu 100 derajat Celsius akan meyakini bahwa fenomena ini akan terus berlangsung. Contoh lain dapat ditemukan dalam pengalaman seorang anak yang jatuh dari sepeda dan merasakan sakit, kemudian mengamati temannya mengalami hal serupa, sehingga ia menyimpulkan bahwa jatuh akan selalu menyebabkan rasa sakit.
Dalam ranah sains, induksi memainkan peran sentral dalam pembentukan teori-teori ilmiah. Isaac Newton, misalnya, melakukan pengamatan berulang terhadap benda-benda yang jatuh dan menyimpulkan adanya gaya gravitasi yang menarik benda menuju pusat bumi. Metode induktif ini telah menjadi fondasi bagi revolusi ilmiah yang mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta.
Perkembangan teknologi AI juga sangat bergantung pada prinsip induktif. Sistem pembelajaran mesin (machine learning) bekerja dengan menganalisis jutaan contoh data untuk kemudian menarik pola umum. Ketika sebuah sistem AI dilatih dengan ribuan kalimat yang mengandung kata “tidak” sebelum kata sifat positif, sistem tersebut akan menginduksi bahwa konstruksi semacam itu mengindikasikan sentimen negatif. Demikian pula, sistem prediksi cuaca menggunakan data historis puluhan tahun untuk menginduksi bahwa keberadaan awan hitam tebal biasanya diikuti oleh hujan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa induksi merupakan mekanisme fundamental yang memungkinkan manusia dan mesin untuk belajar dari pengalaman dan membuat prediksi tentang masa depan.
Problem Induksi
Meskipun induksi tampak sebagai metode yang intuitif dan berguna, para filsuf telah mengidentifikasi sejumlah masalah mendasar yang mempertanyakan validitas logis dari penalaran induktif. Beberapa pemikir besar dalam sejarah filsafat telah menyumbangkan kritik-kritik yang hingga kini masih menjadi perdebatan serius dalam epistemologi dan filsafat ilmu.

Induksi sebagai Kebiasaan Psikologis
David Hume (1711-1776) dalam karyanya A Treatise of Human Nature dan Enquiry Concerning Human Understanding mengajukan problem induksi yang paling fundamental. Hume mempertanyakan dasar rasional dari keyakinan kita bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu. Menurutnya, tidak ada justifikasi logis untuk melakukan lompatan dari pernyataan “sesuatu telah terjadi berulang kali” menuju pernyataan “sesuatu akan selalu terjadi”. Asumsi bahwa alam bersifat seragam (uniformity of nature) tidak dapat dibuktikan baik melalui induksi maupun deduksi, karena pembuktian melalui induksi akan bersifat sirkular (melingkar), sementara tidak ada bukti deduktif a priori untuk uniformitas alam.
Hume menyimpulkan bahwa induksi pada dasarnya hanyalah kebiasaan atau custom psikologis, bukan penalaran rasional yang valid. Ilustrasi yang sering digunakan untuk menggambarkan problem ini adalah kasus seekor ayam yang setiap hari diberi makan oleh petani pada jam tujuh pagi. Setelah seribu hari mengalami perlakuan yang sama, ayam tersebut “menginduksi” bahwa petani adalah sosok yang baik hati dan akan selalu memberinya makan. Namun pada hari yang keseribu satu, petani datang bukan dengan makanan, melainkan untuk menyembelih ayam tersebut. Pengalaman ribuan hari ternyata tidak memberikan jaminan apapun tentang hari berikutnya. Ini menunjukkan bahwa induksi, betapapun kuatnya berdasarkan pengalaman, tidak memiliki fondasi logis yang kuat.

Falsifikasi versus Verifikasi
Karl Popper (1902-1994) dalam The Logic of Scientific Discovery mengembangkan kritik terhadap induksi dengan mengajukan falsifikasionisme sebagai alternatif metodologi ilmiah. Popper berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak dibangun melalui verifikasi induktif, melainkan melalui falsifikasi deduktif. Menurutnya, tidak ada jumlah observasi positif yang dapat membuktikan kebenaran universal suatu teori, tetapi hanya diperlukan satu observasi negatif untuk membantahnya.
Ilustrasi klasik yang digunakan Popper adalah kasus angsa. Selama ribuan tahun, orang-orang Eropa mengamati angsa dan semuanya berwarna putih. Berdasarkan jutaan observasi ini, mereka menyimpulkan secara induktif bahwa “semua angsa berwarna putih”. Namun ketika penjelajah Eropa tiba di Australia, mereka menemukan angsa berwarna hitam. Hanya diperlukan satu angsa hitam untuk meruntuhkan kesimpulan yang dibangun dari jutaan pengamatan. Popper menegaskan bahwa hipotesis ilmiah tidak pernah dapat diverifikasi secara pasti melalui induksi, melainkan hanya dapat “belum terbantah” atau corroborated. Oleh karena itu, metode ilmiah yang valid adalah mengajukan hipotesis yang dapat difalsifikasi, kemudian mencoba membantahnya secara deduktif.

Falasi Generalisasi
Bertrand Russell (1872-1970) dalam The Problems of Philosophy dan sejumlah esainya tentang induksi mengkritik apa yang disebutnya sebagai “induksi melalui enumerasi sederhana” atau hasty generalisation. Russell menunjukkan bahwa penalaran berbentuk “karena A1, A2, hingga An memiliki sifat P, maka semua A memiliki sifat P” merupakan falasi logis yang dikenal sebagai hasty generalization atau generalisasi tergesa-gesa.
Russell terkenal dengan parabelnya tentang ayam induktif. Seekor ayam mengamati bahwa setiap hari petani memberinya makan. Pada hari pertama, ayam berpikir ini mungkin kebetulan. Pada hari kesepuluh, ayam mulai merasa ada pola. Pada hari keseratus, ayam memiliki tingkat kepercayaan sembilan puluh persen. Pada hari keseribu, ayam memiliki keyakinan hampir absolut bahwa petani akan selalu memberinya makan. Namun pada pagi hari Natal, petani datang bukan dengan makanan, melainkan dengan pisau. Kepastian induktif yang dibangun dari seribu hari pengalaman ternyata sama sekali tidak valid pada hari keseribu satu. Russell menegaskan bahwa kuantitas observasi tidak menjamin validitas kesimpulan induktif. Induksi enumeratif sederhana, betapapun banyaknya data yang dikumpulkan, tetaplah merupakan kesalahan logis.

Paradoks Grue
Nelson Goodman (1906-1998) dalam Fact, Fiction, and Forecast mengajukan apa yang disebutnya sebagai “teka-teki baru tentang induksi” atau New Riddle of Induction melalui paradoks “grue“. Goodman menciptakan predikat baru yaitu “grue” yang didefinisikan sebagai “hijau jika diamati sebelum tahun 2100, dan biru jika diamati setelahnya”. Sampai saat ini, di tahun 2025, semua zamrud yang kita amati berwarna hijau, dan karenanya juga “grue” (karena belum melewati tahun 2100).
Berdasarkan observasi yang sama, kita dapat membentuk dua hipotesis induktif yang berbeda. Hipotesis pertama menyatakan “semua zamrud hijau”, yang memprediksi zamrud akan tetap hijau selamanya. Hipotesis kedua menyatakan “semua zamrud grue“, yang memprediksi zamrud akan berubah menjadi biru setelah tahun 2100. Kedua hipotesis ini sama-sama didukung oleh seluruh bukti empiris yang ada hingga saat ini, namun memberikan prediksi yang saling bertentangan untuk masa depan. Goodman menunjukkan bahwa tidak ada kriteria objektif atau netral untuk memilih hipotesis mana yang lebih valid. Ini berarti validitas induksi relatif terhadap pilihan bahasa atau sistem predikat yang digunakan, yang pada dasarnya bersifat arbitrer.

Paradigma dan Relativitas Induksi
Thomas Kuhn (1922-1996) dalam The Structure of Scientific Revolutions mengajukan kritik terhadap pandangan bahwa sains berkembang secara kumulatif dan objektif melalui induksi. Kuhn berpendapat bahwa ilmuwan tidak melakukan induksi dalam ruang hampa, melainkan selalu dalam konteks paradigma tertentu. Paradigma adalah kerangka kerja konseptual yang menentukan masalah apa yang dianggap penting, metode apa yang dianggap valid, dan bagaimana data harus diinterpretasikan.
Kuhn menunjukkan bahwa data empiris yang sama dapat diinduksi menjadi kesimpulan yang sangat berbeda tergantung pada paradigma yang digunakan. Sebagai contoh, dalam paradigma fisika Newton, pengamatan terhadap gerakan planet-planet menghasilkan induksi bahwa gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara massa. Namun dalam paradigma fisika Einstein, pengamatan yang sama diinduksi menjadi kesimpulan bahwa gravitasi adalah kelengkungan ruang-waktu. Pergeseran paradigma atau revolusi ilmiah bukan merupakan hasil dari akumulasi induktif yang rasional, melainkan perubahan fundamental dalam cara memandang realitas. Dengan demikian, Kuhn menunjukkan bahwa induksi bukanlah proses objektif dan linier, melainkan terdistorsi oleh teori dan keyakinan yang sudah ada, serta bersifat revolusioner dan tidak sepenuhnya rasional.
Induksi sebagai Gerak Eksistensial
Tulisan ini adalah suatu upaya , yang bermula dari sebuah gagasan, barangkali dalam konsep gradasional eksistensi , nilai kebenaran bagi induksi tidak mutlak nol (salah total), atau satu (benar total). Barangkali, letak yang lebih baik, benar dan indah dari jawaban masalah ini adalah menerima sifat alamiah induksi sebagai bagian dari gradasional kebenaran yang tidak lain adalah manifestasi atau implikasi dari sifat gradasional eksistensi.
Penggagas gradasi eksistensi, Mulla Sadra (Sadr ad-Din ash-Shirazi, 1571-1640) adalah filsuf Muslim Persia yang mengembangkan sistem filsafat komprehensif yang dikenal sebagai al-Hikmah al-Muta’aliyah atau Hikmah Transenden.
Bila kita refleksikan dalam kerangka piker Mulla Sadra, mungkin kita tidak lagi bisa memandang induksi sebagai persoalan logika formal semata, melainkan sebagai proses ontologis dan epistemologis yang melibatkan relasi mendalam antara subjek pengenal dan objek yang diketahui.
Tulisan ini mencoba merefleksika lima prinsip fundamental yang barangkali bisa menjawab problem induksi.
Tashkik al-Wujud (Gradasi Wujud)
Prinsip pertama dalam filsafat Sadra adalah tashkik al-wujud atau gradasi wujud, yang menyatakan bahwa wujud atau eksistensi bersifat bertingkat-tingkat, bukan homogen. Setiap fenomena dalam alam semesta memiliki intensitas eksistensi yang berbeda, namun semuanya berkesinambungan dalam satu realitas tunggal. Realitas tidak tersusun dari entitas-entitas terpisah yang teratomisasi, melainkan merupakan kontinuum gradasi dari satu prinsip eksistensial yang sama.

Bagi saya yang mengajar nyaris tiga dekade mata kuliah Probabilitas dan Statistika, sungguh gagasan gradasi wujud ini serupa tapi tak sama dengan probabilitas. Lebih mendalam tentang hal ini, para pembaca dipersilakan membaca buku tulisan saya dan Agus Nggermanto dengan pengantar Budi Sulistyo, Probabilitas et Realitas yang diterbitkan Penerbit ITB (2025).
Sifat gradasional eksistensi memberikan jawaban terhadap kritik Hume tentang problem induksi. Hume mengatakan bahwa tidak ada jembatan logis antara “A telah terjadi” dan “A akan terjadi lagi”, sehingga induksi hanyalah kebiasaan psikologis.
Dalam kerangka fikir gradasi eksistensi Sadra, jembatan tersebut bukan terletak pada logika formal, melainkan pada realitas eksistensi atau wujud itu sendiri. Setiap kejadian atau fenomena adalah tajalli atau manifestasi dari prinsip eksistensial yang satu, yaitu al-wujud al-munbasit (wujud yang meluas).
Keteraturan yang kita amati dalam alam bukanlah sekadar kebetulan yang berulang, melainkan refleksi dari kontinuitas eksistensial yang nyata. Maka ketika kita menginduksi bahwa matahari akan terbit besok, kita tidak sekadar mengikuti kebiasaan psikologis, melainkan menangkap keteraturan ontologis yang inheren dalam struktur realitas itu sendiri.
Untuk memahami prinsip ini, dapat dibayangkan analogi dengan kode program dalam sebuah permainan video. Ketika pemain menekan tombol tertentu dan karakter melompat, ini bukan karena pemain “terbiasa” melihat hal itu, melainkan karena ada struktur kode program yang real yang mendasari perilaku tersebut. Demikian pula, alam semesta memiliki “struktur eksistensial” yang membuat keteraturan menjadi nyata, bukan ilusi atau kebiasaan. Induksi yang sahih adalah induksi yang berhasil menangkap keteraturan ontologis ini, bukan sekadar menghitung frekuensi kejadian.
Namun demikian, satu yang tidak dibantah oleh argument ini adalah tidak adanya kebenaran mutlak atau absolut dalam kesimpulan “matahari akan terbit besok”. Jadi , posisi yang ditawarkan akan nilai kebenarannya pun gradasional. Dari sini , mau tidak mau kita meninggalkan pola pikir black and white (hitam dan putih), dan lebih bisa memandang problem induksi Hume dan solusi yang diadopsi dari sifat gradasional eksistensi Sadra dengan pola pikir kebenaran gradasional yang banyak level abu-abu, merentang atau meluas dari putih ke hitam.
Al-‘Ilm al-Huduri (Pengetahuan Hadiri)
Prinsip epistemologis kedua dalam filsafat Sadra adalah pembedaan antara dua jenis pengetahuan. Pertama adalah al-‘ilm al-husuli atau pengetahuan representasional, yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh melalui perantara konsep atau gambaran mental. Kedua adalah al-‘ilm al-huduri atau pengetahuan hadiri, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui kehadiran langsung objek dalam kesadaran subjek tanpa perantara konseptual.
Prinsip ini memberikan jawaban terhadap kritik Popper tentang ketidakpastian verifikasi induktif. Popper benar ketika mengatakan bahwa induksi tidak dapat memberikan kepastian absolut jika dipandang sebagai pengetahuan representasional tentang fakta eksternal.
Namun Sadra menunjukkan bahwa kepastian pengetahuan bersifat gradasional, bergantung pada tingkat kehadiran eksistensial objek dalam subjek. Semakin intens dan langsung kehadiran tersebut, semakin tinggi tingkat kepastian yang diperoleh.

Dalam kerangka ini, induksi bukanlah upaya untuk mencapai kepastian absolut tentang realitas eksternal, melainkan proses peningkatan kehadiran eksistensial antara pengamat dan fenomena yang diamati. Kepastian yang dihasilkan bersifat bertingkat, mulai dari zhonn (dugaan lemah), melalui berbagai tingkatan keyakinan, hingga mencapai yaqin (kepastian tinggi). Setiap pengulangan observasi dalam proses induktif meningkatkan intensitas kehadiran dan dengan demikian meningkatkan derajat kepastian.
Ini tidak sepenuhnya dari pandangan Popper yang melihat hipotesis hanya sebagai “belum terbantah”. Dalam pandangan Sadra, setiap konfirmasi induktif bukan sekadar ketiadaan falsifikasi, melainkan penguatan aktif dari kehadiran eksistensial yang memberikan kepastian gradasional.
Sebagai ilustrasi, dapat dipertimbangkan pengalaman seseorang yang pertama kali mendengar tentang rasa durian dari cerita orang lain. Ini adalah pengetahuan representasional dengan tingkat kepastian yang rendah. Ketika ia mencoba durian untuk pertama kali, ia memperoleh pengetahuan hadiri dengan kepastian yang lebih tinggi. Setelah mencoba sepuluh kali dengan berbagai jenis durian, kepastiannya tentang karakteristik rasa durian meningkat secara signifikan. Setelah seratus kali, ia memiliki kepastian tingkat tinggi yang berbasis pada intensitas pengalaman langsung. Ini bukan sekadar pernyataan “belum terbantah”, melainkan kepastian positif yang bertingkat berdasarkan kualitas kehadiran eksperiensial.
Al-Harakah al-Jawhariyyah (Gerak Substansial)
Prinsip ketiga yang revolusioner dalam filsafat Sadra adalah al-harakah al-jawhariyyah atau gerak substansial. Berbeda dengan filsuf sebelumnya yang hanya mengakui gerak aksidental (perubahan sifat-sifat), Sadra berpendapat bahwa substansi atau esensi segala sesuatu juga bergerak dan bertransformasi menuju kesempurnaan. Ini berlaku pula bagi pengetahuan, yang tidak bersifat statis melainkan dinamis dan evolutif.
Prinsip ini memberikan jawaban terhadap kritik Russell tentang falasi generalisasi enumeratif. Russell mengkritik induksi sebagai penghitungan sederhana yang tidak valid secara logis. Namun Sadra menunjukkan bahwa pengetahuan induktif yang sejati bukanlah akumulasi statis dari observasi individual, melainkan transformasi substansial pemahaman menuju esensi yang lebih hakiki.
Kasus ayam Russell yang salah menginduksi dapat dipahami ulang dalam kerangka ini. Kegagalan ayam bukanlah kegagalan induksi sebagai metode, melainkan kegagalan dalam pergerakan epistemik.
Ayam tersebut terjebak pada tingkat pengetahuan inderawi yang superfisial, hanya mengamati tindakan lahiriah petani tanpa bergerak menuju pemahaman yang lebih dalam tentang konteks, motif, dan tujuan. Dalam epistemologi Sadra, pengetahuan harus mengalami gerak transformatif melalui beberapa tingkatan yaitu tingkat inderawi (observasi fenomena), tingkat imajinal (pembentukan pola), tingkat rasional (pemahaman konseptual), dan tingkat intuitif atau huduri (pemahaman esensial).
Induksi yang matang adalah induksi yang tidak berhenti pada enumerasi data, melainkan bergerak naik melalui tingkatan-tingkatan pemahaman ini. Sebagai analogi, seseorang yang belajar matematika hanya dengan menghafal bahwa dua tambah dua sama dengan empat, tiga tambah tiga sama dengan enam, dan seterusnya, mirip dengan ayam Russell yang hanya mengakumulasi data.
Namun ketika ia memahami konsep penjumlahan itu sendiri, ia telah naik ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi di mana ia tidak lagi bergantung pada enumerasi kasus-kasus individual. Demikian pula, induksi dalam perspektif ini adalah gerak substansial menuju pemahaman esensial, bukan sekadar agregasi data empiris. Induksi adalah gerak substansial menuju tingkat kebenaran gradasional yang lebih tinggi.
Asholatul Wujud (Prinsipalitas Eksitensi)
Prinsip keempat dalam filsafat Sadra adalah ashalat al-wujud (أصالة الوجود) atau “primordialitas wujud” . Prinsip ini menyatakan bahwa wujud atau eksistensi adalah realitas primer dan sejati, sedangkan mahiyah atau esensi bersifat sekunder dan hanya konsep mental belaka. Dalam pandangan ini, yang benar-benar ada dan real di dunia luar adalah wujud itu sendiri, bukan esensi-esensi seperti “manusia”, “pohon”, atau “batu”.
Esensi-esensi tersebut hanyalah cara pikiran kita mengkonseptualisasikan dan mengkategorikan wujud yang kita alami. Sebagai contoh, ketika kita melihat seseorang, yang benar-benar ada secara objektif adalah wujudnya (keberadaannya), sedangkan konsep “manusia” adalah abstraksi mental yang kita gunakan untuk memahami wujud tersebut.
Prinsip ini berbeda dengan pandangan filsuf-filsuf sebelumnya seperti Ibnu Sina yang menganggap esensi sebagai realitas primer, sementara wujud hanya aksiden atau tambahan pada esensi. Bagi Sadra, membalik hierarki ini sangat penting karena membuka jalan untuk memahami bahwa semua yang ada adalah manifestasi dari satu realitas wujud yang sama, hanya berbeda dalam intensitas dan tingkatannya, bukan berbeda dalam jenis substansinya. Dengan demikian, ashalat al-wujud menjadi fondasi bagi prinsip-prinsip lain dalam filsafatnya seperti tashkik al-wujud (gradasi wujud) dan kesatuan eksistensial seluruh realitas.
Filsafat bahasa sebagai implikasi dari ashalat al-wujud menghasilkan pandangan yang sangat berbeda dari konvensionalisme linguistik modern.
Jika wujud adalah realitas primer dan esensi hanya konsep mental sekunder, maka bahasa tidak sepenuhnya arbitrer atau konvensional, melainkan memiliki relasi ontologis dengan realitas yang dideskripsikannya. Dalam perspektif ini, kata-kata dan konsep-konsep bahasa yang baik adalah yang berhasil “menangkap” atau “berpartisipasi” dalam struktur gradasi wujud itu sendiri.
Predikat atau term yang menunjuk pada sifat-sifat wujudiyyah (sifat eksistensial) yang stabil dan riil memiliki validitas ontologis lebih tinggi daripada konstruksi linguistik artifisial yang tidak berkorespondensi dengan struktur wujud. Misalnya, kata “hijau” untuk mendeskripsikan zamrud memiliki dasar ontologis karena menangkap sifat eksistensial yang stabil dalam wujud zamrud, sedangkan kata buatan seperti “grue” (hijau sebelum tahun 2100, biru sesudahnya) tidak memiliki dasar dalam realitas eksistensial dan hanya permainan logika semata. Implikasinya, makna (ma’na) dalam bahasa bukan sepenuhnya konstruksi sosial atau konvensi arbitrer, melainkan pancaran (tajalli) dari struktur wujud yang memiliki intensitas dan hirarki ontologis.
Bahasa yang lebih “benar” atau “valid” adalah bahasa yang konsep-konsepnya lebih dekat dengan dan lebih mencerminkan gradasi serta struktur wujud yang sesungguhnya. Ini menjelaskan mengapa dalam sejarah, konsep-konsep tertentu bertahan lintas budaya dan zaman (karena mereka menangkap realitas wujud yang stabil), sementara konstruksi artifisial lainnya gagal mendapat penerimaan universal (karena tidak berakar pada struktur eksistensial yang riil). Dengan demikian, filsafat bahasa Sadrian bersifat realis ontologis, bukan nominalis atau konvensionalis, di mana kebenaran bahasa diukur dari seberapa baik ia berpartisipasi dalam dan merefleksikan realitas wujud itu sendiri.
Prinsip ini memberikan jawaban terhadap paradoks Goodman tentang “grue“. Goodman menunjukkan bahwa predikat “hijau” dan “grue” sama-sama didukung oleh bukti empiris yang sama, namun memberikan prediksi berbeda. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada kriteria objektif untuk memilih di antara keduanya, sehingga induksi relatif terhadap sistem predikat yang digunakan. Namun Sadra akan berpendapat bahwa kedua predikat ini tidak setara secara ontologis.
Predikat “hijau” menunjuk kepada sifat wujudiyyah atau sifat eksistensial yang stabil dalam zamrud. Warna hijau adalah manifestasi dari struktur substansial zamrud yang real dan konsisten. Sebaliknya, “grue” adalah konstruksi linguistik artifisial yang tidak memiliki dasar dalam realitas eksistensial zamrud. Tidak ada aspek dari wujud zamrud yang “bersiap” untuk berubah menjadi biru setelah tahun 2100. Oleh karena itu, meskipun secara logis formal kedua predikat dapat dirumuskan dan didukung bukti yang sama, secara ontologis mereka tidak memiliki status yang sama.
Untuk memahami perbedaan ini, dapat dibayangkan seseorang yang menciptakan kata baru “banas” yang didefinisikan sebagai “basah jika sebelum jam dua belas siang, kering jika setelahnya”. Secara teknis, ia dapat mengatakan “handuk saya banas”. Namun tidak ada orang yang akan menggunakan kata tersebut dalam praktik karena kata itu tidak menangkap realitas yang stabil dan tidak memiliki utilitas dalam mendeskripsikan dunia. Predikat “hijau” bertahan dalam bahasa manusia selama ribuan tahun karena ia berkorespondensi dengan realitas eksistensial yang stabil. Predikat “grue” tidak akan bertahan karena ia tidak memiliki dasar ontologis.
Dengan demikian, Sadra menunjukkan bahwa induksi yang valid adalah induksi yang menggunakan konsep-konsep yang berakar pada struktur wujud, bukan konstruksi arbitrer. Ada kriteria objektif untuk memilih hipotesis induktif, yaitu seberapa baik konsep-konsep yang digunakan mencerminkan gradasi dan struktur realitas eksistensial. Ini bukan relativisme linguistik, melainkan realisme ontologis yang mengakui bahwa bahasa dan konsep yang baik adalah yang berpartisipasi dalam dan mencerminkan struktur wujud itu sendiri.
Al-‘Aql al-Kulli (Akal Universal)
Berikutnya adalah konsep al-‘aql al-kulli atau Akal Universal dalam filsafat Sadra. Ini merupakan prinsip intelektif kosmik yang menjadi sumber dan horizon kesatuan pengetahuan. Akal Universal ini adalah realitas intermedial antara Yang Mutlak dan dunia partikular, dan merupakan wadah bagi forma-forma universal dan prinsip-prinsip eksistensial yang mendasari keteraturan kosmos.
Prinsip ini memberikan jawaban terhadap kritik Kuhn tentang relativitas paradigmatik dari induksi. Kuhn menunjukkan bahwa ilmuwan melakukan induksi dalam konteks paradigma tertentu, dan pergeseran paradigma mengubah cara interpretasi data. Ia menyimpulkan bahwa sains tidak berkembang secara kumulatif dan objektif, melainkan melalui revolusi yang bersifat tidak rasional sepenuhnya. Namun bagi Sadra, pergeseran paradigma tidak berarti relativisme epistemologis, melainkan refleksi dari tingkatan partisipasi manusia yang berbeda terhadap Akal Universal.
Fisika Newton dan fisika Einstein, misalnya, tidak saling meniadakan secara mutlak. Keduanya adalah tajalli atau manifestasi dari tingkatan Akal Universal yang berbeda. Fisika Newton merupakan pencerahan pada tingkat fenomenal yang lebih lahiriah, sementara fisika Einstein merupakan pencerahan pada tingkat struktural yang lebih dalam.
Keduanya valid pada tingkatannya masing-masing, dan revolusi ilmiah dari Newton ke Einstein bukanlah penggantian kebenaran dengan kebenaran yang berbeda, melainkan tasa’ud epistemik atau kenaikan gradasional dalam struktur pengetahuan yang berpartisipasi dengan tingkat Akal Universal yang lebih tinggi.
Sebagai ilustrasi, dapat dibayangkan seseorang yang melihat sebuah gunung dari kejauhan. Gunung tersebut tampak kecil dan berwarna biru karena efek atmosferik. Ini adalah satu “paradigma” persepsi. Kemudian ia mendaki dan sampai di puncak gunung tersebut. Sekarang ia melihat bahwa gunung itu besar, terdiri dari berbagai jenis batuan, ditumbuhi pepohonan, dan seterusnya. Ini adalah “paradigma” persepsi yang berbeda. Kedua paradigma ini tidak saling meniadakan, melainkan merupakan tingkatan kebenaran yang berbeda tentang realitas yang sama. Paradigma pertama tidak salah, tetapi parsial dan superfisial. Paradigma kedua lebih komprehensif dan mendalam.
Demikian pula, dalam perkembangan sains, setiap paradigma merepresentasikan tingkat partisipasi terhadap Akal Universal. Induksi yang dilakukan dalam setiap paradigma adalah valid pada tingkatannya, dan revolusi ilmiah adalah proses tadrij atau gradasi menuju pencerahan yang lebih tinggi. Ini bukan relativisme di mana semua paradigma setara, melainkan hirarki epistemik di mana paradigma yang lebih tinggi mencakup dan melampaui paradigma yang lebih rendah. Dengan demikian, Kuhn benar bahwa induksi tidak objektif dalam pengertian netral-paradigmatik, tetapi Sadra menunjukkan bahwa ini tidak berarti subjektivisme atau relativisme, melainkan gradualitas dalam pencapaian kebenaran.
Beberapa Catatan Penutup
Tulisan ini berupaya menjawab problema induksi berbasis filsafat Mulla Sadra.
Lima kritik tajam terhadap induksi terhadap induksi dapat dipahami ulang dan dijawab tanpa ditolak secara total melalui kerangka ontologis dan epistemologis yang komprehensif.
Hume benar bahwa tidak ada pembuktian logis formal untuk validitas induksi, namun Sadra menunjukkan bahwa validitas induksi tidak terletak pada logika formal melainkan pada keteraturan ontologis wujud yang bertingkat. Popper benar bahwa verifikasi induktif tidak dapat memberikan kepastian absolut, namun filsafat Sadra mengindikasikan bahwa kepastian bersifat gradasional berdasarkan intensitas kehadiran eksistensial. Russell benar bahwa enumerasi sederhana adalah falasi, namun filsafat Sadra memberikan alternatif wacana bahwa induksi sejati adalah gerak substansial menuju pemahaman esensial. Goodman benar bahwa pilihan predikat mempengaruhi induksi, namun dalam kerangka fikir filsafat Sadra ada kriteria ontologis untuk membedakan predikat yang valid dari yang artifisial. Kuhn benar bahwa induksi terikat paradigma, namun dalam kerangka fikir filsfat Sadra paradigma bisa dipandang tingkatan partisipasi terhadap Akal Universal, bukan relativisme sewenang-wenang.
Sintesis dari kelima respons ini dapat dirumuskan dalam prinsip fundamental filsafat Sadra bahwa pengetahuan adalah gerak dari yang eksternal menuju yang internal, dari yang manifes menuju yang tersembunyi. Induksi, dalam kerangka ini, bukanlah semata-mata metode logis untuk menyusun proposisi umum dari proposisi partikular, melainkan proses ontologis-epistemologis di mana subjek pengenal berpartisipasi dalam keteraturan eksistensial realitas. Setiap langkah dalam proses induktif merupakan gradasi dalam kesatuan eksistensial antara akal manusia dan struktur kosmos.
Maka induksi bukanlah metode yang total tertolak dalam epistemologi, melainkan bisa menjadi jalan yang sahih untuk menaiki tangga kebenaran secara bertahap bila dipahami dalam kerangka pikir yang tepat. Dari tingkat pengetahuan zhonni atau dugaan, melalui tingkatan-tingkatan keyakinan yang semakin kuat, menuju yaqin atau kepastian tinggi, dan pada puncaknya mencapai pengetahuan huduri atau kehadiran langsung yang merupakan puncak epistemologi Sadra.
Induksi adalah manifestasi dari gerak substansial pengetahuan, dari dunia empiris partikular menuju pemahaman universal, dari fenomena lahiriah menuju esensi batiniah.
Dengan demikian, dalam perspektif hikmah muta’aliyah Mulla Sadra, induksi mungkin dapat didefinisikan ulang sebagai gerak epistemik dalam gradasi wujud yang memantulkan keteraturan eksistensial, bukan sekadar kebiasaan psikologis atau agregasi data empiris. Induksi, alih-alih gagal memberikan kepastian, justru membangun jalan menuju kepastian yang bertingkat-tingkat, di mana logika, ontologi, dan pengalaman bersatu dalam satu proses integral menuju hikmah atau kebijaksanaan yang tinggi. Barangkali hal ini bisa menjadi kontribusi filsafat Sadra dalam menafsirkan ulang problem induksi yang telah menjadi perdebatan panjang dalam tradisi filsafat Barat.
👤 Dr. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng., Sekretaris Dewan Syura IJABI; Dosen STEI ITB.