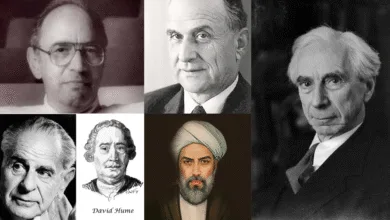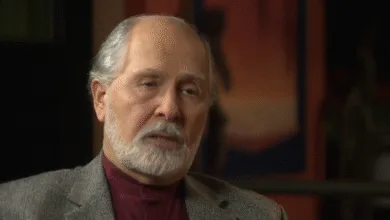Islam dan Moralitas: Integrasi Etika dan Syariat
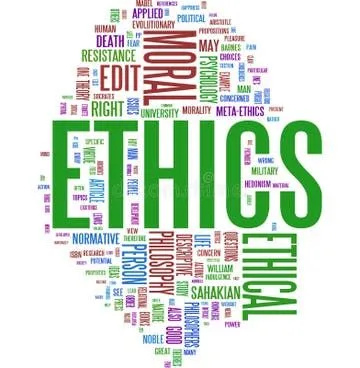
Oleh Mohammad Adlany, Ph.D. (Anggota Dewan Syura IJABI)
Dalam Islam, moralitas bukanlah sekadar ajaran etika yang berdiri sendiri, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari syariat. Syariat, yang secara harfiah berarti “jalan menuju sumber air”, adalah seperangkat aturan Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Namun, hakikat syariat bukan hanya sekadar kumpulan hukum formal, melainkan sarana untuk menumbuhkan akhlak mulia dan membentuk manusia bermoral. Moralitas sejati tidak bisa dilepaskan dari syariat. Hal ini karena syariat berfungsi sebagai jalan praktis yang menuntun manusia kepada pembentukan akhlak. Tanpa syariat, moralitas hanya menjadi konsep abstrak yang rapuh dan relatif.
Rasulullah saw bersabda:
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (Al-Kāfī, jil. 2, hlm. 99)
Hadis ini menegaskan misi utama kerasulan Nabi Muhammad saw, yakni membimbing manusia menuju kesempurnaan moral. Wahyu, syariat, dan seluruh risalah Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menanamkan, melindungi, dan menyempurnakan akhlak mulia dalam diri manusia. Dengan demikian, akhlak bukanlah sesuatu yang sekunder, melainkan inti dari risalah Islam. Rasulullah saw diutus bukan hanya untuk menegakkan syariat lahiriah, tetapi juga untuk menghidupkan nilai-nilai batiniah yang memurnikan hati dan perilaku manusia. Dengan demikian, syariat bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menanamkan akhlak mulia.
Syariat mencakup aspek ibadah, muamalah, dan akhlak. Dimensi ibadah, seperti salat dan puasa, tidak hanya ritual, melainkan pendidikan moral. Fungsi utama ibadah adalah pembentukan akhlak. Begitu juga dengan zakat dan sedekah yang berorientasi pada keadilan sosial dan empati, atau haji yang menanamkan kesetaraan, kerendahan hati, serta persaudaraan universal. Dengan demikian, setiap aspek syariat memiliki implikasi moral yang mendalam.
Imam Ali as menegaskan hubungan antara ibadah, syariat, dan akhlak:
ثَمَرَةُ الْعِبَادَةِ الْعِصْمَةُ
“Buah dari ibadah adalah penjagaan (dari dosa).” (Ghurar al-Ḥikam, hadis no. 1453)
لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا أَدَبَ مَعَهُ، وَلَا خَيْرَ فِي أَدَبٍ لَا دِين مَعَهُ
“Tidak ada kebaikan pada agama yang tidak disertai akhlak, dan tidak ada kebaikan pada akhlak yang tidak disertai agama.” (Nahj al-Balāghah, ḥikmah no. 31)
Ungkapan ini menunjukkan dua hal: (1) agama yang dijalankan tanpa akhlak hanyalah formalitas, dan (2) akhlak yang tidak didasari syariat tidak memiliki pijakan transenden. Dengan kata lain, kesempurnaan moral hanya dapat dicapai melalui ketaatan terhadap syariat yang benar dan ikhlas.
Imam Ja‘far al-Shadiq as juga menegaskan hubungan erat ini:
لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: حِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ، وَوَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ، وَحُسْنُ خُلُقٍ يُعَاشِرُ بِهِ النَّاسَ
“Seorang hamba tidak akan menjadi mukmin sejati sampai ia memiliki tiga sifat: kesabaran yang dapat menahan kebodohan orang jahil, ketakwaan yang mencegahnya dari maksiat kepada Allah, dan akhlak yang baik yang dengannya ia bergaul dengan manusia.” (Al-Kāfī, jil. 2, hlm. 107)
Hadis ini menegaskan bahwa amal syariat bukan tujuan akhir, melainkan instrumen yang harus berbuah pada moralitas luhur. Ketika syariat dijalankan dengan benar, ia melatih jiwa untuk tunduk pada disiplin ilahi, sehingga membentuk karakter yang konsisten dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih sayang.
Dalam riwayat lain yang senada, beliau bersabda:
لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ فِعْلُهُ أَرْجَحَ مِنْ قَوْلِهِ، وَخُلُقُهُ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ
“Seorang hamba tidak akan menjadi mukmin sejati hingga amalnya lebih utama daripada ucapannya, dan akhlaknya lebih baik daripada amalnya.” (Al-Kāfī, jil. 2, hlm. 107)
Seorang Muslim sejati diukur bukan hanya dari ritual yang ia lakukan, tetapi sejauh mana ia memancarkan akhlak mulia dalam interaksi sosial: jujur dalam ucapan, adil dalam keputusan, rendah hati, dermawan, dan penuh kasih.
Inti dari syariat adalah akhlak yang baik. Syariat bukan sekadar aturan, tetapi “pendidikan ruhani” yang melahirkan akhlak mulia. Imam Ali as berkata:
إِنَّ الدِّينَ هُوَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ
“Agama (syariat) itu tidak lain adalah akhlak yang baik.” (Ghurar al-Ḥikam wa Durar al-Kalim, hlm. 38)
Imam Ja‘far al-Shadiq as menegaskan:
مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ امْرِئٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ
“Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik.” (Al-Kāfī, jil. 2, hlm. 99)
Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan ini sejatinya adalah pilar moralitas. Menjaga jiwa berarti menegakkan penghormatan terhadap kehidupan; menjaga akal berarti menolak segala bentuk kebodohan dan manipulasi; menjaga keturunan berarti melindungi martabat keluarga dan generasi; menjaga harta berarti menegakkan keadilan ekonomi. Dengan demikian, tujuan syariat pada hakikatnya merupakan cetak biru moralitas Islam dalam kehidupan individu dan sosial.
Al-Ghazali menafsirkan syariat sebagai jalan penyucian jiwa dan pengendalian hawa nafsu agar manusia layak menerima cahaya Ilahi dan mampu berakhlak mulia. Syariat adalah penjaga lahiriah, sementara moralitas adalah buah batiniah yang dihasilkan darinya. (Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn, jilid 3, hlm. 53)
Ibn Arabi menghubungkan syariat dengan hakikat, bahwa hukum-hukum lahiriah hanyalah sarana menuju penyempurnaan batin yang terwujud dalam akhlak yang merupakan tajalli atau cermin sifat-sifat Allah dalam diri manusia. Syariat sebagai pintu masuk menuju realitas batin. (Al-Futūḥāt al-Makkiyyah, jilid 2, hlm. 295)
Mulla Sadra menekankan bahwa syariat, tarekat, dan hakikat adalah satu kesatuan yang bertingkat: syariat adalah tahap awal yang membimbing manusia menuju kesempurnaan eksistensial, yaitu akhlak ilahiah. (Al-Asfār al-Arba‘ah, jilid 9, hlm. 182)
Imam Khomeini menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah transformasi moral, bukan sekadar pelaksanaan hukum lahiriah. (Arba‘ūn Hadīthan, hadis ke-20, hlm. 155)
Ketika syariat dijalankan tanpa kesadaran moral, ia berpotensi kehilangan ruhnya. Puasa tanpa akhlak hanya menjadi penderitaan jasmani, zakat tanpa niat ikhlas hanya menjadi transaksi sosial, dan hukum tanpa keadilan hanya menjadi penindasan. Dengan demikian, moralitas adalah jiwa dari syariat.
Dari perspektif Islam, kesempurnaan moral tidak dapat dicapai tanpa pelaksanaan syariat yang baik dan benar. Syariat bertindak sebagai kerangka lahiriah yang menjaga manusia dari penyimpangan, sekaligus sebagai latihan praktis untuk menumbuhkan akhlak batiniah.
Seorang Muslim mungkin saja memiliki sifat-sifat baik secara natural, tetapi sifat tersebut baru mencapai kesempurnaan ketika ia dijalankan dalam kerangka syariat. Misalnya, sifat dermawan menjadi sempurna ketika disalurkan melalui zakat dan sedekah sesuai aturan syariat; kesabaran mencapai puncaknya melalui latihan puasa; kerendahan hati mencapai makna terdalamnya melalui shalat dan sujud di hadapan Allah.
Dengan demikian, syariat bukanlah beban formalistik, melainkan jalan yang memastikan moralitas manusia tidak tercerabut dari akar spiritualnya. Tanpa syariat, moralitas akan kehilangan orientasi transenden; sebaliknya, syariat yang tidak melahirkan moralitas adalah syariat yang gagal dipahami esensinya.
Islam memandang moralitas sebagai inti dari agama, dan syariat sebagai jalannya. Ahlulbait menegaskan bahwa moralitas tidak mungkin sahih dan sempurna tanpa syariat yang dijalankan secara baik dan benar.
Moralitas sejati hanya dapat dicapai dengan fondasi syariat, pendalaman spiritual, dan refleksi Ilahi. Tanpa syariat, moralitas mudah jatuh ke dalam relativisme
Islam menawarkan visi moralitas yang utuh, transenden, dan kontekstual. Utuh, karena menyatukan syariat, akhlak, dan spiritualitas. Transenden, karena berorientasi kepada Allah sebagai sumber moral. Dan kontekstual, karena dapat diterapkan dalam realitas sosial dengan tetap menjaga prinsip universalnya.
Akhirnya, kesempurnaan moralitas seorang Muslim bukan hanya diukur dari seberapa patuh ia menjalankan ritual syariat, tetapi sejauh mana syariat itu berbuah akhlak yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, syariat adalah akar, moralitas adalah buah; tanpa akar pohon akan mati, dan tanpa buah pohon kehilangan maknanya.
Kesimpulan: Islam memandang moralitas sebagai inti dari agama, sementara syariat adalah jalannya. Kesempurnaan moral tidak mungkin tercapai kecuali dengan pelaksanaan syariat secara baik dan benar. Oleh karena itu, seorang Muslim sejati adalah mereka yang menjalankan syariat dengan kesadaran penuh sehingga melahirkan akhlak yang mulia.
Syariat dan moralitas dalam Islam bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Syariat berfungsi sebagai jalan formal yang mengatur perilaku manusia, sementara moralitas adalah tujuan substansialnya. Ibadah, hukum, dan muamalah dalam Islam pada hakikatnya bertujuan membentuk manusia berakhlak mulia, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw dan Ahlulbait. Oleh sebab itu, memahami syariat tanpa moralitas hanya melahirkan formalitas kosong, sementara moralitas tanpa syariat kehilangan pijakan wahyu. Keselarasan keduanya adalah kunci kesempurnaan hidup Islami.