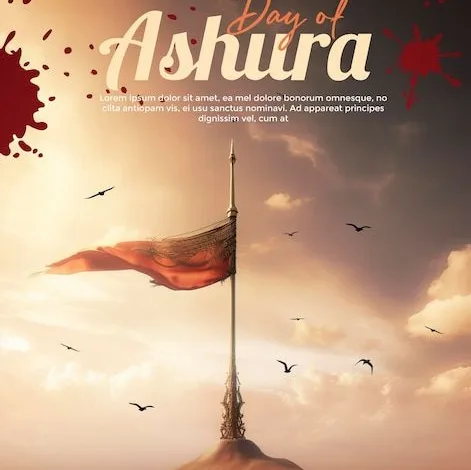
Oleh Mohammad Adlany, Ph.D, Anggota Dewan Syura IJABI
Cinta itu menguatkan dan solidaritas itu menyatukan. Karbala adalah tragedi dan cahaya sekaligus. Di dalamnya bukan hanya terukir keberanian dan pengorbanan, tetapi juga cinta yang tulus dan solidaritas yang menggetarkan hati antara para pejuang kebenaran. Imam Husain as dan para sahabatnya bukan sekadar pemilik prinsip, tetapi juga saudara dalam perjuangan yang saling menguatkan hingga detik-detik terakhir.
Kisah mereka mengajarkan bahwa perjuangan tidak hanya butuh kebenaran, tetapi juga cinta di antara para pencinta kebenaran itu sendiri.
Al-Qur’an menegaskan bahwa ikatan sejati tidak dibangun atas dasar dunia, tapi atas dasar iman:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ…
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.” (QS. Al-Hujurat: 10)
Ayat ini menemukan makna paling hidupnya di Karbala. Di sana, kita menyaksikan bagaimana para sahabat Imam Husain memperlakukan satu sama lain dengan kasih sayang dan keberanian yang saling meneguhkan, bukan dengan ego dan perhitungan duniawi.
Imam Husain as adalah pemimpin yang menyayangi para sahabatnya. Imam Husain as tidak memperlakukan pengikutnya sebagai bawahan, tetapi sebagai keluarga dan saudara seiman. Beliau mengajak bicara dengan kelembutan, menyebut mereka dengan penuh cinta, dan bahkan ketika malam Asyura tiba, beliau berkata:
“Pergilah kalian semua, aku izinkan. Mereka hanya menginginkan aku. Aku tidak ingin kalian terbunuh.” (Bihar al-Anwar, jil. 44, hal. 293)
Namun apa jawaban para sahabatnya? Mereka menangis dan menolak pergi. Salah satunya berkata:
“Wahai putra Rasulullah! Apakah kami akan hidup setelah engkau dibunuh? Demi Allah, itu tak mungkin!”
Ini bukan sekadar kesetiaan. Ini adalah solidaritas ruhani: sebuah cinta yang tidak memikirkan keselamatan pribadi, tetapi keberpihakan pada kebenaran dan pemiliknya.
Abul Fadhl al-Abbas, saudara Imam Husain as, dikenal karena keberaniannya. Tapi lebih dari itu, ia dikenal karena cintanya. Saat hendak mengambil air untuk anak-anak, ia tidak meminumnya, karena teringat bahwa Husain as dan keluarga kehausan. Ketika tangannya tertebas, ia berkata:
والله إن قطعتموا يميني، إني أحامي أبدًا عن ديني، وعن إمام صادق اليقين.
“Demi Allah, meski kalian telah memotong tangan kananku, aku akan tetap membela agamaku, dan imanku kepada imamku yang yakin.”
Ali Akbar, putra Imam Husain as, dengan penuh cinta berkata:
“Wahai Ayah, bukankah kita berada di atas kebenaran?”
Ketika dijawab, “Ya, wahai anakku,” ia berkata: “Maka kami tak peduli apakah kita mati atau mereka yang mati.”
Zuhair bin Qain dan Hurr, dua orang dari latar belakang yang berbeda, akhirnya bersatu karena kebenaran. Ketika Hurr bertaubat dan bergabung dengan Imam Husain, tidak ada sikap sinis dari sahabat lainnya. Yang ada hanyalah pelukan persaudaraan dan pengampunan.
Solidaritas itu adalah nagian dari iman. Imam Ja‘far Shadiq as berkata:
المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى.
“Mukmin adalah saudara bagi mukmin lain, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya.” (Al-Kafi, jil. 2, hal. 166)
Inilah solidaritas yang hidup dalam Karbala. Saat satu orang terluka, yang lain tidak mundur. Mereka berdiri bersama hingga akhir, bukan karena ingin dikenal sejarah, tetapi karena mereka mencintai satu sama lain karena Allah.
Dalam Ziarah Asyura, kita membaca:
اللهم اجعلني عندك وجيهًا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين.
Doa ini menunjukkan bahwa keinginan tertinggi seorang pecinta kebenaran adalah bisa bersama para pecinta lainnya, hidup dan mati dalam jalan yang sama.
Kita yang mengaku mencintai kebenaran dan keadilan perlu meneladani cinta dan solidaritas para pejuang Karbala. Dunia saat ini penuh dengan orang yang ingin benar sendirian dan menjatuhkan sesama pejuang hanya karena perbedaan kecil. Padahal Karbala mengajarkan: cinta sesama pejuang adalah kekuatan moral, solidaritas adalah benteng yang melindungi perjuangan, dan berjuang bersama lebih kuat daripada berjuang sendiri.
Marilah kita bangun Karbala di hati kita. Jika kita ingin menjadi Husaini sejati, kita harus menghidupkan nilai cinta dan solidaritas di antara para pejuang kebenaran. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling curiga. Mari saling menopang seperti Abbas dan Husain, seperti Ali Akbar dan para sahabat. Sebab perjuangan tidak bisa dimenangkan oleh orang yang berjalan sendiri, tapi oleh barisan orang yang saling mencintai karena Allah.







