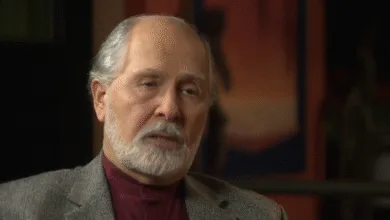Oleh Mohammad Adlany, Ph.D. (Anggota Dewan Syura IJABI)
Salah satu hadis yang sering dikutip dalam literatur etika, tasawuf, dan filsafat Islam adalah sabda Nabi Muhammad saw:
النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا
“Manusia itu tertidur, ketika mereka mati barulah mereka terbangun.” (Al-Majlisī, Bihār al-Anwār jilid 4, hlm. 43)
Hadis ini menggambarkan kehidupan dunia sebagai kondisi “tidur” panjang, sedangkan kematian merupakan “kebangkitan” menuju kesadaran sejati.
Tidur adalah keadaan sementara. Dalam mimpi, manusia menyaksikan berbagai citra dan pengalaman yang tampak nyata, namun ketika terbangun, ia mendapati semua itu hilang. Analogi inilah yang digunakan Nabi untuk menjelaskan hakikat dunia.
Al-Qur’an menegaskan:
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
“Ia mengira bahwa hartanya membuatnya kekal.” (QS. al-Humazah [104]: 3)
Manusia kerap terjebak pada ilusi kekekalan duniawi. Namun, pada saat sakaratul maut, ia mendapati tangannya kosong. Semua yang selama ini dipandang permanen ternyata hanyalah bayangan sementara.
Dalam Nahj al-Balāghah, Imam Ali as berkata:
اليومَ عملٌ ولا حسابٌ، وغداً حسابٌ ولا عملٌ
“Hari ini adalah (waktu) amal tanpa hisab, sedangkan esok adalah (waktu) hisab tanpa amal.” (Khutbah 42)
Ungkapan ini senada dengan hadis Nabi saw tadi. Dunia adalah tempat “bermimpi” sekaligus “beramal”, sementara akhirat adalah saat “terbangun” sekaligus “menyadari” segala amal, namun tanpa lagi kesempatan memperbaikinya.
Ibn ‘Arabī memandang dunia sebagai ‘ālam al-khayāl (alam imajinasi). (al-Futūḥāt al-Makkiyyah, jilid 2, hlm. 323)
Segala sesuatu di dunia adalah tajallī (penampakan) yang memiliki realitas relatif, mirip dengan mimpi.
Menurutnya, kehidupan duniawi tidak bisa dipandang sebagai realitas mutlak, sebab hakikat segala sesuatu hanya jelas ketika manusia berjumpa dengan al-Ḥaqq (Tuhan).
Pandangan ini selaras dengan hadis “al-nās niyām…”, yakni bahwa manusia belum sepenuhnya “bangun” selama berada di dunia.
Mullā Ṣadrā, filsuf Syiah terkemuka, menjelaskan bahwa kematian adalah taḥawwul wujūdī (transformasi eksistensial). (Al-Asfār al-Arba‘ah, jilid 9, hlm. 13–15)
Jiwa manusia yang selama di dunia terikat pada tubuh dan khayalan, pada saat kematian memasuki tahap kesadaran baru.
Bagi Ṣadrā, kehidupan dunia adalah bentuk wujūd khayālī (eksistensi imajinatif), sedangkan kematian menyingkap realitas lebih tinggi—yakni alam mitsal dan kemudian alam akal. Dengan demikian, hadis Nabi saw mencerminkan filsafat eksistensialis Islami: tidur = eksistensi rendah, mati = kesadaran lebih sempurna.
Jika kematian adalah saat terbangunnya kesadaran, maka manusia bijak tidak menunggu sampai kematian untuk menyadarinya. Nabi saw bersabda:
حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا
“Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab (oleh Allah).” (Al-Tirmidhī, Sunan, hadis no. 2459)
Konsep muḥāsabah (introspeksi) adalah cara untuk “bangun” sejak di dunia, bukan sekadar menunggu kematian. Dengan evaluasi diri, manusia dapat memutus belenggu ilusi duniawi dan mengorientasikan dirinya pada realitas yang abadi.
Kesimpulan, hadis “al-nās niyām…” membuka cakrawala pemahaman bahwa dunia adalah tidur panjang yang penuh ilusi, dan kematian adalah momen terbangunnya kesadaran. Ibn ‘Arabī menafsirkan dunia sebagai alam imajinasi, sementara Mullā Ṣadrā menegaskannya sebagai tahap eksistensi rendah yang ditransformasikan menuju realitas lebih tinggi.
Dengan demikian, hadis ini tidak sekadar bersifat etis, melainkan juga metafisis. Ia mengajarkan bahwa kesadaran sejati hanya diperoleh ketika manusia melampaui tidur panjang dunia, baik melalui kematian maupun melalui muḥāsabah dan penghayatan spiritual sejak di dunia.