Satya
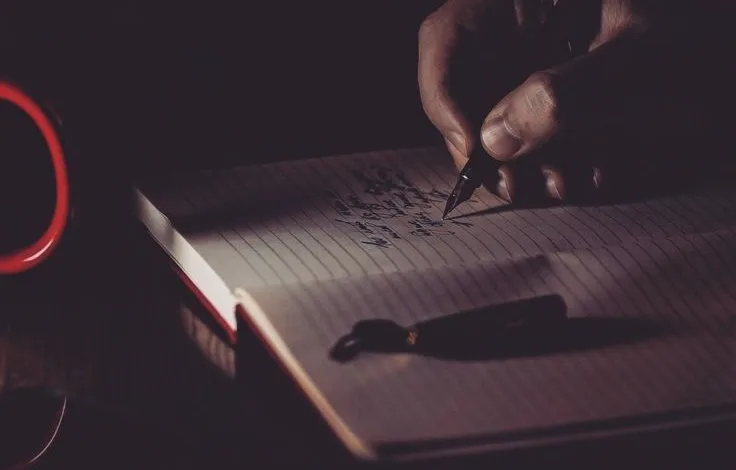
Oleh Abdul Karim
“Truth is not comfortable; it is the fire that burns the illusions we cradle.”
Manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari tempat bernaung dari ketidakpastian. Kenyamanan, dalam segala bentuknya, adalah pelarian halus dari keterbukaan terhadap realitas yang tidak selalu ramah. Di sinilah paradoks itu lahir: semakin kita mencintai kenyamanan, semakin kita menolak kebenaran. Sebab kebenaran bukanlah bantal empuk tempat kita berbaring; ia adalah cermin yang memaksa kita menatap luka, keterbatasan, dan ketelanjangan eksistensi. Dalam ketegangan ini, terlihat bahwa kenyamanan bukan sekadar kondisi fisik, melainkan konstruksi mental yang menyingkirkan apa pun yang mengganggu rasa aman. Dan di balik itu, tersembunyi sebuah penolakan yang dalam—penolakan terhadap kenyataan yang menuntut keberanian untuk melihat apa adanya.
Orang yang mencintai kenyamanan membangun benteng dari kebiasaan, sistem nilai yang tak pernah digugat, dan rutinitas yang membius. Namun, kebenaran tidak tinggal di dalam benteng itu; ia mengetuk pintu dengan membawa badai. Hubungan antara kenyamanan dan kebencian pada kebenaran bukanlah kebetulan, tetapi konsekuensi logis dari psikologi manusia. Kenyamanan menciptakan zona di mana tidak ada tantangan, dan di situlah kebenaran menjadi ancaman. Bukan karena kebenaran itu kejam, tetapi karena ia menuntut transformasi. Orang yang menolak diguncang akan selalu membenci suara yang memanggilnya keluar.
Dalam ruang batin manusia, kenyamanan sering kali menjadi topeng dari ketakutan terdalam. Ada rasa panik eksistensial yang tersembunyi: kesadaran akan kefanaan, akan rapuhnya makna yang kita susun. Dari sini muncul kebutuhan untuk menutup mata. Kenyamanan menawarkan anestesi, dan ketika anestesi itu bekerja, kebenaran tampak seperti racun. Inilah sebabnya mengapa sebuah masyarakat yang terlalu mencintai kestabilan sering kali justru melahirkan kebisuan moral. Ketika rasa aman dijadikan nilai tertinggi, kebenaran akan menjadi pengacau yang harus disingkirkan.
Kenyamanan juga memiliki wajah kolektif. Ia membentuk sistem sosial yang lebih peduli menjaga harmoni semu daripada menggali realitas. Dalam dunia yang mengutamakan kesenangan dan kestabilan, kebenaran menjadi subversif. Ia mengganggu keteraturan, mengancam struktur yang sudah mapan. Kenyamanan sosial, dalam bentuk utopia buatan, menuntut kepatuhan, bukan pencarian. Maka tidak heran jika kebenaran dihadapi bukan dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan kebencian. Bukan karena manusia tidak mengenalnya, tetapi karena kebenaran mengingatkan pada sesuatu yang telah diputuskan untuk dilupakan: kebebasan untuk menanggung ketidakpastian.
Namun, ada sesuatu yang lebih dalam. Kebencian pada kebenaran lahir bukan hanya dari rasa takut, tetapi juga dari rasa kehilangan identitas yang melekat pada kenyamanan. Ketika kenyamanan menjadi pusat hidup, diri pun menyatu dengannya. Kebenaran yang datang menghancurkan kenyamanan tidak hanya dianggap musuh, tetapi juga pembunuh eksistensi. Mengguncang kenyamanan berarti meruntuhkan bangunan ego yang dibangun di atasnya. Di sinilah tragedinya: orang tidak sekadar menolak kebenaran, mereka melawannya dengan kebencian karena kebenaran mengancam membongkar diri yang mereka kenal.
Di tingkat eksistensial, kecintaan pada kenyamanan adalah bentuk halus dari penyangkalan akan kematian. Dalam diam, manusia menyusun ilusi abadi dari rutinitas, hubungan, dan sistem kepercayaan yang menenangkan. Kenyamanan berfungsi seperti perisai yang menutupi fakta paling mendasar: bahwa hidup rapuh, bahwa semua yang kita genggam akan hilang. Ketika kebenaran datang membawa pesan ini, ia mematahkan ilusi. Reaksi spontan terhadapnya bukanlah penerimaan, tetapi penolakan yang lahir dari rasa takut kehilangan segalanya. Kebencian pun lahir sebagai mekanisme bertahan hidup, meskipun justru menghalangi kehidupan yang autentik.
Ada momen ketika kenyamanan mencapai titik di mana ia tidak lagi melindungi, melainkan membunuh perlahan. Dalam ruang itu, kebenaran menjadi satu-satunya obat pahit. Namun, obat pahit ini tidak pernah terasa manis di awal. Orang yang terlalu mencintai kenyamanan tidak melihat kebenaran sebagai penyembuh, melainkan sebagai algojo. Ironinya, dalam kebencian terhadap kebenaran, manusia justru menutup pintu pada kebebasan sejati. Sebab kebebasan hanya lahir ketika kita berani berdiri di hadapan realitas tanpa penyangkalan.
Kenyamanan memiliki daya hipnosis. Ia membuat kita percaya bahwa kita hidup, padahal kita hanya berjalan di dalam mimpi yang diciptakan rasa takut. Kebenaran, dengan segala keterbukaannya, adalah panggilan untuk terbangun. Tetapi kebangkitan itu menyakitkan. Tidak heran jika orang lebih memilih bantal empuk ilusi daripada dinginnya udara pagi kesadaran. Dalam setiap jiwa, ada tarik-menarik antara dua kekuatan ini: dorongan untuk tetap tertidur dalam hangatnya kenyamanan dan panggilan untuk membuka mata terhadap kebenaran.
Namun, kebenaran bukanlah musuh kenyamanan itu sendiri; ia musuh dari kenyamanan yang membeku menjadi penjara. Ada bentuk kenyamanan yang lahir setelah kebenaran diterima—kenyamanan yang bukan ilusi, melainkan kedamaian setelah pergulatan. Untuk mencapainya, seseorang harus melewati kebencian awal, harus rela melepaskan pegangan lama. Di sinilah keberanian manusia diuji. Apakah ia akan memilih tetap terbius dalam kehangatan palsu, ataukah berani menghadapi rasa dingin yang menyalakan hidup?
Masyarakat yang membenci kebenaran adalah cermin dari individu-individu yang takut menghadapi dirinya sendiri. Ketika cinta terhadap kenyamanan menjadi agama, segala bentuk suara yang mengganggu akan dibungkam. Tetapi sejarah menunjukkan, kebenaran selalu menemukan jalan. Ia tidak bisa dibunuh oleh kebencian; ia hanya bisa ditunda. Pada akhirnya, kebenaran akan merobek tirai kenyamanan yang rapuh, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membebaskan.
Tema ini bukan sekadar abstraksi filosofis; ia hadir dalam setiap pilihan sehari-hari. Saat kita menolak mendengar kritik karena membuat tidak nyaman, saat kita menghindari percakapan jujur karena takut melukai, saat kita berdiam dalam rutinitas yang mematikan jiwa demi rasa aman—di situlah kebencian pada kebenaran tumbuh. Setiap kali kita memilih kenyamanan daripada kejujuran pada diri sendiri, kita sedang melatih hati untuk memusuhi kebenaran.
Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali menghantui: apakah kita berani mencintai kebenaran lebih dari kenyamanan? Kebenaran tidak menjanjikan rasa aman; ia hanya menawarkan keaslian. Dalam dunia yang semakin terobsesi dengan stabilitas, jawaban terhadap pertanyaan ini akan menentukan arah hidup kita. Orang yang memilih kenyamanan mungkin menemukan ketenangan sesaat, tetapi orang yang memilih kebenaran menemukan kehidupan itu sendiri. Dan mungkin, di titik itu, kenyamanan yang sejati baru bisa lahir—bukan dari pelarian, tetapi dari keberanian untuk melihat segala sesuatu apa adanya.
Daftar Pustaka
Camus, Albert. The Rebel: An Essay on Man in Revolt. New York: Vintage Books, 1956.
Huxley, Aldous. Brave New World. London: Chatto & Windus, 1932.
Becker, Ernest. The Denial of Death. New York: Free Press, 1973.

Abdul Karim
Guru matematika SMUTH 2000 - 2005 dan praktisi pendidikan matematika dan IT






